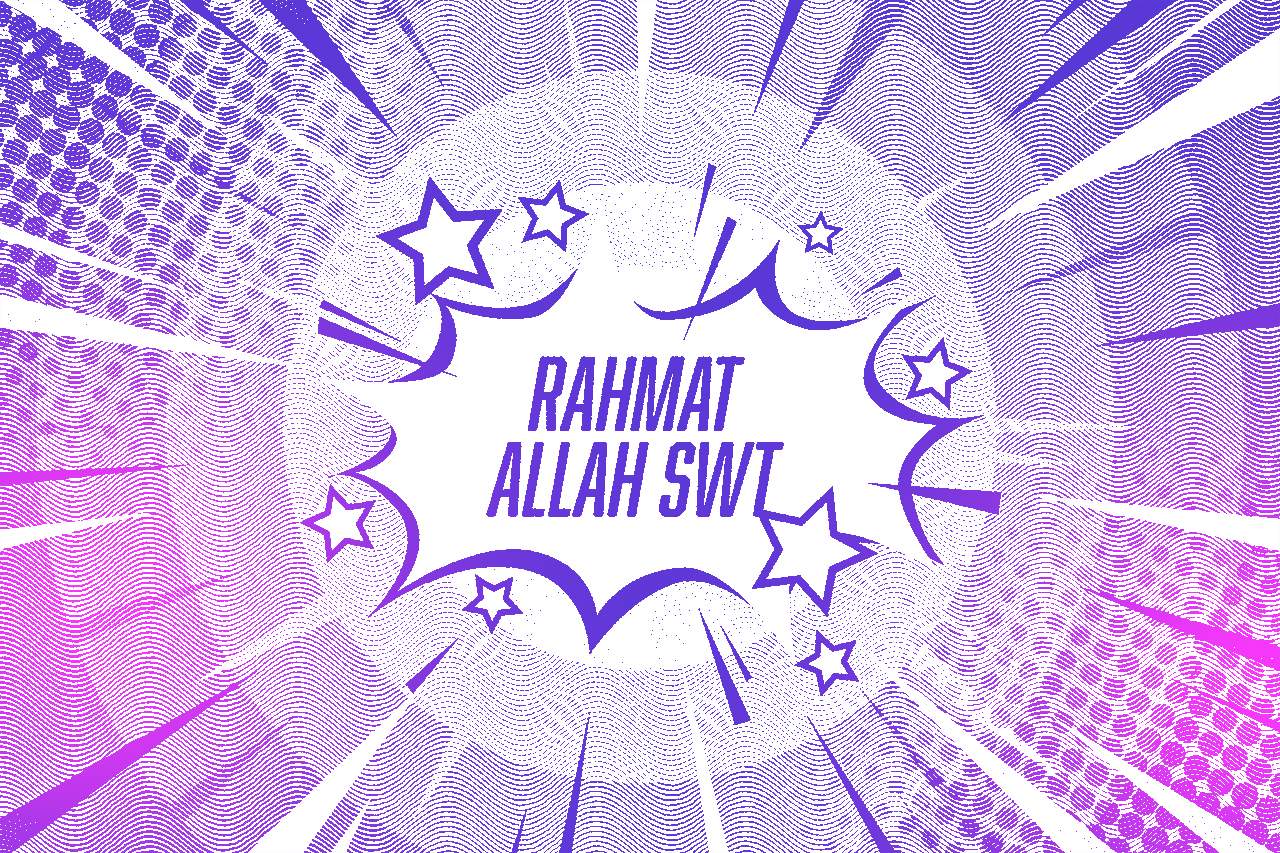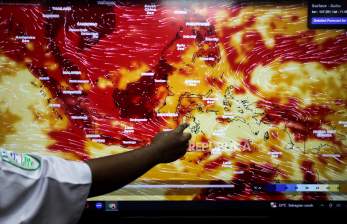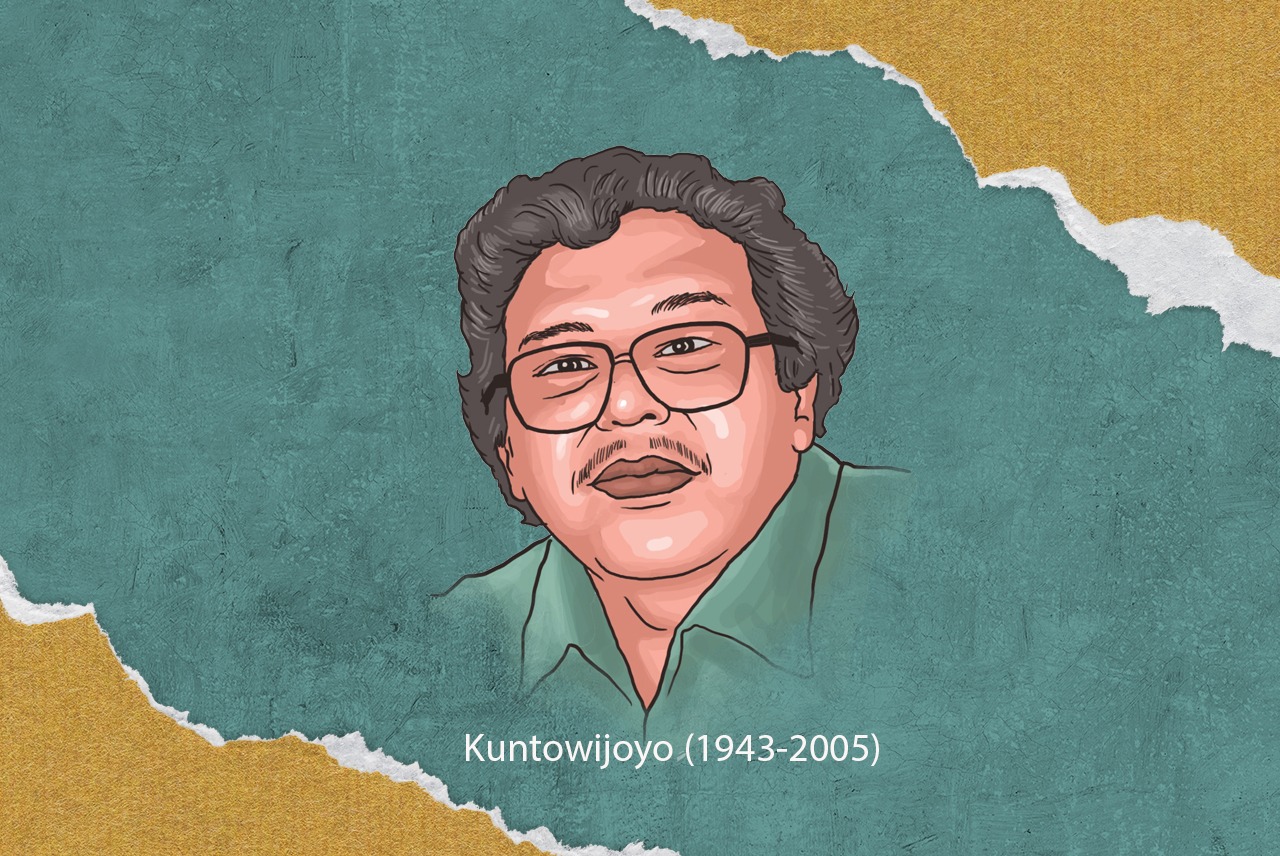
Refleksi
Ihwal Objektifikasi Politik Islam
Sejarah politik kita terputus-putus, tidak ada kesinambungan.
Oleh KUNTOWIJOYO
Pelaku, penggembira, dan pengamat politik, suka berpikir seolah-olah peta politik umat Islam yang diletakkan pada Pemilu (1955) adalah final, permanen, dan tidak berkembang. Seolah-olah politik Islam hanya berputar-putar sekitar dikotomi antara sekuler versus islamis, abangan versus santri, tradisionalis versus modernis, dan skripturalis versus substansialis. Antara I versus You, Aku versus...
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Sepertiga Malam Terakhir
Sungguh, sepertiga malam terakhir begitu agung untuk dilewatkan.
SELENGKAPNYAAr-Rubayyi binti Mu'awwidz, Angkat Senjata Bersama Pasukan Muslimin
Ar-Rubayyi juga memberikan pengobatan untuk para sahabat yang terluka.
SELENGKAPNYAFenomena Jamaah Lansia Minta Pulang Bisa Diantisipasi
Setibanya di Madinah, Saida menangis dan meminta dipulangkan ke kampung halamannya.
SELENGKAPNYA