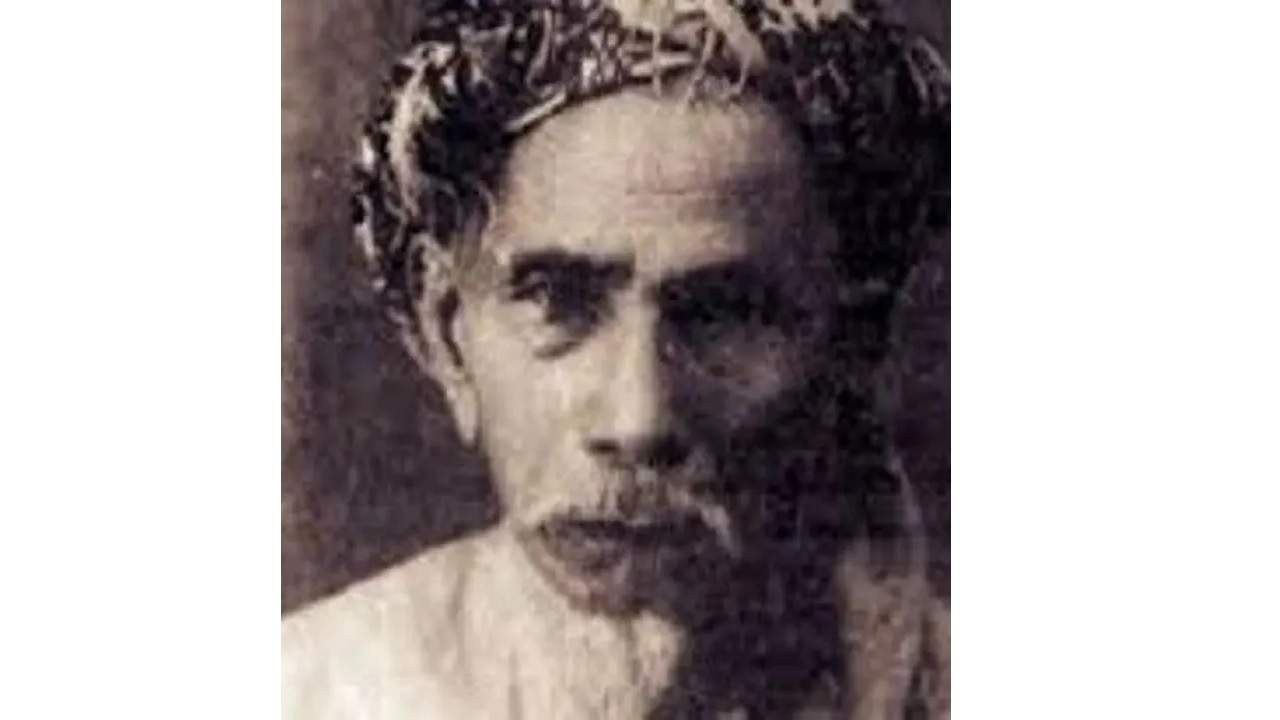Dunia Islam
Inikah Pondok Pesantren Pertama di Indonesia?
Terdapat diskusi mengenai manakah pondok pesantren pertama di Indonesia.
Indonesia boleh berbangga hati. Sebab, kaum Muslimin di Tanah Air memiliki corak lembaga pendidikan keagamaan Islam yang khas dan boleh jadi tidak ditemui di negara-negara lain. Institusi yang dimaksud adalah pondok pesantren (ponpes). Lembaga pendidikan ini memiliki karakteristik tradisional, tetapi terus berkembang dari masa ke masa—hingga kini. Buku Ensiklopedi Islam...
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Teladan Memuliakan Tamu Sejak Zaman Nabi
Para nabi Allah telah memberikan teladan perihal memuliakan tamu.
SELENGKAPNYASyekh Junaid al-Batawi, Ulama Indonesia yang Imam Masjidil Haram
Syekh Junaid al-Batawi adalah orang Indonesia pertama yang jadi imam besar Masjidil Haram.
SELENGKAPNYAIrjen Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati
Teddy dituntut lebih berat dari terdakwa lain karena dianggap sebagai aktor intelektual.
SELENGKAPNYA