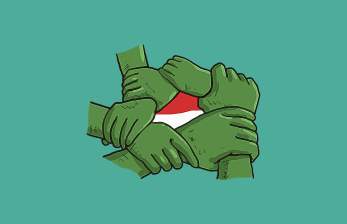Opini
Belajar Berdamai dengan Bumi Selama Ramadhan
Sudah saatnya Ramadhan tahun ini dijadikan permulaan proses perdamaian kita dengan bumi.
ANGGI AZZUHRI, Kandidat Doktor Studi Hukum Islam di Universitas Islam Internasional Indonesia Salah satu fenomena unik yang hanya terjadi pada Ramadhan, setidaknya selama beberapa dekade ke belakang, adalah meningkatnya penjualan makanan siap santap menjelang berbuka puasa, terutama di daerah urban. Peningkatan ini tentunya dipicu tren penyiapan takjil yang sepertinya harus variatif....
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Cegah Politisasi Puasa
Puasa itu membela yang lemah karena dilemahkan dan membantu yang miskin.
SELENGKAPNYASejarah Permulaan Penulisan Sirah
Penulisan biografi atau Sirah an-Nabawiyah menjadi perhatian para sarjana sejak abad-abad pertama Hijriyah.
SELENGKAPNYAMemahami Makna Shalat Tarawih, Qiyamulail, dan Tahajud
Shalat pada malam hari dinamakan qiyamulail sekaligus juga tahajud
SELENGKAPNYA