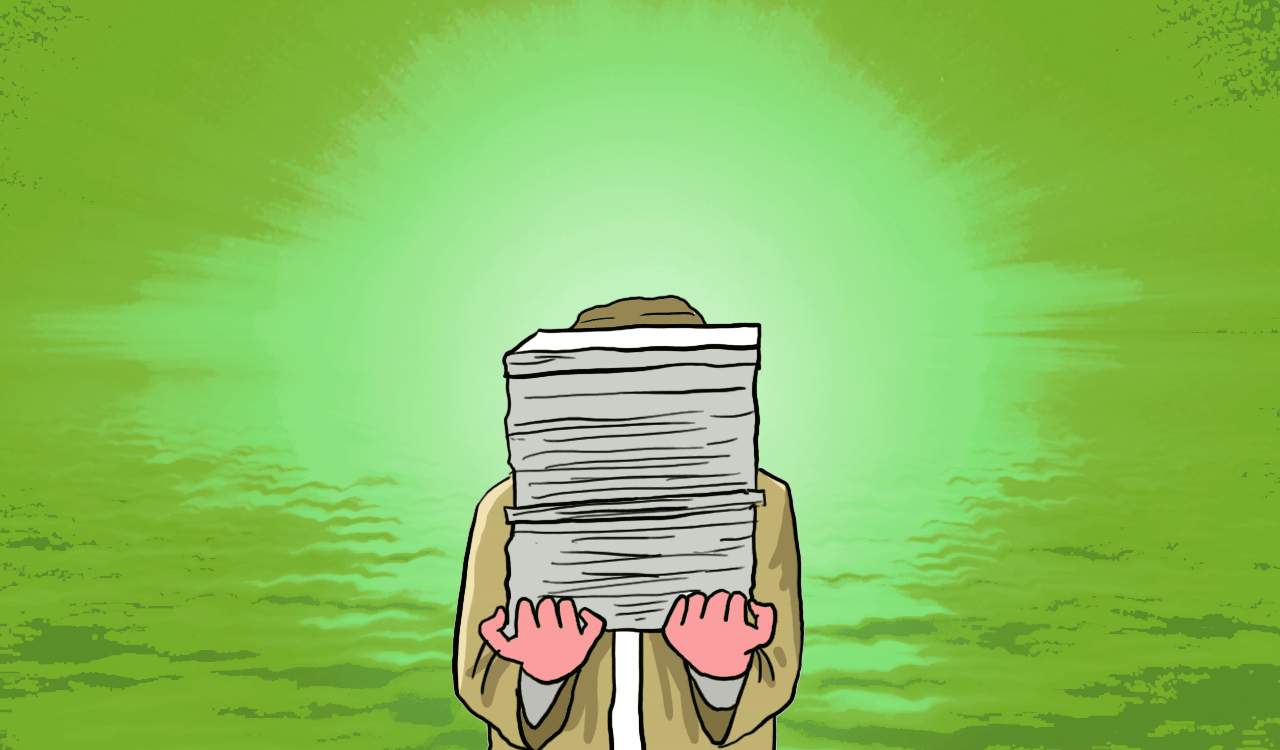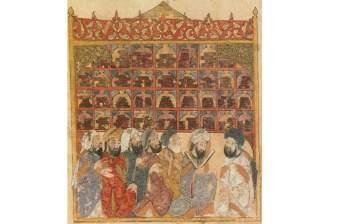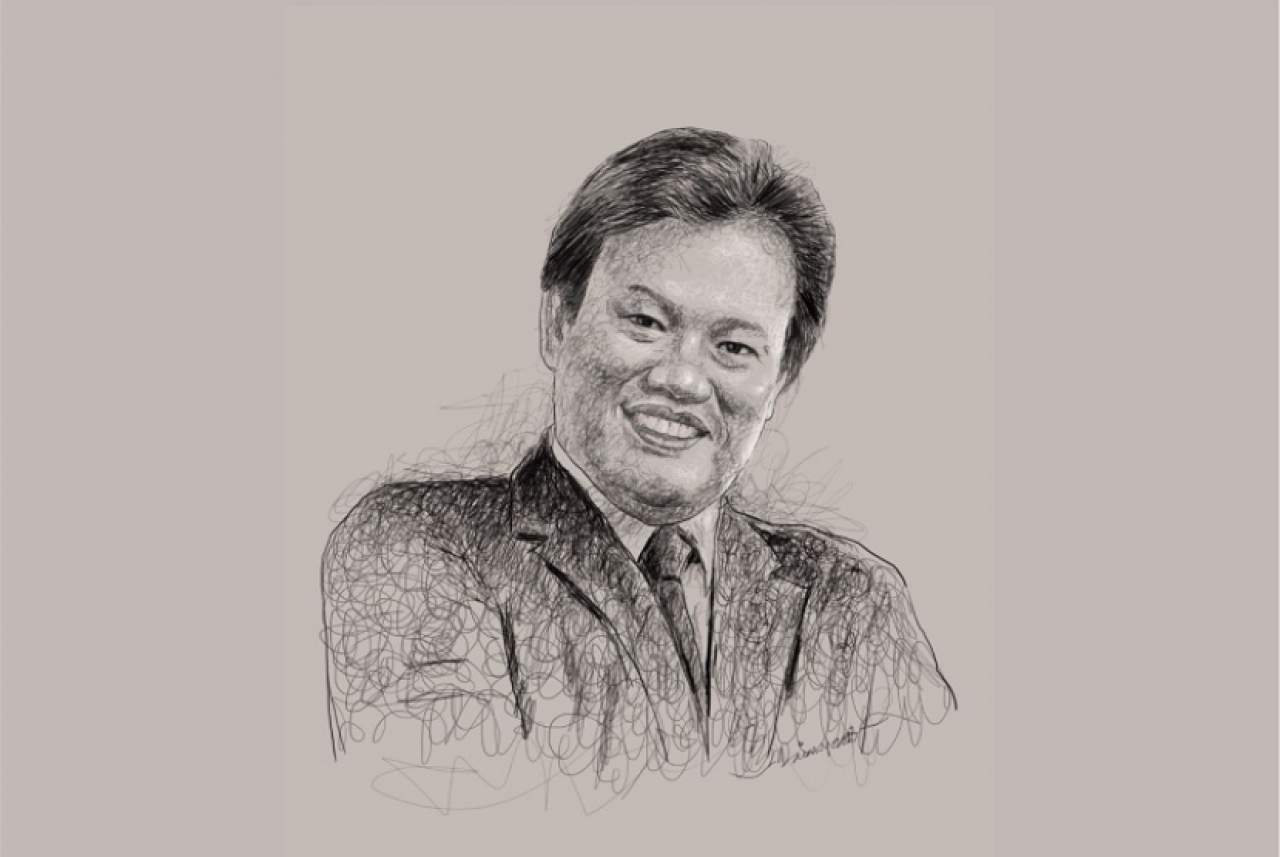
Analisis
Menuju Transisi Energi
Transisi energi adalah jalan menuju transformasi sektor energi global menjadi nol karbon.
Oleh SUNARSIP
Transisi energi kini menjadi agenda global di tengah upaya untuk mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Sesuai istilahnya, transisi energi berarti terdapat proses dalam menekan emisi karbon yang menyebabkan perubahan iklim (climate change). Transisi energi adalah jalan menuju transformasi sektor energi global menjadi nol karbon....
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Ikhtiar Indonesia Mencegah Perang Irak
Pada awal 2003, marak aksi menentang serangan AS ke Irak.
SELENGKAPNYAGayus Kiri ... Gayus Kiri..
Masyarakat tak punya pilihan selain menggunakan humor untuk menghibur diri.
SELENGKAPNYA