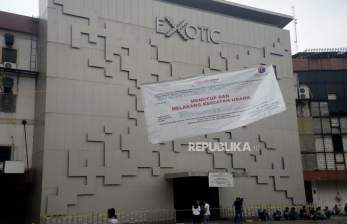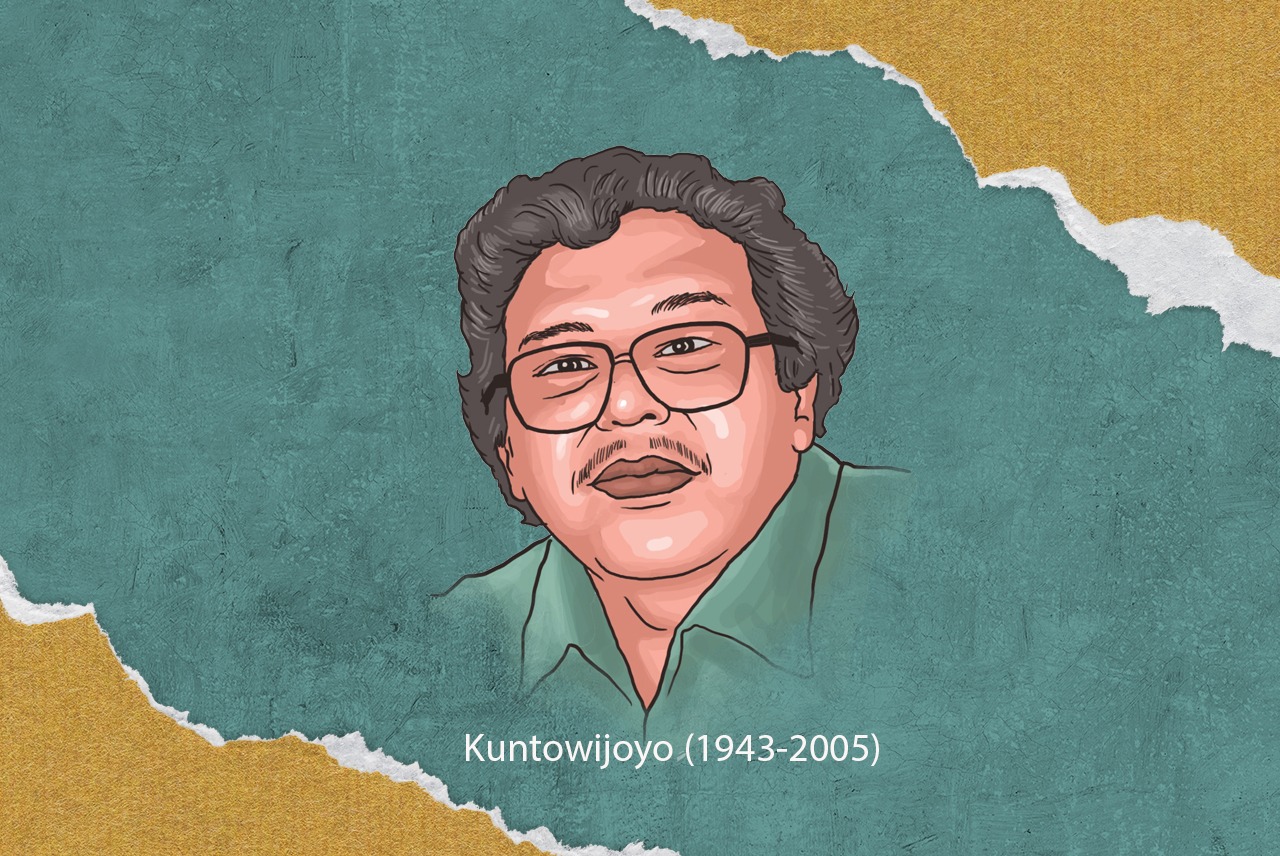
Refleksi
Jawa
Seolah-olah Jawa itu satuan yang tidak pernah berubah.
Oleh KUNTOWIJOYO
Gugatan pada budaya Jawa yang melupakan daulat rakyat dan hanya memperhatikan daulat negara baru-baru ini dikemukakan oleh WS Rendra dalam Pidato Kebudayaan Megatruh pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-29 Taman Ismail Marzuki pada 10 November 1997 (Republika, edisi 12 November 1997). Ini kemudian dibenarkan oleh Soetjipto Wirosardjono (Republika, edisi...
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Kala Muslimah Memilih untuk Jomblo
Melajang bagi kaum wanita juga menjadi perhatian tersendiri bagi kalangan ulama.
SELENGKAPNYAPara Puan Dalam Sejarah Ilmu Islam
Pada masa awal, ada banyak Muslimah terpelajar yang berperan dalam perkembangan syiar agama.
SELENGKAPNYAMuslimah Kawin Lari, Apa Hukumnya?
Wali bagi calon pengantin perempuan diwajibkan karena dia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri.
SELENGKAPNYA