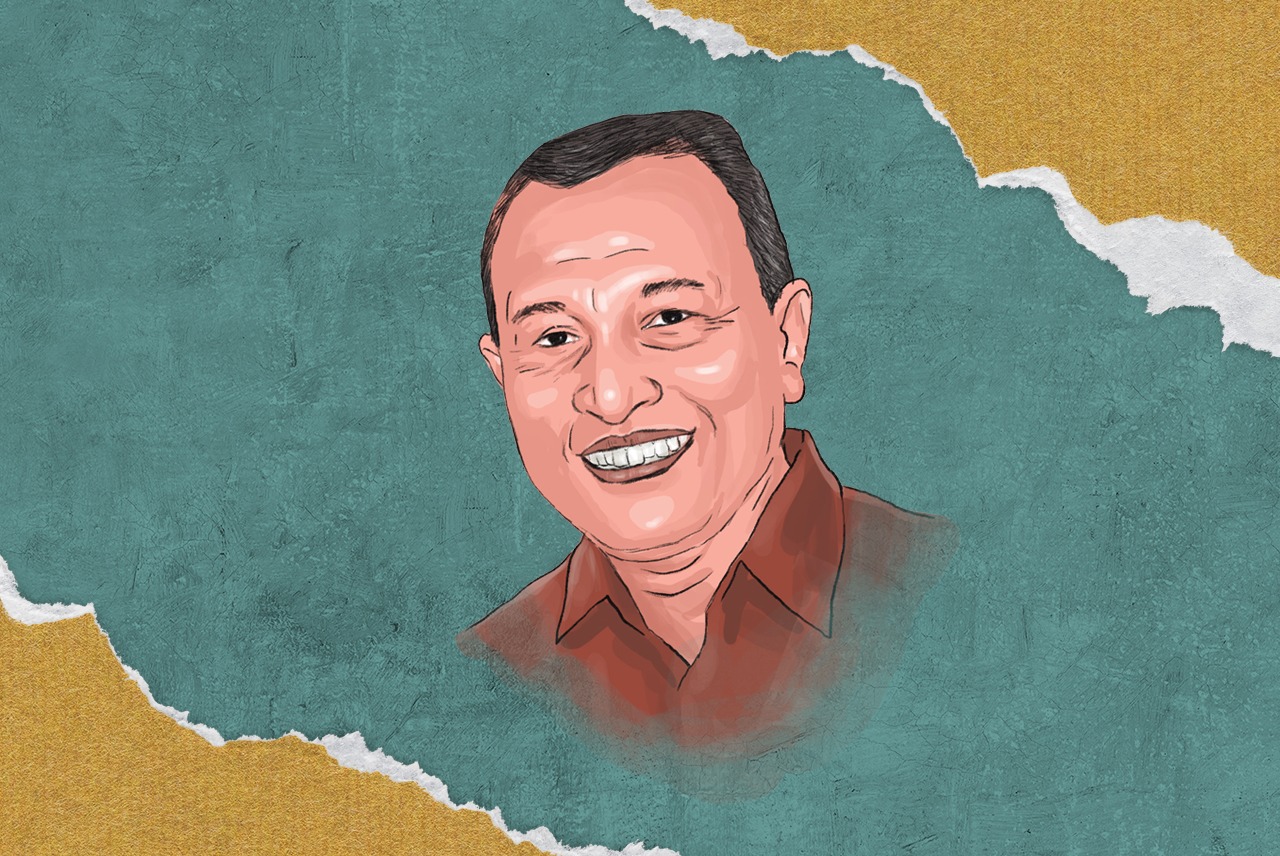
Refleksi
Tantangan Kebangsaan
Secara budaya, pendekatan yang sentralistis itu pun telah mengakibatkan pergeseran.
Oleh ADI SASONO
OLEH ADI SASONO Gary Hamel, pemikir bisnis terpenting dari Universitas Harvard saat ini, dalam buku yang akan diterbitkannya dengan judul Leading The Revolution meramalkan bahwa di abad 21 ini akan berlangsung pertarungan antara mereka yang mapan dengan yang sedang bangkit, antara pemeluk masa lalu dengan pencerah masa depan, dan antara 'hirarki...
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Kronologi Kerusuhan Morowali Versi Buruh
Kerusuhan pada Sabtu (14/1) malam itu sebenarnya berakar dari insiden pada akhir 2022.
SELENGKAPNYAPerjalanan Youtuber Jay Palfrey Menemukan Hidayah
Youtuber Jay Palfrey menemukan hidayah Islam kala ke negeri-negeri mayoritas Muslim.
SELENGKAPNYA










