
Kitab
Refleksi Politik Kebangsaan
Buku ini menghimpun tulisan Ketum Muhammadiyah tentang bangsa dan umat.
OLEH HASANUL RIZQA
Diskursus perpolitikan acap kali mempersoalkan hubungan antara agama dan negara. Relasi tersebut sekurang-kurangnya memunculkan tiga paradigma, yakni integralistik, sekuler, dan substantif.
Yang pertama menghendaki Islam sebagai dasar negara. Yang kedua bervisi memisahkan agama dari negara. Dalam arti, agama merupakan ranah privat sehingga negara tidak perlu mengurus atau mengatur keberagamaan warganya.
Adapun yang ketiga cenderung sebagai sintesis. Dalam pemahaman ini, agama tidak harus menjadi ideologi negara, tetapi kehidupan bernegara memerlukan panduan etika dan moral, sebagaimana yang diajarkan agama. Indonesia condong pada paradigma yang terakhir itu.
Menurut cendekiawan Muslim Prof Haedar Nashir, para pendiri bangsa menyadari pentingnya agama dan kehadiran Tuhan dalam perjuangan. Sebagai contoh, Mukaddimah UUD 1945 menegaskan, “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” rakyat Indonesia bisa menyatakan kemerdekaannya. Dengan demikian, perasaan diri sebagai hamba Tuhan tumbuh dalam kalbu kolektif masyarakat Tanah Air.
Di Indonesia, hubungan antara agama dan negara terbingkai dalam sistem demokrasi. Hal itu serta kaitannya dengan kondisi aktual saat ini dibahas dalam buku terbaru Haedar Nashir, Agama, Demokrasi, dan Politik Kekerasan (2021).
Perasaan diri sebagai hamba Tuhan tumbuh dalam kalbu kolektif masyarakat Tanah Air.
Dalam karyanya itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut mengajak pembaca untuk tidak terjebak pada simplifikasi, kenaifan, dan bias dalam memahami persoalan tentang isu-isu kebangsaan.
Buku ini menghimpun tulisan-tulisan Haedar yang pernah dimuat dalam rubrik “Refleksi” dan “Opini” harian umum Republika. Seperti tampak pada judulnya, ada tiga topik utama yang memayungi keseluruhan tulisan tersebut.
Mengenai agama, guru besar sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu membuat rumusan. Menurutnya, agama sebagai sistem nilai yang berbasis pada ajaran Tuhan berkaitan dengan dunia sakral sekaligus profan. Alhasil, visi sekuarisme menjadi tertolak, setidaknya dalam perspektif Islam.
Sementara itu, demokrasi dan politik sepenuhnya merupakan dimensi profan. Namun, ketika segala urusan duniawi, termasuk demokrasi dan politik, bersentuhan dengan agama dan umat beragama, aspek keprofanannya sering kali mengalami sakralisasi. Misalnya, soal pernikahan.
Demokrasi dan politik sepenuhnya merupakan dimensi profan.
Dalam masyarakat yang demokratis, siapapun boleh atau bahkan berhak menikah. Akan tetapi, pernikahan sesama jenis di Indonesia tidak bisa menuntut pengakuan legal dari negara. Sebab, bagi masyarakat Tanah Air, institusi pernikahan pun dimaknai sebagai perkara yang sakral.
Dalam ajaran Islam, umpamanya, ia disebut sebagai mitsaqan ghalizhan, suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh antara seorang lelaki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang tenteram, selamat di dunia dan akhirat.
Apakah dengan tidak diakuinya pernikahan sesama jenis Indonesia boleh dicap “nirdemokratis”? Tidak, sebab demokrasi yang hidup di negeri ini menjadikan nilai-nilai agama sebagai tuntunan etika dan moral.

Konteks Reformasi
Agama, Demokrasi, dan Politik Kekerasan terdiri atas empat bagian, yakni “Mencari Makna Agama”, “Reformasi dan Ancaman Demokrasi”, “Politik Kekerasan dan Kekerasan Politik”, serta “Jalan Tengah Muhammadiyah.”
Keseluruhan bagian tulisan itu umumnya membicarakan situasi kebangsaan pasca-peristiwa Reformasi 1998, yang berkaitan terutama dengan dunia politik, umat Islam, dan Muhammadiyah.
Pada bagian pertama, salah satu esai karangan Haedar bertajuk “Agama dan Gejala Radikalisasi Politik.” Artikel itu terbit dalam situasi menjelang pemilihan umum bulan Juni tahun 1999. Inilah pemilu pertama sejak Reformasi bergulir.
Yang disorotinya ialah politisasi simbol-simbol agama. Menurut Haedar, hingga batas tertentu politisasi simbol-simbol agama itu wajar adanya, lebih-lebih dalam masyarakat Indonesia yang dikenal religius.
Namun, di sisi lain politisasi simbol-simbol keagamaan bagaikan pisau bermata dua. Sebab, keadaan tersebut dapat memacu kecenderungan radikalisasi politik.

Ia mendeteksi, kecenderungan radikalisasi politik sebelum Pemilu 1999 tampak dari beberapa gejala. Misalnya, pertentangan antarpendukung partai politik (parpol) yang mengakibatkan bentrokan fisik.
Ujung-ujungnya, korban berjatuhan dari pihak rakyat biasa. Di samping itu, persaingan yang makin kuat memunculkan konflik politik yang melampaui batas-batas toleransi. Terakhir, adanya kekerasan bahasa politik, seperti terbaca dalam brosur, spanduk, ceramah, dan berbagai bentuk komunikasi politik lainnya.
Padahal, agama mengajarkan nilai-nilai universal, semisal kasih sayang (rahman-rahim), kedamaian (salam), toleransi (tasamuh), atau pemaaf (al-awf). Dalam wacana dan konstruksi politik yang teradikalisasi, nilai-nilai religi itu cenderung tersisihkan. Kalaupun masih ada, wujudnya hanya sekadar retorika atau jargon, tetapi tidak termanifestasi dalam pola perilaku dan aktivitas politik yang konkret.
Analisis Haedar atas situasi perpolitikan pada masa itu agaknya masih relevan sekarang. Sebab, adanya politisasi simbol-simbol agama tetap muncul di tengah masyarakat. Kaum elite politik kerap memanfaatkan jargon-jargon keagamaan untuk meyakinkan dirinya sebagai pemegang kebenaran (mission sacre) di hadapan lawan politik.
Lawan politik yang dikonstruksikan itu tidak mesti mereka yang berbeda agama, tetapi seringkali juga mereka yang satu agama.
“Lawan politik yang dikonstruksikan itu tidak mesti mereka yang berbeda agama, tetapi seringkali juga mereka yang satu agama,” tulisnya.
Pada bagian kedua dari buku ini, terdapat artikel Haedar, “Merajut Indonesia Ikhlas.” Dengan tulisannya itu, ulama kelahiran Bandung, Jawa Barat, tersebut mengajukan resep untuk “melawan” radikalisasi politik, yakni keikhlasan.
Tidak seperti politik-yang-radikal, politik-yang-ikhlas justru menghindari kalkulasi pamrih diri atau golongan. “Manusia ikhlas tidak akan pamrih dalam berbuat kebajikan dan mencegah kemunkaran karena motivasi utamanya meraih ridha dan karunia Allah,” ujarnya.
Haedar menekankan, Indonesia kini sangat memerlukan energi ikhlas sebagai potensi rohani dalam membangun negeri. Segenap warga dan elite harus berani meruntuhkan ego dan kepentingan diri demi bangsa Indonesia yang bersatu, berkemajuan, dan berperadaban luhur.
Manusia ikhlas tidak akan pamrih dalam berbuat kebajikan dan mencegah kemunkaran karena motivasi utamanya meraih ridha dan karunia Allah.
Sangat disayangkan apabila semangat tenggang rasa, saling peduli dan berbagi, kian terkikis. Di dunia politik, gejala demikian amat terasa.
“Kursi di pemerintahan dari pusat hingga daerah menjadi bancakan, siapa yang pegang kuas dia dan kroni atau kelompoknya yang menikmati dengan syahwat berlebih, senang kalau yang lain terpinggirkan,” tulis Haedar.
Politik-yang-radikal menghendaki zero sum game. Bahkan, dalam konteks keumatan pun, acap kali tampak semangat saling berebut antargolongan. Kesempatan kuasa dijadikan aji mumpung kelompok sendiri dengan menyisihkan yang lain.
“Agama dan nilai-nilai kebangsaan yang luhur sekadar jadi retorika dan alat komodifikasi golongan sendiri. Di sinilah ujian keikhlasan kolektif dalam berbangsa menjadi pertaruhan,” katanya.

Muhammadiyah dan politik
Buku ini juga membicarakan posisi Muhammadiyah dalam konteks perpolitikan Indonesia abad ke-21. Sebagai contoh, tulisan akademisi UMY itu yang berjudul “Muhammadiyah Pasca-Pemilu 2019.” Ia menyatakan, persyarikatan ini tidak akan terombang-ambing arus politik lima tahunan.
Berdasar pada Khittah Denpasar 2002, Muhammadiyah memiliki sejumlah pedoman dalam persentuhannya dengan dunia politik. Di antaranya ialah, Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani yang kuat. Itu sebagaimana tujuan Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
“Muhammadiyah meyakini, politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek ajaran Islam dalam urusan keduniawian yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama,” tegasnya.
Muhammadiyah meyakini, politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek ajaran Islam dalam urusan keduniawian.
Sejak awal, organisasi masyarakat (ormas) Islam ini memang tidak berafiliasi dan tidak pula mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan politik atau organisasi politik manapun. Namun, Persyarikatan tidak akan menutup mata bila ada anggotanya yang aktif dalam politik. Kepada mereka, diimbau untuk selalu mengedepankan tanggung jawab, akhlak mulia, keteladanan, dan perdamaian.
Sering kali, para elite politik mengabaikan aspek keteladanan hanya demi menggaet suara rakyat sebanyak-banyaknya. Padahal, lanjut Haedar, persatuan dan kepentingan nasional semestinya diletakkan di atas segalanya.
Pada poin inilah, ia mengingatkan, kontestasi pemilu jangan sampai memicu luapan ego yang cenderung memecah-belah persatuan bangsa. “Karena, keberadaan dan masa depan Indonesia tidak dapat dipertaruhkan oleh dinamika kontestasi politik lima tahunan yang temporer!” ujarnya.
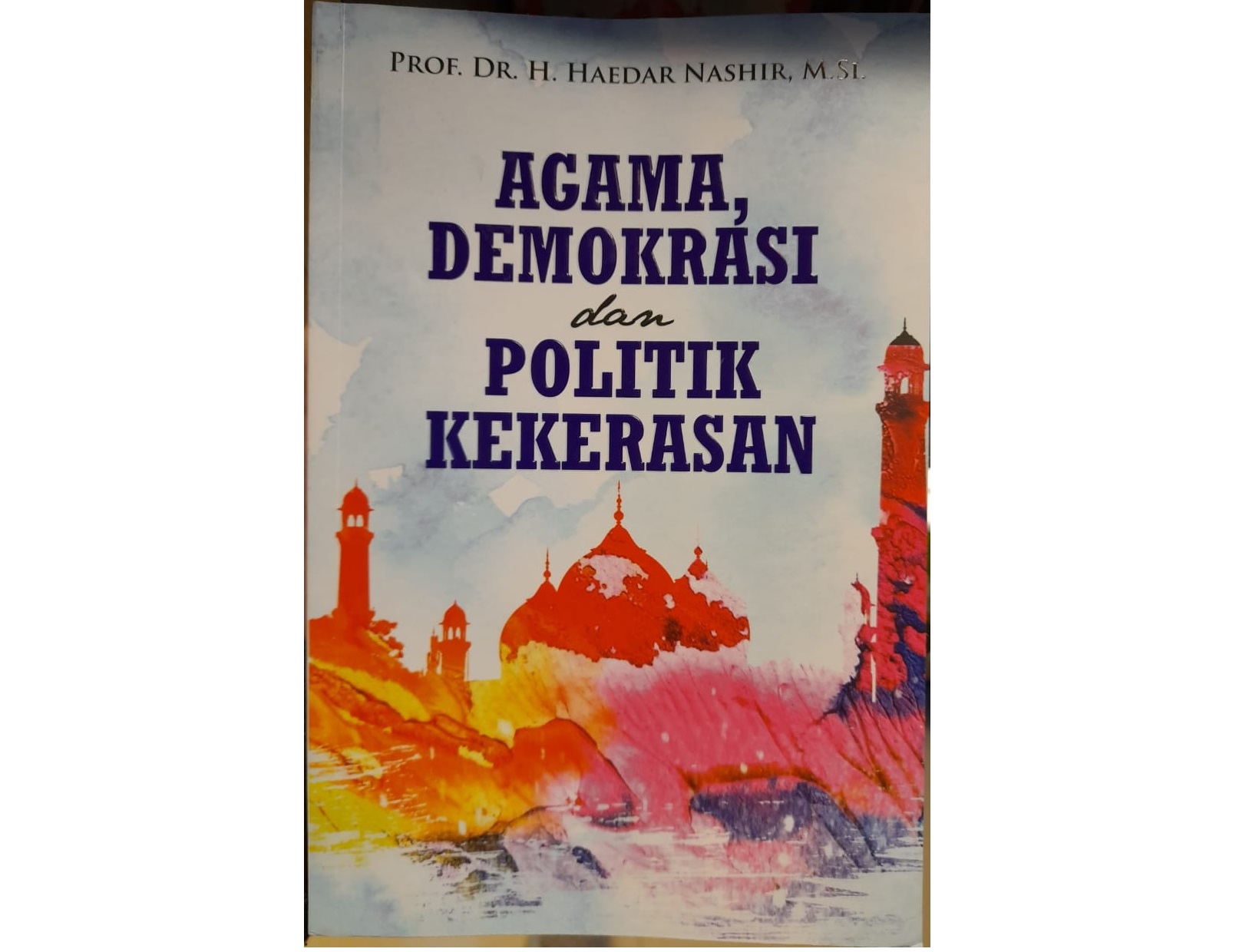
DATA BUKU
JUDUL: Agama, Demokrasi, dan Politik Kekerasan
Penulis: Prof Haedar Nashir
Penerbit: Republika Penerbit dan Suara Muhammadiyah
Tebal: 225 halaman
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.







