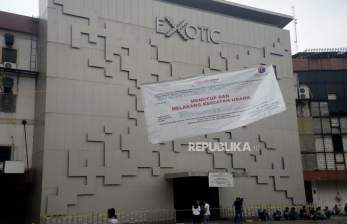Iqtishodia
Dampak Tarif terhadap Human Capital: Mengurai Tantangan, Menempa Strategi
Sentimen negatif mendorong investor menarik dana dari aset berisiko.
Oleh Budi Purwanto dan Indra Refipal Sembiring (Dosen di Departemen Manajemen, FEM-IPB University)
Awal April 2025, udara politik dan ekonomi dunia kembali memanas. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan yang langsung menggemparkan pasar global: Reciprocal Tariff. Dengan nada tegas, Trump menyatakan Amerika akan memberlakukan tarif tambahan 10 persen untuk seluruh impor, plus tarif timbal balik yang lebih tinggi bagi negara-negara yang dianggap memiliki defisit perdagangan besar terhadap AS.
Indonesia, yang secara eksplisit disebut menghambat ekspor AS melalui berbagai hambatan tarif dan non-tarif, langsung masuk daftar. Seketika, tarif impor sebesar 32 persen dipasang untuk produk Indonesia di pasar AS. Setelah negosiasi singkat, angka itu turun menjadi 19 persen.
Namun, penurunan ini datang dengan harga yang tidak kecil: Indonesia harus membuka pasar dalam negeri secara luas untuk produk AS, menghapus hambatan tarif dan non-tarif pada lebih dari 99 persen komoditas mereka, termasuk pangan, alat kesehatan, teknologi, hingga sektor strategis lainnya (Transnational Institute, 2025).
Bagi sebagian pengamat, penurunan dari 32 menjadi 19 persen adalah kemenangan diplomasi. Namun, hal ini juga dilihat sebagai bentuk unilateral coercion—pemaksaan sepihak yang mencerminkan hegemoni dagang dalam bentuk paling terbuka.
Apabila memahami isi narasi ini, maka tarif tersebut bukan sekadar kesepakatan dagang biasa, melainkan pelanggaran terhadap prinsip most-favored nation WTO dan semangat timbal balik yang selama ini menjadi pilar perdagangan multilateral.
Efek pengumuman ini langsung terasa di pasar finansial. Nilai tukar rupiah melemah, dari Rp 16.741 per dolar AS pada 3 April menjadi Rp 17.200 pada 8 April.
Sentimen negatif mendorong investor menarik dana dari aset berisiko seperti rupiah dan membawanya ke dolar AS yang kembali menjadi safe haven. Potensi kenaikan suku bunga The Fed akibat inflasi pascatarif mempercepat arus modal keluar dari negara-negara berkembang.
Di sektor riil, pelaku industri mulai menghitung ulang strategi. Produk padat karya seperti elektronik dan garmen terancam kenaikan harga di pasar AS sebesar 10–20 persen, cukup untuk membuat pembeli beralih ke pemasok lain.
Penurunan pesanan berpotensi memicu penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja. Dampak kebijakan tarif ini tidak hanya berhenti pada perdagangan. Perubahan tarif seperti ini dapat memengaruhi modal manusia (human capital) secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung muncul dari perubahan neraca perdagangan dan produktivitas ekonomi; dampak tidak langsung merembes ke pasar tenaga kerja, investasi pendidikan, dan pengembangan keterampilan.
Human capital—konsep yang didefinisikan Becker (1964) sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas ekonomi—adalah aset strategis.
Ketika ekspor terpukul, peluang kerja di sektor berteknologi menengah-tinggi menyusut. Insentif bagi pekerja untuk mengembangkan keterampilan bisa melemah. Li et al. (2018) mencatat, liberalisasi perdagangan di China menurunkan lama sekolah di wilayah padat karya karena anak muda lebih memilih bekerja cepat demi penghasilan langsung.
Ketidakpastian investasi akibat kebijakan tarif juga berdampak pada inovasi. Tabash et al. (2023) dan Cui et al. (2021) menunjukkan bahwa ketidakpastian kebijakan ekonomi menghambat investasi riset dan pengembangan serta mengurangi adopsi teknologi baru. Aizenman (1995) bahkan menggambarkannya sebagai “pajak implisit” terhadap aktivitas ekonomi baru, termasuk pelatihan keterampilan.
Dalam konteks Indonesia, risiko ini berlipat ganda karena perjanjian yang menyertai penurunan tarif juga menghapus berbagai regulasi domestik yang melindungi strategi nasional, termasuk larangan ekspor bahan mentah seperti nikel dan tembaga—kunci hilirisasi industri baterai dan teknologi bersih.
Tanpa perlindungan ini, Indonesia berisiko kembali ke perangkap sebagai eksportir bahan mentah, kehilangan peluang nilai tambah di dalam negeri, dan membiarkan lapangan kerja bernilai tambah tinggi tercipta di luar negeri.
Namun, sejarah menunjukkan bahwa guncangan perdagangan dapat menjadi momentum untuk memperkuat strategi nasional. Dokumen kajian ini mengangkat beberapa contoh. Brasil memperkuat sektor pertaniannya lewat kebijakan substitusi impor dan insentif produksi dalam negeri.
India menjalankan kebijakan Atmanirbhar Bharat untuk melindungi industri strategis dan membatasi impor selektif. Vietnam memanfaatkan perdagangan bebas secara selektif, hanya menyetujui perjanjian yang sejalan dengan strategi industrialisasi dan diversifikasi mitra dagang.
Untuk memastikan human capital Indonesia tetap berdaya saing di tengah tekanan kebijakan tarif seperti Reciprocal Tariff Trump 2025, strategi pertama yang perlu diutamakan adalah memperkuat kapasitas industri domestik melalui hilirisasi dan diversifikasi pasar ekspor.
Hilirisasi sumber daya alam—seperti mengolah CPO menjadi biofuel dan kosmetik, serta nikel menjadi baterai kendaraan listrik—akan menciptakan lapangan kerja bernilai tambah tinggi yang menyerap tenaga kerja terampil. Pada saat yang sama, diversifikasi pasar ke kawasan seperti Uni Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin akan mengurangi ketergantungan pada pasar AS, sekaligus membuka peluang penguasaan pasar baru yang lebih stabil.
Langkah ini harus dibarengi dengan kebijakan insentif pajak dan pendanaan riset bagi industri yang serius membangun ekosistem inovasi dan transfer teknologi, sehingga tenaga kerja Indonesia dapat terus memperbarui keterampilan mereka sesuai tuntutan pasar global.
Selain itu, pemerintah perlu melakukan investasi besar-besaran pada pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan industri, dengan fokus pada sektor teknologi, manufaktur, dan energi terbarukan yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi.
Program upskilling dan reskilling harus disinergikan dengan dunia usaha, sehingga lulusan pelatihan siap bekerja di industri yang memerlukan kompetensi spesifik. Ketidakpastian kebijakan perdagangan, seperti yang dicatat Tabash et al. (2023) dan Cui et al. (2021), dapat menghambat inovasi jika tidak diimbangi oleh SDM yang adaptif dan berorientasi solusi.
Karena itu, kurikulum pendidikan—seperti yang diusahakan dalam vokasi dan politeknik—perlu dirancang ulang untuk mengakomodasi teknologi terkini, keterampilan digital, dan kemampuan beradaptasi lintas sektor.
Dengan kombinasi antara penguatan industri, diversifikasi pasar, dan pengembangan keterampilan, Indonesia dapat mempertahankan bahkan meningkatkan daya saing human capital-nya di tengah lanskap perdagangan global yang semakin penuh risiko.
Reciprocal Tariff Trump 2025 mungkin dirancang untuk memperkuat industri AS, tetapi bagi Indonesia, tantangan yang muncul adalah ujian ketahanan ekonomi dan visi jangka panjang. Dengan strategi yang terukur, berpihak pada penguatan human capital, dan keberanian dalam diplomasi, badai tarif ini bisa diubah menjadi momentum untuk menegakkan kedaulatan ekonomi di tengah arus besar perdagangan global yang kian sarat risiko.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.