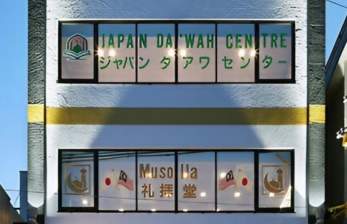Iqtishodia
Hilirisasi Kelapa dan Tantangan Ketersediaan Bahan Baku
Identifikasi pasar ekspor untuk produk hilir kelapa perlu segera dilakukan.
Oleh Dr. Widyastutik (Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB)
Kelapa (Cocos nucifera) sering disebut sebagai tree of life atau pohon kehidupan karena nilai kegunaan kelapa tidak hanya terletak pada bagian daging buahnya yang dapat diolah menjadi santan, kopra, maupun minyak kelapa, tetapi hampir seluruh bagian tanamannya memiliki manfaat ekonomis. Pertumbuhan produk kelapa didorong oleh meningkatnya tren gaya hidup sehat dan preferensi konsumen terhadap produk alami. Permintaan global terhadap berbagai produk turunan kelapa, seperti Virgin Coconut Oil (VCO), air kelapa, dan santan, terus mengalami peningkatan seiring dengan perubahan pola konsumsi masyarakat (Kementan, 2025).
Indonesia merupakan salah satu negara produsen utama kelapa yang tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga mengekspor berbagai produk turunannya (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2021). Produksi dunia sebesar 64.121.914 MT, sementara itu Indonesia berkontribusi sebesar 17.046.263 MT, atau sebesar 27% dari total produksi dunia.
Kelapa merupakan komoditas tanaman tropis yang telah dibudidayakan secara turun-temurun oleh masyarakat Indonesia dan memiliki peranan penting dalam sistem pertanian nasional. Tanaman ini tersebar luas di berbagai wilayah Nusantara dan memiliki peran strategis dalam aspek sosial, budaya, serta ekonomi masyarakat. Lahan budidaya kelapa lebih dari 95 persen dimiliki oleh rakyat. Dari 17,2 juta petani kelapa di dunia, 34,3 persen merupakan petani kelapa Indonesia.
Indonesia menduduki posisi nomor dua dari sisi lahan, sementara itu jumlah petani dan rata-rata pengelolaan lahan menduduki posisi nomor satu. Produktivitas tertinggi ditempati oleh India. Berdasarkan Sambodo et al. (2024), benchmark pada petani kelapa di India menunjukkan petani kelapa telah mengadopsi praktik GAP dengan bimbingan Coconut Development Board (CDB), yang mengimplementasikan irigasi tetes yang efisien dan pemanfaatan internet of things (IoT) untuk meningkatkan produktivitas pertanian kelapa.
Pemerintah India melalui CDB menyelenggarakan program-program seperti pendirian kios/titik kelapa dan kebun pembibitan kelapa, pengembangan teknologi kelapa, serta pelatihan keterampilan khusus dalam memanjat pohon kelapa dan perlindungan tanaman dengan program friends of coconut tree.
Kunci sukses keberhasilan pengembangan kelapa di India didukung oleh institusi pemerintah seperti CDB dan Coir Board, yang memiliki peran pada desentralisasi program pengembangan kelapa. CDB di bawah koordinasi Kementerian Usaha Kecil dan Menengah India menjadi penanggung jawab utama dalam pengembangan kelapa.
Potensi pemanfaatan yang menyeluruh inilah yang menjadikan kelapa sebagai komoditas komersial bernilai tinggi. Peta Jalan Hilirisasi Kelapa Tahun 2025–2045 mengarahkan percepatan hilirisasi kelapa guna mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai pemimpin global dalam hilirisasi kelapa dan turunannya. Pelaksanaannya didukung dengan keterpaduan penanganan isu-isu strategis perkelapaan dari hulu hingga hilir. Hilirisasi akan difokuskan pada komoditas yang memiliki potensi dampak makroekonomi besar.
Kelapa merupakan salah satu komoditas pertanian dalam arti luas yang menjadi agenda pemerintah untuk hilirisasi. Potensi PDB walaupun lebih rendah dibandingkan sawit, namun potensi tenaga kerja relatif lebih tinggi. Sementara itu, potensi ekspor dan investasi kelapa relatif lebih rendah dibandingkan sawit. Potensi penyerapan tenaga kerja yang terlibat dalam hilirisasi kelapa diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang tinggi.
Tantangan dan Strategi Kunci Hilirisasi Kelapa
Investasi industri pengolahan kelapa skala menengah-besar masih terbatas, utamanya disebabkan belum adanya jaminan ketersediaan bahan baku sehingga utilisasi masih berkisar 40–55 persen. Salah satu kunci keberhasilan hilirisasi adalah tersedianya bahan baku. Produktivitas kelapa cenderung stagnan pada angka sekitar 1,1 ton per hektar per tahun, dengan tren penurunan baik dalam hal produksi maupun luas lahan, mendorong produksi kelapa bulat cenderung mengalami penurunan.
Selama 16 tahun terakhir, produksi kelapa nasional secara gradual mengalami penurunan. Rata-rata penurunan produksi setiap tahunnya adalah -0,89 persen. Dalam lima tahun terakhir, produksi cenderung meningkat walaupun menurun kembali pada tahun 2023 dan 2024.
Selama 10 tahun terakhir, terdapat 10 provinsi yang menjadi sentra produksi kelapa nasional, dengan kontribusi terhadap produksi kelapa nasional sebanyak 65,51 persen. Provinsi Riau merupakan kontributor terbesar terhadap produksi kelapa nasional (14,15 persen), disusul oleh Sulawesi Utara, Jawa Timur, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah.
Merujuk pada Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025–2045 oleh Sambodo et al. (2024), program dan inisiatif pemerintah selama ini yang bertujuan meningkatkan produksi dan produktivitas belum menunjukkan hasil yang signifikan. Saat ini terdapat sekitar 378,2 ribu hektar atau sekitar 11,3 persen dari total luas perkebunan kelapa yang terdiri dari luas areal tanaman tidak menghasilkan/tanaman rusak (TTM/TR).
Di sisi lain, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung peremajaan, perluasan, dan intensifikasi berkisar antara 6.000–10.000 hektar per tahun. Kondisi ini menyebabkan proporsi pohon kelapa yang tua, rusak, dan tidak produktif meningkat sebesar 2,4 persen.
Paralel dengan kondisi ini, budidaya kelapa masih dilakukan dengan metode konvensional, di mana sebagian besar petani mengandalkan hasil alami tanpa perlakuan (pemupukan, pengairan, dan penanganan hama penyakit) tambahan yang berarti. Dengan pelarangan hewan beruk untuk memanen kelapa, petani kelapa saat ini juga menghadapi posisi tawar yang rendah dalam menggunakan tenaga pemanen yang terbatas, sehingga penghasilannya cenderung berkurang dengan sistem panen bagi hasil.
Ditambah dengan rendahnya harga jual kelapa di tingkat petani, kondisi ini mendorong terjadinya konversi lahan kelapa ke penggunaan lain yang dianggap lebih menguntungkan, serta regenerasi petani berjalan lambat.
Data menunjukkan pada tahun 2022, sekitar 90 persen kelapa di Indonesia dipanen saat sudah tua atau matang, dan 10 persen dipanen saat muda. Dari kelapa tua atau matang yang dipanen, sekitar 49 persen diolah menjadi kopra yang kemudian diproses menjadi minyak kelapa. Sekitar 82,1 persen minyak kelapa diekspor sebagai crude coconut oil (CNO), sementara sisanya untuk konsumsi domestik. CNO merupakan produk olahan kelapa terbesar yang diperdagangkan secara global.
Selain dijadikan kopra, kelapa tua juga diolah menjadi kelapa parut kering (7,9 persen), santan (7,1 persen), virgin coconut oil (VCO) (4,5 persen), dan penggunaan domestik lainnya (17,1 persen). Sebagian kelapa tua juga diekspor (4,4 persen). Kelapa muda hampir seluruhnya dikonsumsi di dalam negeri, dan hanya 0,02 persen yang diekspor (ICC, 2023 dalam Sambodo, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat bagian-bagian kelapa seperti air, sabut, dan tempurung yang masih belum dimanfaatkan secara optimal dan sering kali terbuang.
Pemanfaatan bahan baku kelapa masih ada yang underutilized, seperti air kelapa yang baru diolah 20 persen, sabut 30 persen, dan tempurung 35 persen (Kementerian Perindustrian, 2024). Untuk itu, hilirisasi industri pengolahan kelapa diprioritaskan pada pengolahan produk dengan nilai tambah tinggi, seperti konsentrat air kelapa, Medium Chain Triglycerides (MCT), karbon aktif, dan bioavtur/Sustainable Aviation Fuel (SAF).
Pemanfaatan lebih lanjut dari bagian-bagian kelapa ini berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian melalui diversifikasi produk turunan. Saat ini terdapat 30 industri besar di Indonesia yang bergerak pada produksi turunan kelapa. Sebanyak 16 industri di antaranya merupakan industri terintegrasi antara perkebunan dan industri pengolahannya.
Hilirisasi kelapa ke arah industri minyak kelapa, VCO, oleokimia, santan dan turunannya, high fat desiccated coconut dan turunannya, gula kelapa, kecap kelapa, coir geotextile, cocopeat, bioavtur, serta MCT bertujuan untuk meningkatkan utilisasi industri kelapa dari 45 persen (2022) menjadi 55 persen (2029).
Tantangan lain untuk peningkatan kinerja hilirisasi industri berbasis kelapa adalah isu investasi yang mendukung hilirisasi kelapa secara terintegrasi, serta penguasaan teknologi untuk menghasilkan produk-produk bernilai tambah tinggi. Dari sisi pemasaran, tingginya biaya logistik juga akan memengaruhi efisiensi rantai pasok dan harga akhir produk kelapa sebelum masuk ke industri pengolahan (Sambodo et al., 2024).
Berbagai tantangan tersebut tentunya memerlukan kolaborasi multi pihak untuk tata kelola kesuksesan program hilirisasi kelapa. Dari sisi hulu, aspek peremajaan, penerapan GAP, pertanian regeneratif, penguatan produksi, kelembagaan, dan persebaran bibit unggul menjadi strategi kunci. Dari sisi industri, investasi dan peningkatan utilisasi serta diversifikasi industri produk turunan kelapa sangat diperlukan, selain harmonisasi kebijakan untuk mendukung integrasi rantai pasok industri kelapa.
Peningkatan investasi industri kelapa terintegrasi yang mencakup kemitraan dengan petani, termasuk membangun kepercayaan (trust) antara petani dan industri, sangat diperlukan untuk menjamin adanya transmisi harga ekspor produk turunan sampai ke petani.
Sementara itu, identifikasi pasar ekspor untuk produk hilir kelapa perlu segera dilakukan untuk memetakan daya saing Indonesia di pasar global. Market intelligence produk turunan kelapa mana yang mampu bersaing di pasar negara tertentu akan berbeda-beda. Pemetaan daya saing dan strategi penetrasi pasar ekspor, baik ke negara tradisional maupun nontradisional, sangat diperlukan untuk menjamin keberlangsungan permintaan produk turunan kelapa Indonesia.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.