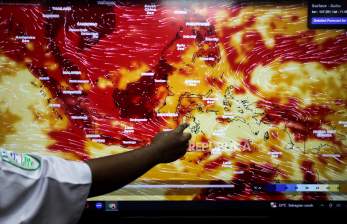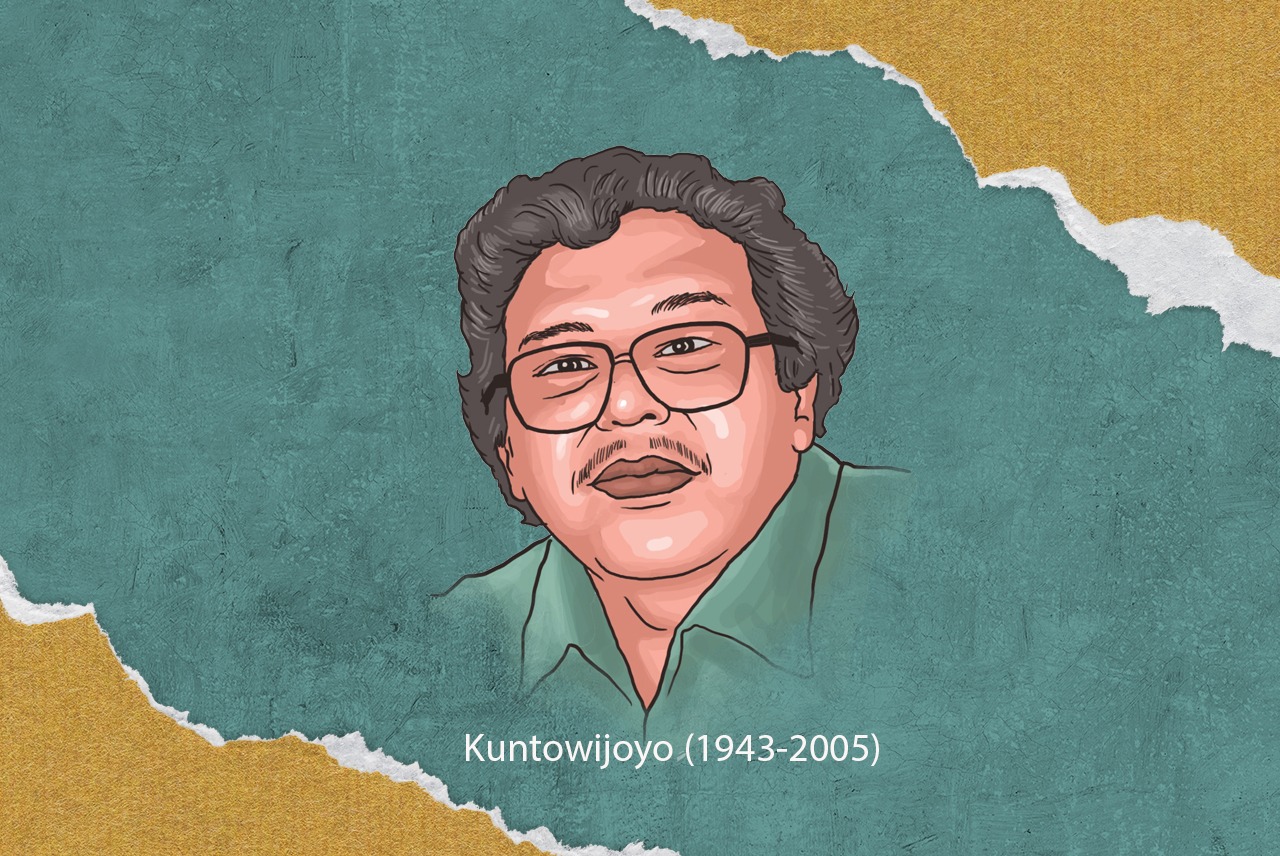
Refleksi
Dimensi Kultural Integrasi Bangsa (Bagian 1)
Sejarah politik kita terpaku pada gejala pemilu pertama.
Oleh KUNTOWIJOYO
Tulisan ini akan dimulai dengan pernyataan yang menyesakkan napas: kita kecewa dengan perjalanan sejarah bangsa. Kita selalu menoleh ke belakang, karena itu budaya politik -- khususnya sistem pengetahuan dan tingkah laku politik -- kita berjalan di tempat, tidak maju-maju. (seterusnya, istilah budaya politik maksudnya ialah sistem pengetahuan dan tingkah...
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.