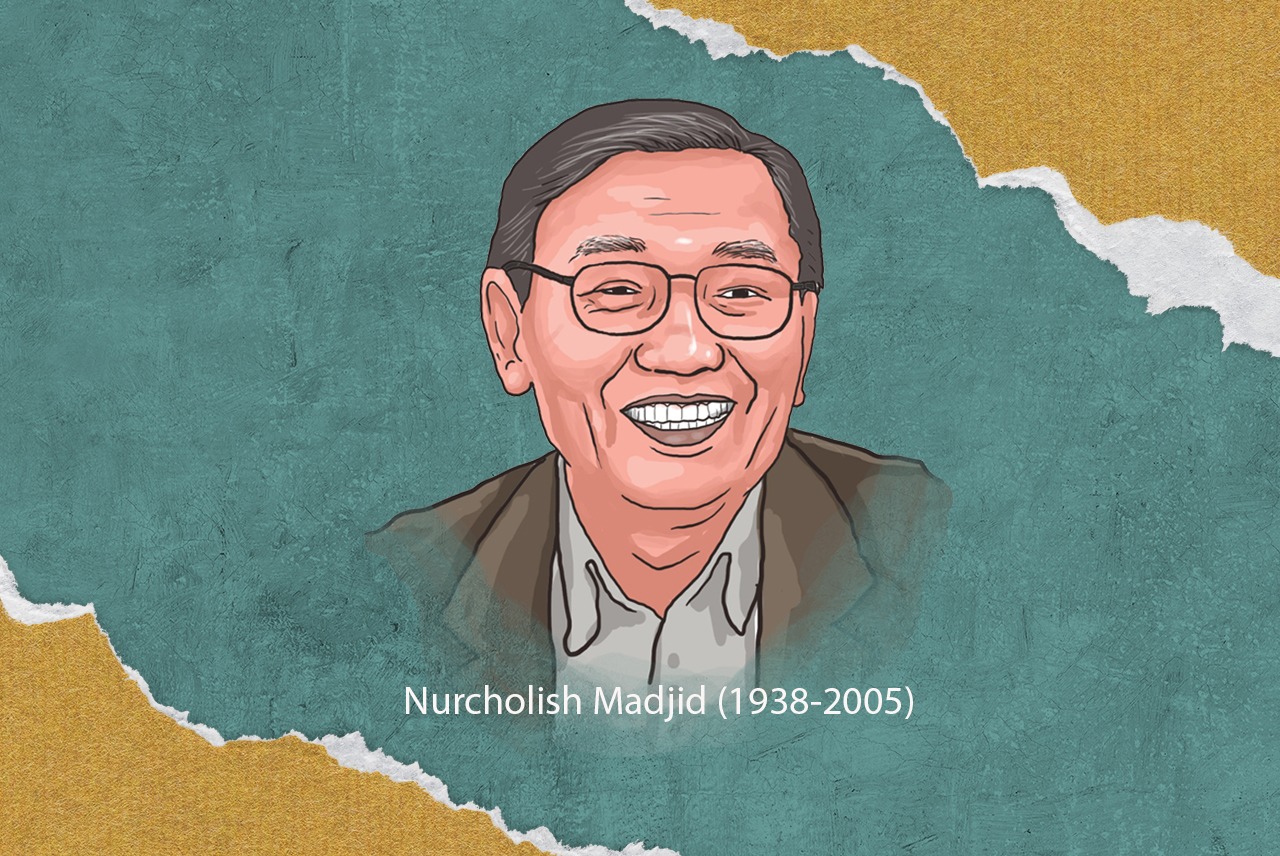Refleksi
Paradigma Baru Pendidikan Nasional
Teknologi informasi dapat menjadi alat pendorong ke arah demokratisasi.
Oleh ADI SASONO
OLEH ADI SASONO Model pendidikan nasional dewasa ini diuji oleh arus gelombang ketiga. Jika gelombang pertama bernuansa pola dominasi kegiatan agraris praindustri, gelombang kedua bernuansa budaya produksi-massa, pendidikan-massa, konsumsi-massa, dan media-massa, yang berskala raksasa. Pendekatan produksi-massa telah mendorong tumbuh pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkompartementalisasi dalam spesialisasi dan superspesialisasi karena...
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Fikih Peradaban dan Legitimasi Piagam PBB
Perbincangan fikih peradaban absen dalam kanon-kanon fikih yang ditulis para ulama.
SELENGKAPNYARoda Kehidupan Para Penjaja Kopi Keliling
Pedagang kopi starling sudah ada sejak 1999. Mereka memilih menggilas jalanan Ibu Kota dengan berjualan kopi keliling.
SELENGKAPNYAPeneguhan Kesadaran HAM di Indonesia (Bagian III/Habis)
Banyak pelanggaran HAM di Indonesia dianggap biasa saja.
SELENGKAPNYA