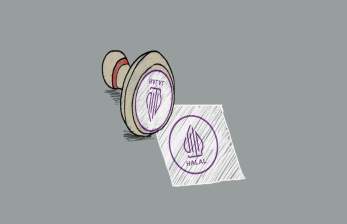Opini
Wajah Teknologi Pendidikan Kita
Sebanyak apa pun produk digital, guru akan tetap menjadi klaim keberhasilan pembuat platform.
IMAN ZANATUL HAERI; Kabid Advokasi Guru P2G, Wasekjen Hisminu Salah satu produk kebijakan pendidikan nasional paling dibanggakan Nadiem Makarim, lebih tepatnya produk kerja 400 orang tim bayangan adalah Platform Merdeka Mengajar (PMM). Dalam satu platform, guru bisa mengakses semua dokumen dan contoh praktik kurikulum baru. Termasuk produk percontohan para guru yang...
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Khalifah Pun Menjadi Kuli Panggul
Dia juga rajin menguping langsung dari rakyat dan menyaksikan praktik langsung kebijakannya di lapangan.
SELENGKAPNYAMenjaga Ibadah Sunnah
Di antara ibadah sunnah yang mesti kita jaga shalat sunnah Rawatib dan shalat Dhuha.
SELENGKAPNYAMemanen Jutaan Gigawatt Listrik dari Laut
Kalau arus laut, sumbernya jelas tersedia dan melimpah, tinggal mengambil.
SELENGKAPNYA