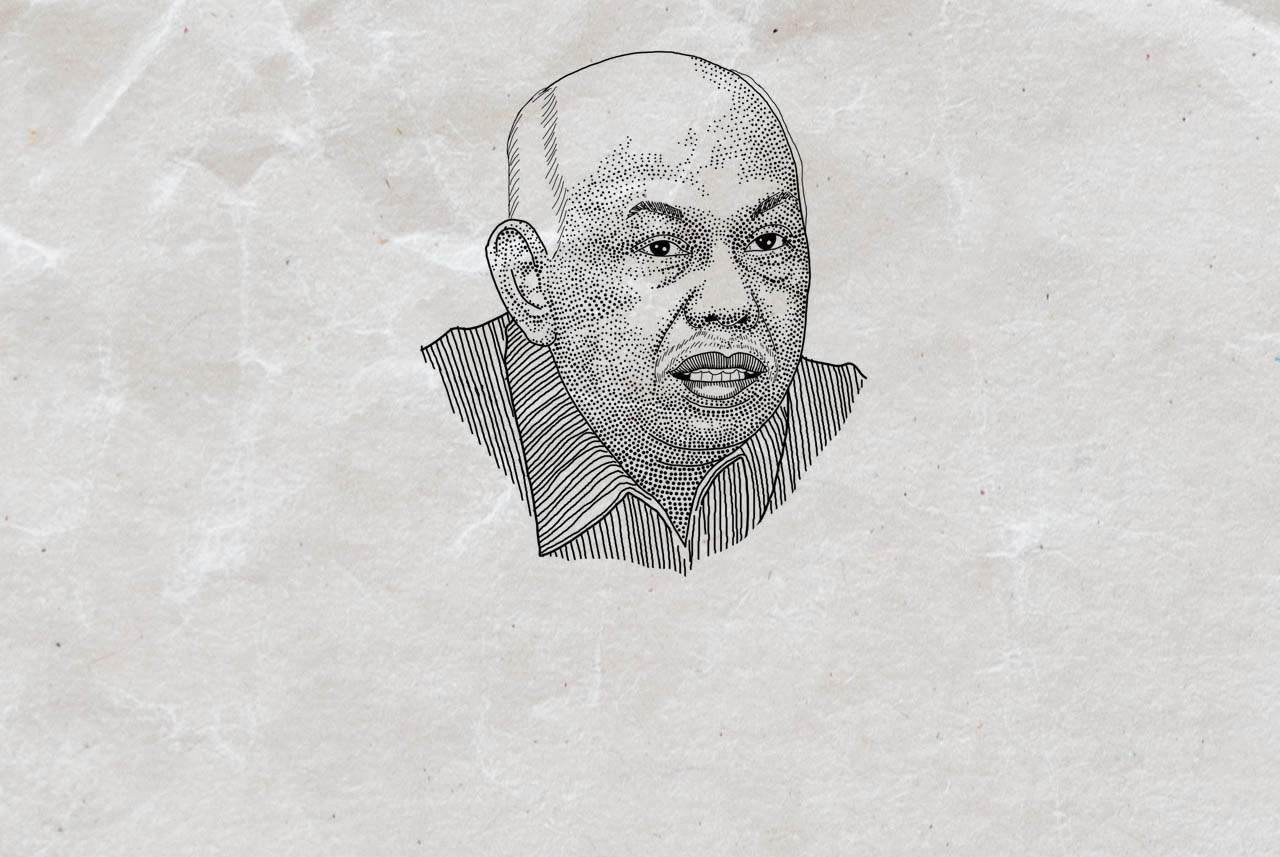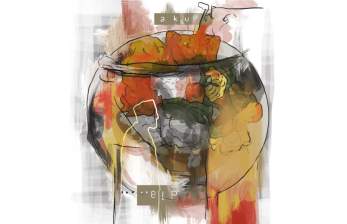Nostalgia
Jejak Romusha di Bayah
Sebagian besar jejak berdarah pembangunan rel kereta api Saketi-Bayah tersisa dalam cerita yang memudar.
OLEH M AKBAR Mentari kian meninggi ketika saya mengajak Sarjo (83 tahun) untuk meniti ulang sejarah hidupnya sebagai pekerja romusha di masa penjajahan Jepang di wilayah Bayah, Banten selatan. Saya menyapanya Mbah Sarjo. Kami mengajak lelaki tak beranak itu dengan mobil yang kami bawa dari Jakarta. Selepas shalat Zhuhur di rumah,...
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
HOS Tjokroaminoto, Orator dan Penggerak Perubahan
HOS Tjokroaminoto mengarahkan SI berhaluan nasionalisme yang merangkul seluruh suku bangsa di Tanah Air.
SELENGKAPNYASelamat Jalan Tokoh Istiqamah
Ia telah meninggalkan banyak legasi yang tak gampang digantikan.
SELENGKAPNYAIstiqamah untuk Keilmuan Islam
Kepakaran Azyumardi di bidang sejarah Islam telah menempatkannya sebagai ahli sejarah Islam kawasan Asia Tenggara yang sangat berpengaruh.
SELENGKAPNYA