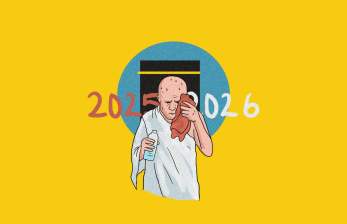Opini
Sinergi untuk Literasi
Masyarakat Indonesia secara umum tak bermasalah dengan kemampuan membaca aksara dan angka. Namun, aktivitas membaca belum jadi budaya.
SRI HARTONO, Pustakawan Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tersisihkannya literasi dari daftar trending topic berdampak pada peringatan International Literacy Day, 8 September 2022. Tak banyak ekspos tanggal penting tersebut sekalipun tema peringatannya sangat penting dan futuristis. Selain pustakawan dan pegiat literasi, hanya sebagian kecil kepala daerah yang masih...
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.