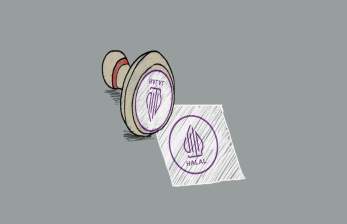Teraju
Menelisik Muasal Batik Peranakan
Krisis kain pada masa Kolonial Belanda melahirkan banyak sub-genre batik baru yang dikembangkan keturunan Belanda, Arab, dan Tionghoa di Indonesia. Mengawinkan banyak budaya dan kaya filosofi.
OLEH SIWI TRI PUJI B Batik encim, Anda mengenalnya kan? Dari namanya kita akan tahu dari genre mana batik ini berasal. Nama encim merujuk pada akar Tionghoa, kata encim berarti bibi dalam bahasa kaum Cina peranakan di Indonesia. Batik encim yang kita kenal saat ini masuk dalam sub-genre batik peranakan yang...
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Seleksi-seleksian Komisioner KPU-Bawaslu
Beredarnya nama-nama komisioner terpilih sebelum fit and proper test dan pelanggaran mekanisme seleksi, bisa menjadi beban bagi KPU periode 2022-2027.
SELENGKAPNYACina Jadi Pusat Mobil Listrik Dunia
Berdasarkan data Badan Energi Internasional, 2021 terjadi momentum terbaik kenaikan jumlah kendaraan listrik yang beredar di seluruh dunia.
SELENGKAPNYA