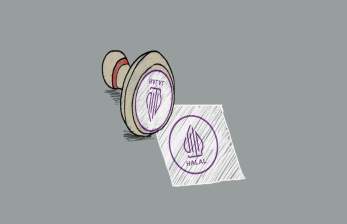Nostalgia
Monopoli Kain, Booming Kopi dan Jubah Putih Padri
Oleh FIKRUL HANIF SUFYAN, periset dan pengajar sejarah. Pernah menjadi dosen tamu dalam visiting scholar di Faculty of Art University of Melbourne Australia
Memasuki tahun 1667 sebuah catatan hubungan kerjasama hubungan perdagangan telah terjadi antara Barus dengan pialang asal Padang dan nahkoda dari Sungai Tarab. Dalam laporan diketahui, bahwa orang Aceh sudah mengkreditkan pakaian mereka untuk saudagar-saudagar yang bersandar di Barus. Mata uang emas sebagai alat tukar masa itu, mendorong Kompeni melakukan hal yang sama di Pantai Barat Sumatra.
Belanda meniru sistem yang diterapkan Aceh, untuk komoditi kain seharga 400 tail emas. Sistem pemberian kredit di muka tidak hanya dibatasi pada pialang terkemuka saja, juga pada pedagang kecil lada yang menempuh jarak jauh. Masa keemasan perdagangan pantai Barat Sumatra hanya bertahan sampai 1670an, karena terjadi perubahan kebijakan Kompeni terhadap pelayaran dan perdagangan swasta. Sehingga pada tahun 1686 kembali pemerintah mengeluarkan aturan monopoli perdagangan garam dan kain, untuk melindungi serangan dari Jawa (Marsden, 2008).
Lintas Perdagangan Kain di Pantai Barat Sumatra
Monopoli perdagangan kain Kompeni di pantai barat Sumatra, mulai dirasakan saudagar asal India tahun 1678. Puncaknya ketika para saudagar keling makin menipis persediaan kainnya, akibat perlawanan terhadap Eropa di Coromandel. Daerah pedalaman Minangkabau—terutama penghasil utama tekstil dan tenunan merupakan tujuan dari bahan kain asal India.
Nagari Pandai Sikek, dan Silungkang mempunyai selera untuk bahan kain tenun. Karena tidak ada jenis kain yang memenuhi selera pengrajin songket, keluhan demi keluhan diterima oleh perwakilan dagang India dan Kompeni di pantai barat Sumatra. Sehingga perlahan-lahan persatuan saudagar keling sudah kehilangan pelanggannya.
Perwakilan Kompeni melihat celah bisnis kain ini. Mereka pun memasok 1500 lebih bal kain per tahun, dan seluruhnya diborong pedagang dan pengrajin kain Darek dari tahun 1718-1749. Namun setahun kemudian, persediaan kain mereka menyusut hingga 80 persen di Pantai Barat Sumatra. Pada tahun 1750 keuntungan yang dihasilkan dalam perdagangan kain itu menurun drastis. Tercatat pada masa itu mereka hanya bisa menjual 550 bal/tahun saja (De Radicale Beschrijving van Sumatras Westkust, 1730).
Faktor penyebabnya adalah perpecahan di antara aliansi pialang, yang berujung jatuhnya harga lada pada titik terendah dan minimnya pajak pemerintah sebesar 402 ringgit. Melihat gelagat buruk ini, pejabat Kompeni di Padang meminta Batavia agar mengucurkan kredit ringan kepada para pialang—guna lepas dari krisis keuangan. Barang-barang yang dijual pada mereka harus dijajakan keliling dalam jumlah kecil pada para pembeli yang lebih miskin lagi. Setelah itu, barulah mereka bisa membayar jumlah emas yang telah ditentukan.

Kesulitan itu makin bertambah, ketika pada tahun 1770 harga emas kembali melonjak tajam. Hal ini tentu saja menjadi salah satu faktor menurunnya penjualan kain di Pantai Barat Sumatra dan berdampak pada pengrajin tenunan di pedalaman Minangkabau. Kenaikan harga emas yang tidak bisa dikendalikan Kompeni, menyulitkan para penjual kain membayar pinjaman uang emas kepada pemilik gudang pakaian di sekitar Muaro Padang.
Kompeni selanjutnya menyodorkan kredit ringan, untuk menggairahkan kembali perdagangan kain, lada, dan komoditi lainnya di pantai barat Sumatra. Memasuki pertengahan abad ke-18 perdagangan Kompeni di sekitar pantai Pariaman dan Padang mengalami kemacetan. Alasan utamanya, mereka tidak mampu lagi menyediakan berbal-bal tekstil untuk pedalaman Minangkabau.
Ketika mereka telah menyediakan kain yang dinginkan, Kompeni tidak bisa menjual kain tersebut semurah Inggris. Mereka kalah telak. Pialang Inggris, bahkan sudah memasuki Luhak Tanah Datar untuk mencari emas dan dibarter dengan berbal-bal kain murah di tahun 1750. Situasi yang menguntungkan pialang Inggris tersebut merangsang pedagang keliling dan penenun songket berdatangan ke tepi pantai. Untuk bagian Air Bangis pada tahun 1766 telah tersandar 200 perahu Inggris dari Madras (Modern Asian Studies Vol VIII, 1974: 31).
Pada 1790 perdagangan emas mengalami penurunan, dan Kompeni mengeluarkan kebijakan menerima mata uang—sebagai persentase potongan penjualan kain di Padang. Kondisi ini tentu menguntungkan etnis Cina di Padang. Sebab mereka memiliki mata uang sendiri dan memungkinkan bertindak sebagai pialang tunggal dalam perdagangan kain. Aturan kompeni juga berimbas pada patahnya dominasi pialang Minangkabau, yang selama ini mengandalkan emas sebagai alat tukar kain.
Komoditas kain pada periode berikutnya, menjadi poin terpenting dalam perdagangan di pantai barat Sumatra, setelah permintaan pengrajin tenunan meningkat tajam di awal abad ke-19. Permintaan kain polos putih juga mengalami kenaikan, berasal dari pesanam pemimpin tarekat, maupun murid-muridnya yang beraliran Syattariyah dan Naqsyabandiyah. Meningkatnya permintaan helaian kain putih, juga datang dari calon haji—yang kaya mendadak pasca booming kopi dan akasia.
Jubah, Turban, dan Burqa dalam Identitas Padri
Perjumpaan Padri dengan ajaran Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1787) terjadi, ketika Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piobang pulang dari Mekah pada tahun 1803. Ketiga haji asal Tanah Datar selama bermukim di Mekah telah menerima ajaran—yang oleh pengikut aliran ini, menolak disebut wahabi, dan seharusnya mereka disebut muwahhidun (mengesakan Allah).
Kuatnya pengaruh pemikiran Ahmad ibn Hanbal dan Ibn Taimiyah, turut memengaruhi Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piobang mengamalkan beberapa anjuran Nabi Muhammad dan mengadopsi gaya berbusana selama mereka bermukim di Mekah.
Identitas kaum Padri—terutama memanjangkan jenggot, bila ditelisik bersesuaian dengan riwayat Ibnu Umar, “Potonglah kumis dan biarkanlah jenggot..” Ketiga haji itu tentu memahami, kata u’fu (potonglah) bermakna cukurlah sebagian darinya hingga dia menjadi tipis—termasuk sunnah untuk mencukur kumis, atau tidak membiarkannya tumbuh panjang.
Selama bermukim di Mekah, Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik dengan pengalaman empirisnya beradaptasi dengan kebiasaan laki-laki Arab merawat jenggot mereka, dan tidak membiarkan kumisnya tumbuh lebat.
Tidak sebatas identitas lahiriah, model busana ketiga Haji itu nantinya menjadi rujukan Tuanku nan Renceh, Tuanku Lintau, dan pengikut Padri lainnya. Mereka merujuk pada hadist nabi tentang keutamaan memakai jubah dan celana cingkrang). Produk budaya dan rujukan sumber hukum Islam—kemudian menjadi pedoman Tuanku nan Renceh, menyerukan laki-laki di nagari Kamang untuk shalat, memelihara jenggot, berjubah, tidak boleh mengisap candu, makan sirih, dan mabuk (Kepper, 1900; Indisch Magazijn 12/1, No. 7. 1844:1; Lange, 1852: 20-21; Martamin, 1984).
Ketika busana seorang muslim Arab, identik dengan jubah dan turban—larangan bertasyabbuh sesungguhnya ditujukan pada hal-hal di luar kebiasaan yang dilakukan Nabi Muhammad. Tidak mengherankan, bila kerasnya aturan berjubah dan menghindari sikap tasyabbuh—menjadi otoritas Tuanku Nan Renceh—yang harus dipatuhi rakyat Kamang.
Untuk perempuan, Tuanku Nan Renceh menganjurkan memakai busana gamis yang menutup seluruh bagian tubuhnya, cadar, dan larangan memakan sirih. Seperti pada foto 9 (kanan) terlihat perempuan yang berbaju kurung, dan menutupi rambutnya dengan sehelai selendang. Jenis busana yang lazim dipakai sebelum Padri, dilarang Tuanku Nan Renceh. Ia menginginkan model busana gamis, kerudung yang menutupi dada, dan burqa. Seluruh aturan Tuanku Nan Renceh itu wajib dipatuhi semua perempuan—bila dilanggar akan diberi sanksi.
“Siapa yang mencukur jenggot didenda 2 suku, yang memepat gigi didenda seekor kerbau, lutut yang tidak ditutup didenda 2 suku, perempuan yang tidak menutup muka didenda 3 suku, perempuan yang bertengkar didenda 5 suku, orang tua yang memukul anak didenda 2 suku, memanjangkan kuku didenda 2 suku, riba didenda 5 kepang, meninggalkan shalat sekali didenda 5 suku, kalau lebih dihukum mati” – demikian aturan yang diterapkan oleh Tuanku Nan Renceh.
Selain mengatur busana, Padri melarang seorang laki-laki memakai pakaian dari sutra. Aturan itu diduga merujuk riwayat Umar bin Khattab dan Hudzaifah bin Yaman, bahwa laki-laki yang berbusana sutra akan menyerupai perempuan yang suka kepada perhiasan. Sedangkan seorang muslim dituntut tegar, mempunyai kekuatan, dan jantan. Pemakaian bahan sutra diperbolehkan, bila sutra itu seukuran dua jari, atau empat jari, dan menempel dengan bahan kain lain. Namun, bila seluruh busana terbuat dari bahan sutra, maka haram untuk si laki-laki.
Jubah Padri dan Booming Kopi
Darimana sumber bahan sutra yang tersebar di pantai Barat Sumatra? Dalam catatan De Stuers, pada tahun 1820 orang-orang Cina masih menjual benang sutra ke penenun Pandai Sikek dan Silungkang. Bahkan masa itu, orang-orang Cina sampai akhir abad ke-19, memasok kain dan porselen dari Penang dan Singapura. Keadaan orang-orang Cina yang bermodal besar, menunjukkan kemampuan mereka secara finansial berbeda dengan pialang asal Minangkabau. Pada tahun 1824 mereka digambarkan sebagai orang-orang kaya yang mendiami rumah yang lebih baik di Kampung Pondok atau Kampung Pecinan (De Vestiging en Uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra, 2 vol. Amsterdam, 1849).
Lancarnya produk sutra masuk ke pedalaman Minangkabau, tentu mengundang tanda tanya besar—mengingat Paderi masih berkuasa di pedalaman Minangkabau. Larangan berbusana sutra rupanya tidak dipedulikan keluarga bangsawan, penghulu, dan orang-orang kaya.
Di kalangan Padri—untuk bahan jubah putih dan serban putih, umumnya terbuat dari kain katun, bukan bahan sutra. Tuanku Lintau yang mengetahui basis transaksi kain katun berada di Sungai Indragiri dan Lubuk Jambi—ia pun ingin menguasai daerah perdagangan kopi asal Lintau dan Buo. Namun, ia menemui kendala di Lubuk Jambi, karena komoditas dagang mereka diboikot.
Pada tahun 1823 Tuanku Lintau mengerahkan 1200 tentaranya dan membakar sebagian besar daerah Lubuk Jambi. Dua tahun pasca serangan sporadis Padri, di Pelalawan Pantai Timur Sumatra telah diramaikan dengan impor kain katun putih dan berwarna asal Singapura.
Kisah membanjirnya kain katun di Pantai Timur, bermula dari kepuasan pialang Singapura terhadap murahnya harga jual kopi asal Luhak Limopuluah Koto, senilai 9,60 gulden per setengah pikul. Harga itu jauh lebih murah, ketimbang membelinya di Pantai Barat Sumatra. Tidak mengherankan, bila setiap pekan di Halaban dan nagari-nagari lainnya mereka menggelar kain katun putih, berwarna, dan sutra asal Singapura (Muller, 1855: 29).
Di tengah berkecamuknya Perang Padri, identitas jubah putih dan serban sempat dilarang Kompeni. Larangan memakai jubah juga diberlakukan di Jawa. Kompeni menganggap huru-hara di Sumatra Barat dan Jawa disebabkan identitas jubah yang kerap menjadi simbol perlawanan. Selanjutnya jubah diasosiasikan sebagai penebar kekerasan. Van Dijk mensinyalir, bahwa perlawanan rakyat terhadap VOC pada 1670-an di Banten disebabkan banyak orang menanggalkan pakaian Jawa dan beralih pada busana Arab (Schulte Nordholt, 2009) .
Ketika bermukim di Mekah, Snouck Hurgronje (1959: 1335) mencatat bahwa orang-orang dari seluruh Nusantara sangat antusias membicarakan perlawanan Aceh terhadap Kompeni. Jemaah haji yang berkumpul di Mekah, kemudian hidup dalam suasana anti kolonialisme (Van Koningsveld, 1989). Sehingga perjalanan spiritual di Tanah Haram sudah beralih menjadi pemersatu dan perangsang anti kolonialisme. Karena citra yang dibangun Kompeni demikian buruk, berimbas pada respon umum, bahwa para haji itu adalah penghasut dan pembuat onar.
Di tengah berkecamuknya perlawanan Padri dan Diponegoro, Kompeni mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk membatasi pengaruhnya lewat syarat-syarat naik haji. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah tahun 1825 dan 1831 berupa penetapan biaya paspor yang mahal untuk jamaah haji asal Jawa dan Madura. Mereka juga dikenai denda yang besar, bila tidak mengikuti aturan. Namun, biaya selangit yang ditetapkan Kompeni, rupanya tidak mampu membendung hasrat calon jemaah haji menuju Tanah Haram.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.