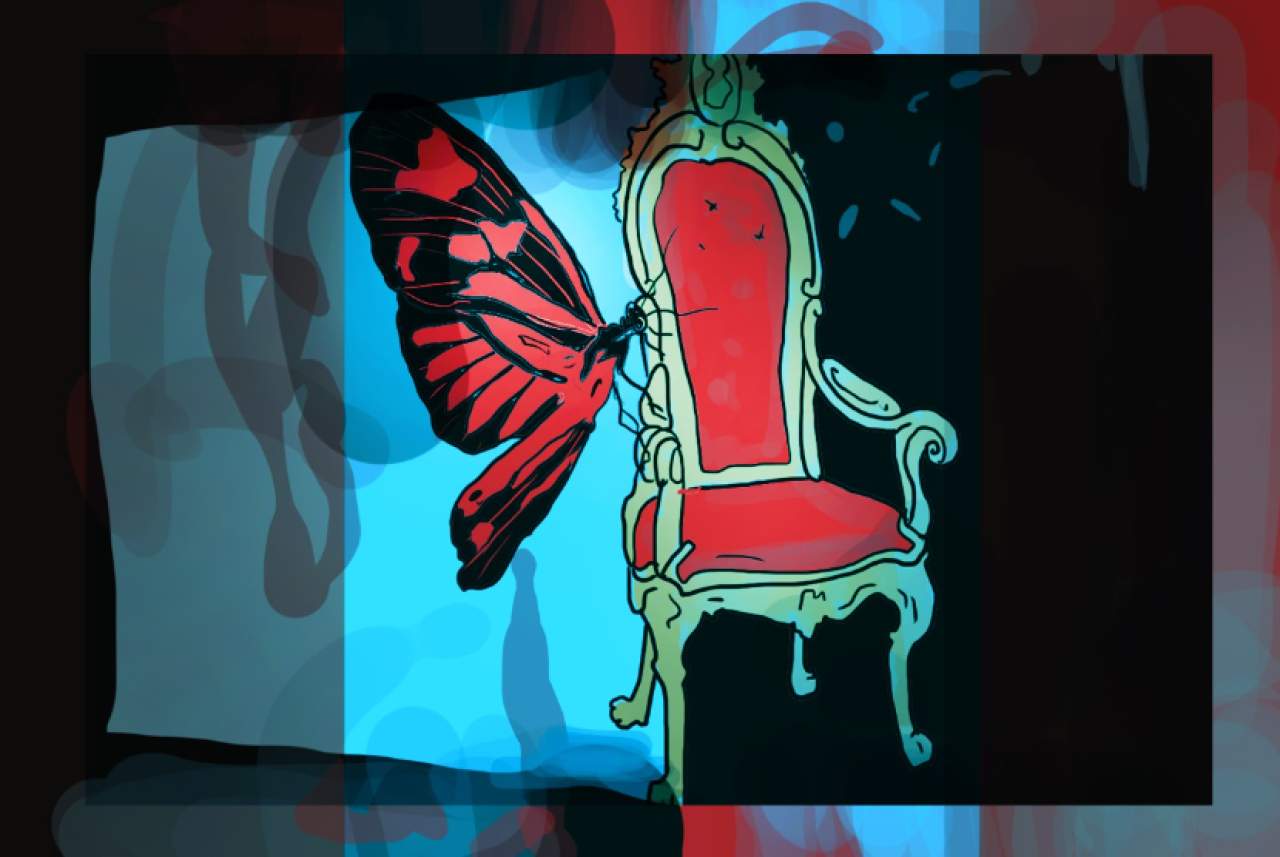Sastra
Tabungan Haji
Cerpen Ali Satri Efendi
Oleh ALI SATRI EFENDI
Takwim masih ingat sekali saat itu, ketika ia pulang lebih cepat karena di sekolah hanya ujian praktek shalat saja. Abah mengajaknya pergi ke bank dan mengisi beberapa lembar formulir dengan lampiran fotokopi akta kelahirannya dan kartu keluarga. Tabungan akhirat, siapa tahu dapat panggilan, kata Abahnya setelah selesai semua proses. Beberapa tahun kemudian, ia baru mengerti kalau yang Abah lakukan adalah membuka tabungan haji.
Kenangan lima belas tahun lalu itu tiba-tiba terlintas di benaknya ketika ia melihat berita di televisi di sebuah restoran Padang. Persiapan pemerintah untuk keberangkatan jamaah haji Indonesia tahun ini. Ia juga teringat cerita Abahnya beberapa waktu lalu, Uwak Aini, tetangganya di kampung pernah menangis beberapa hari karena keberangkatannya ke Tanah Suci batal lantaran pandemi. Sayangnya, ketika pengiriman jemaah haji dibuka kembali, Wak Aini sudah pergi ke tanah kubur. Lalu putrinya yang menggantikan ibadahnya tersebut beberapa tahun kemudian.
Takwim sendiri heran, di kondisi serba sulit seperti ini - PHK dimana-mana, harga kebutuhan pokok naik, rupiah semakin lemah, kebijakan-kebijakan pemerintah bikin naik pitam - masih banyak orang yang bisa berangkat haji.
“Enggak puasa, lo?” Rekan kerja Takwim membuyarkan ingatannya. Ia melihat piring di depan Takwim yang tandas menyisakan bercak sambal hijau.
“Lo sendiri?” Takwim balik tanya sambil mengambil gelas teh.
“Sudah kemarin,” jawab rekannya sambil melihat lauk-pauk di etalase. Takwim hanya tersenyum mengejek. Pertanyaan rekannya tadi seolah membawanya melompat dari kecamuk pikiran ke rumah makan yang buka diam-diam di penghujung Ramadhan.
Bulan puasa tinggal beberapa hari, tapi tidak sekalipun Takwim melaksanakan kewajibannya sebagai umat. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Baginya, Ramadhan dan bulan-bulan lain itu serupa. Bedanya, di bulan ini ia bisa jajan menu takjil seperti orang-orang yang berpuasa, tapi menikmatinya sebelum waktu berbuka.
Jika dirunut ke belakang, kelunturan taatnya itu berawal sejak masa-masa terakhir ia kuliah. Perkenalannya dengan banyak orang dengan berbagai pandangan mereka. Lingkaran pergaulan yang jauh berbeda dari teman-teman di sekolahnya. Acara-acara yang ia hadiri. Tempat-tempat yang ia kunjungi. Hingga pergeseran-pergeseran pandangan yang ia terima. Padahal dulu waktu ia belajar di madrasah tsanawiyah dan aliyah, puasanya tidak pernah bolong. Tadarus tidak pernah ditinggal dan ia paling rajin datang ke pengajian. I'tikaf di masjid pun jarang ditinggalkan. Ia sendiri menyadari, banyak sekali perubahan yang ia alami. Tanpa ada yang ia sesali.
Ponselnya berdering. Sebuah panggilan dari Kakaknya di kampung. Sudah lama juga ia tidak menelepon keluarganya. Kalau begini pasti ada yang penting.
Betul saja.
***
Akhir pekan belum juga tiba. Senang-senang di Sabtu-Minggu juga baru rencana. Tapi mau tidak mau Takwim harus ambil cuti untuk pulang kampung. Dikna, kakak keduanya bilang, kondisi Abahnya memburuk lagi. Ia terkulai di tempat tidur sepanjang hari. Padahal dua minggu lalu ia begitu semangat mempersiapkan panen perkebunan mangga yang sebentar lagi. Ia sudah berkoordinasi dengan petani-petani setempat. Karung-karung baru pun sudah ia pesan dari Paman di Karawang. Tapi esoknya dokter sudah mondar-mandir ke rumah hampir setiap petang.
Kondisi ini sudah terjadi berulang berkali. Berulang pula Abahnya bisa membaik kembali dengan sendirinya. Usia di atas tujuh puluh memang rentan dengan berbagai penyakit, pikirnya. Tapi Dikna khawatir akan terjadi apa-apa kali ini. Apalagi Abahnya terus menanyakan kabar anak bungsunya itu di Ibukota. Oleh karena itu, Takwim memutuskan untuk pulang saja dan meninggalkan rencana-rencana akhir pekan yang telah disusun matang. Untung saja, perjalanan ke kampung halamannya tidak begitu jauh dan belum pula memasuki puncak arus mudik. Mobil yang ia kendarai masih dapat melaju lancar. Biasanya – apapun yang terjadi - ia pulang kampung sehari menjelang lebaran. Malah ia pernah pulang kampung setelah lebaran karena banyak acara perusahaan yang harus ia urus. Tapi entah, barangkali karena begitu banyak kenangan yang belakangan terlintas, semua pekerjaan ia alihkan sementara pada rekan-rekannya. Atasannya pun menerima ketika ia ajukan formulir cuti di meja.
Sesampainya di rumah yang membentuknya itu – paling tidak sampai usia delapan belas tahun - Takwim dipeluk oleh Dikna yang mengucap syukur dengan sangat. Ia perempuan yang masih lajang dan satu-satunya yang diandalkan untuk mengurus rumah tersebut sehari-hari. Kakaknya ini juga yang belakangan sibuk mengatur urusan perkebunan yang sebetulnya tidak seberapa, tapi hasilnya sudah berjasa menyekolahkan Takwim dan saudara-saudaranya. Di ruang tamu, Takwim juga bertemu dua kakak laki-lakinya yang merantau tidak begitu jauh dari kampung halaman. Sementara kakak perempuannya yang nomor tiga belum bisa pulang karena tinggal dengan keluarga kecilnya di beda pulau.
Dikna lalu mengajak Takwim ke kamar Abahnya segera setelah ia meletakkan ransel di bangku ruang tamu. Sepanjang langkah singkat tersebut, mata Takwim berkeliling ke penjuru ruang yang ia lewati. Kembali terlintas di benaknya berbagai kenangan yang ia pahat di rumah ini. Di ruang tamu itu ia dan teman-temannya biasa menonton kartun di hari minggu dan Abahnya yang senang sekali menonton siaran berita. Dari dapur selalu terhembus aroma masakan Ibu. Di ruang makan itu ia pernah menjatuhkan mangkuk besar yang berisi butir-butir telur balado yang baru dimasak ibunya. Setelah itu ia berlari ke rumah tetangga karena takut terkena omelan. Di samping lemari itu ia kerap bersembunyi ketika bermain petak umpet. Pernah juga di bawah kursi itu. Ah, banyak hal yang tidak berubah dari rumah ini, pikirnya.
Pintu kamar Abahnya terbuka. Di dalam terlihat Ibunya yang tengah menemani. Takwim mencium tangan dan memeluk ibunya. Kenangan kembali berkelebat ke hari ia memutuskan untuk tinggal di rumah kost di Ibukota. Ketika itu terdengar jelas isakan ibunya di telinga, seolah tidak bisa menerima pendewasaan anak terakhirnya ini. Isakan yang kembali ia rasakan sore itu. Cuma Takwim tidak secengeng dulu yang sebetulnya juga berat meninggalkan rumah tersebut.
Kemudian ia duduk di samping sang Abah dan mencium tangannya. Ia seolah bertemu kembali dengan tangan yang tidak pernah lelah menggendongnya dulu ketika kecil. Lamat-lamat ia bisa mengingat aroma minyak wangi untuk shalat yang tersebar di buku-buku jari Abahnya. Aroma kasturi yang telah ia pakai puluhan tahun. Bahkan teman-teman masa kecil Takwim yang sering main ke rumah akrab dengan wangi tersebut. Ibu atau Kakaknya pasti rutin mengoleskan minyak tersebut tersebut ke tubuh Abah, pikirnya. Sejenak Takwim tidak tahu musti berkata apa. Ia cuma bisa merasakan genggaman tangan yang begitu lemah. Semangat yang masih bergemuruh belasan tahun silam seolah tandas sudah.
Rupanya Abah sadar dengan kehadiran anak bungsunya ini. Ia berusaha membuka matanya dengan penuh kepayahan. Pun dengan usaha yang sama ia buka mulutnya amat perlahan.
“Wim...” itulah kata yang akhirnya bisa Abahnya ucapkan dengan lirih dan hela nafas yang enggan.
“Iya, Abah. Takwim disini,” jawabnya perlahan.
Takwim bisa merasakan kondisi Abahnya saat ini tidak seperti kondisi sakit ia sebelumnya. Rasa khawatir seketika merajamnya. Entah, apakah ia bisa menyembunyikan kekhawatirannya itu atau tidak. Rasanya ia tidak mampu mengambil kendali sampai sejauh itu. Padahal harusnya itu mudah ia lakukan. Bertahun-tahun ia tinggal jauh dari kampungnya, dari rumahnya. Mengobrol dengan kedua orang tuanya pun seperlunya. Ia tidak bisa lagi mengikuti cerita Ibunya tentang Para Penceramah baru yang ada di TV. Ia juga tidak bisa mengobrol tentang hukum-hukum agama dengan Abahnya lagi. Rasanya ceramah terakhir yang ia dengar adalah ceramah almarhum Ustaz Jefri Al Buchori bertahun silam.
Mana mungkin juga Takwim bercerita tentang pengalaman menemani beberapa klien ke kelab, prestasinya untuk tidak mabuk walau menenggak beberapa gelas minuman beralkohol dan pergaulannya dengan selebgram-selebgram populer. Walaupun Ibunya pernah tanya macam-macam ketika wajahnya terpampang di stories sedang hura-hura bersama teman-teman. Ini berkat laporan Dikna yang kadang rajin scrolling stories sampai ujung.
Tapi melihat kondisi Abahnya saat ini, jarak yang sekian lama menganga seolah rapat seketika. Entah melalui pintasan dimensi yang mana. Ia merasa betul-betul pulang ke rumah.
“Wim...” Abahnya mencoba berkata lagi, “haji...haji...” kali ini Takwim merasa genggaman tangan Abahnya lebih kuat. Takwim mencoba memahami apa yang dimaksud Abahnya.
“Iya, Abah,” jawabnya agar Abah tidak bersusah payah menjelaskan. Ia pikir Abahnya pasti mencoba mengingatkan supaya ia jangan lupa menunaikan ibadah haji jika mampu. Takwim tidak pernah terpikir untuk melaksanakan rukun Islam kelima itu. Malah rencananya yang paling dekat adalah ia dan beberapa temannya akan melancong ke beberapa negara Eropa awal tahun depan.
Seperti sudah mendapatkan instruksi dari Abah, Ibunya lantas melangkah menuju lemari. Ia buka sebuah laci dan mengambil sebuah buku kecil. Lalu ia serahkan buku tersebut ke tangan Takwim.
Sayup-sayup Takwim seolah mengenal buku kecil nan tipis ini. Ia buka lembar per lembar. Sebuah buku tabungan haji.
“Kamu bisa berangkat tahun ini, Wim,” kata Ibunya melanjutkan maksud yang baru saja diutarakan Abahnya.
Dengan bingung, Takwim memandang wajah Ibunya yang masih menyisakan isak. Lalu beralih ke wajah Abahnya. Takwim tidak bisa bertanya-tanya lagi.
“Haji... Wim...” ujar Abahnya lagi dengan sisa semangat yang masih ada.
***
Sehari setelah Takwim menerima buku tabungan haji tersebut, Abahnya pulang ke pangkuan Tuhan. Sepanjang tiga hari masa berkabung, Takwim terkadang mencuri waktu menggenggam dan melihat-melihat buku tersebut. Kadang di kamarnya. Kadang di kamar Abahnya. Kadang tertegun di perkebunan. Ia lebih merasa, ini sebuah hukuman untuknya daripada rejeki.
Di hari terakhir keberadaanya di rumah yang hampir tidak pernah berubah itu, Ibunya memergoki ia melamun memegang buku tabungan haji tersebut. Ia lantas berujar, itu amanah terakhir dari Abah. Jangan ragu-ragu. Takwim cuma bisa tersenyum.
Dan begitulah. Banyak yang tidak menyangka dengan keputusan Takwim untuk melaksanakan haji tahun itu. Teman-temannya bilang, Takwim habis di rukyah di kampung. Rekan kerja satu perjuangannya di Warung Padang bilang, Takwim sedang mabuk hijrah.
***
Empat puluh hari setelah Lebaran akhirnya Takwim berada di Masjidil Haram. Ia bertekad, cukup mengikuti pemimpin jemaah saja, tanpa melakukan tambahan ibadah seperti yang dilakukan jamaah lain yang jarang kembali ke kamar. Banyak waktu yang justru ia habiskan untuk melihat smartphone-nya, baik untuk memeriksa pekerjaan, atau sekedar berselancar di media sosial. Tapi ia enggan mengunggah foto ketika beribadah, seperti yang dilakukan banyak orang.
Suatu hari, gawainya hilang. Takwim tidak tenang seharian. Seketika tidak ada apapun yang bisa ia lakukan. Lalu ia pikir, daripada suntuk di hotel, ia putuskan menemani teman sekamarnya untuk pergi ke Masjidil Haram. Namun Takwim tidak ingin mengikuti temannya itu mendekat ke Ka'bah. Mereka pun berpisah, Takwim memutuskan menyaksikan para jemaah saja dari sisi terjauh hajar aswad.
Tapi diantara begitu banyaknya langkah yang tidak pernah putus, Takwim mendapati satu sosok yang berdiri memandangnya. Pandangan yang mampu menembus tubuh-tubuh yang menghalangi. Takwim seolah ditarik oleh pandangan tersebut. Ia mengenal sosok tersebut.
“Abah...”
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Kartini dalam Puisi Akrostik
Puisi Akrostik adalah jenis puisi yang menggunakan huruf awal dari setiap baris.
SELENGKAPNYA