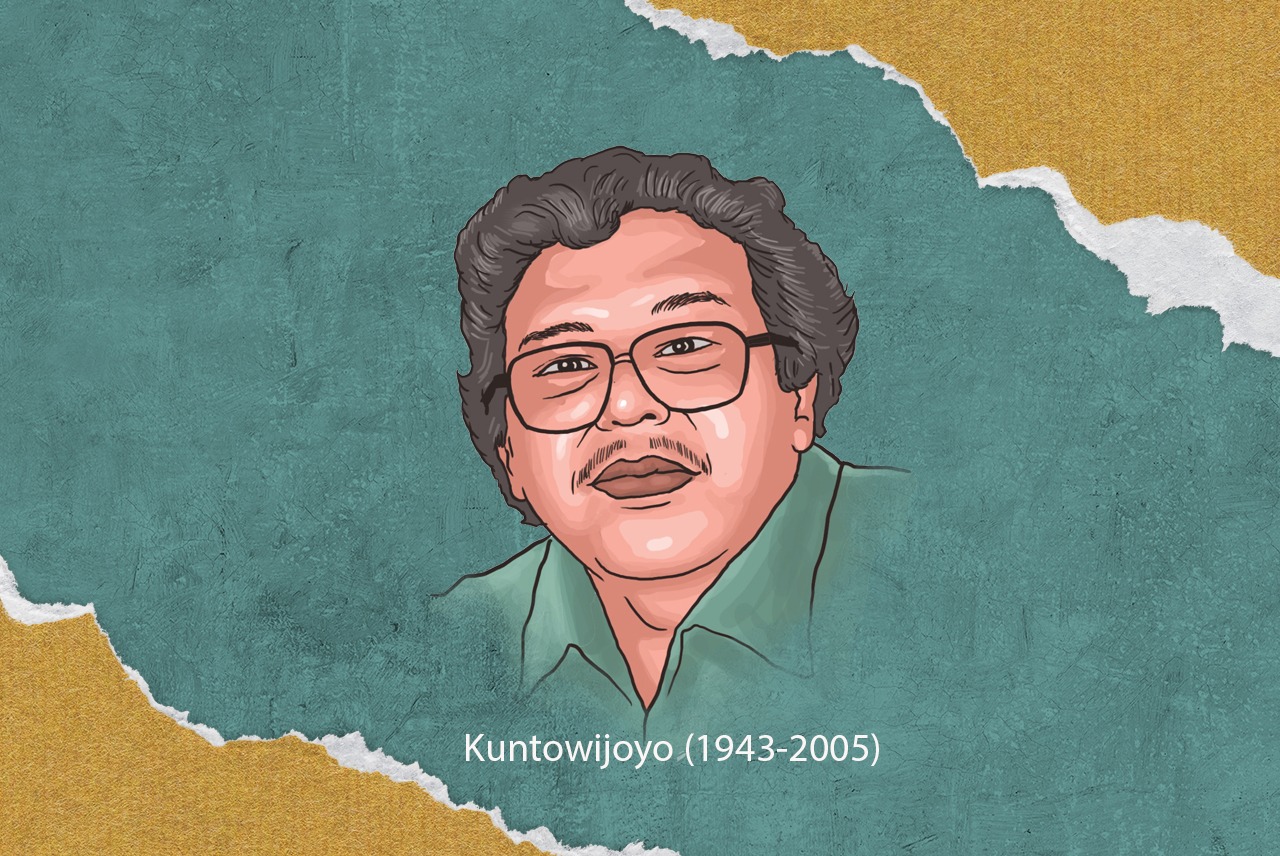
Refleksi
Islam dan Strukturalisme Transendental (Bagian IV)
Dirasa perlu suatu ijtihad baru mengenai masyarakat industrial.
Oleh KUNTOWIJOYO
Kesadaran Sejarah. Ada continuum dari kesadaran individual ke kesadaran kolektif ke kesadaran sejarah. Kaum muslimin baru sampai pada kesadaran individual. Gambaran tentang masa depan (eschatology) hanya dikaitkan dengan individu, tak pernah dengan umat, apalagi dengan sejarah umat. Kesadaran kolektif sebagai umat sudah lama ada, meskipun belum merata. Kesadaran sejarah...
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Islam dan Strukturalisme Transendental (Bagian III)
Perluasan kesadaran individual itu sayangnya sampai kini hanyalah pada kesadaran jamaah.
SELENGKAPNYAIslam dan Strukturalisme Transendental (Bagian II)
Epistemologi dalam Islam adalah epistemologi relasional.
SELENGKAPNYAIslam dan Strukturalisme Transendental (Bagian I)
Islam juga mengalami transformasi secara spasial, historis, dan sosial.
SELENGKAPNYA






