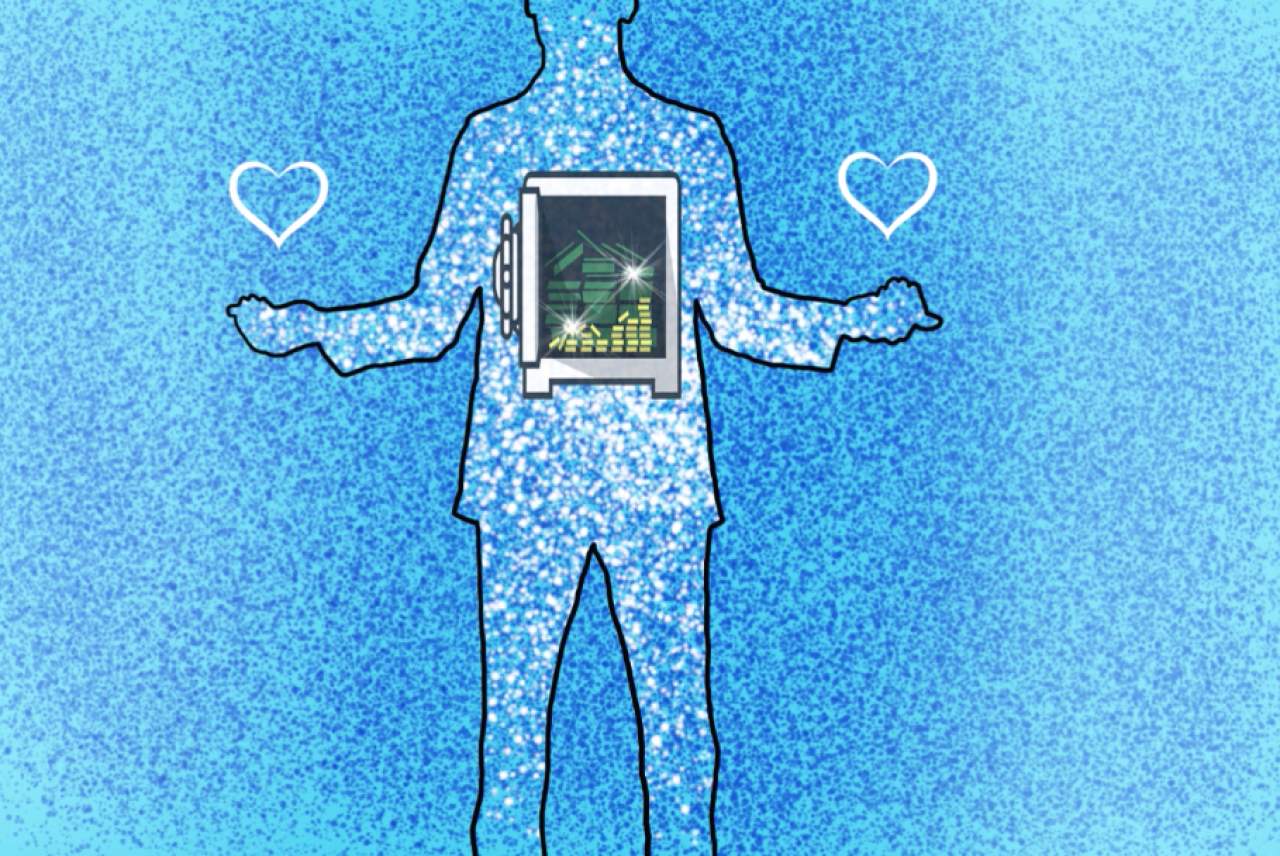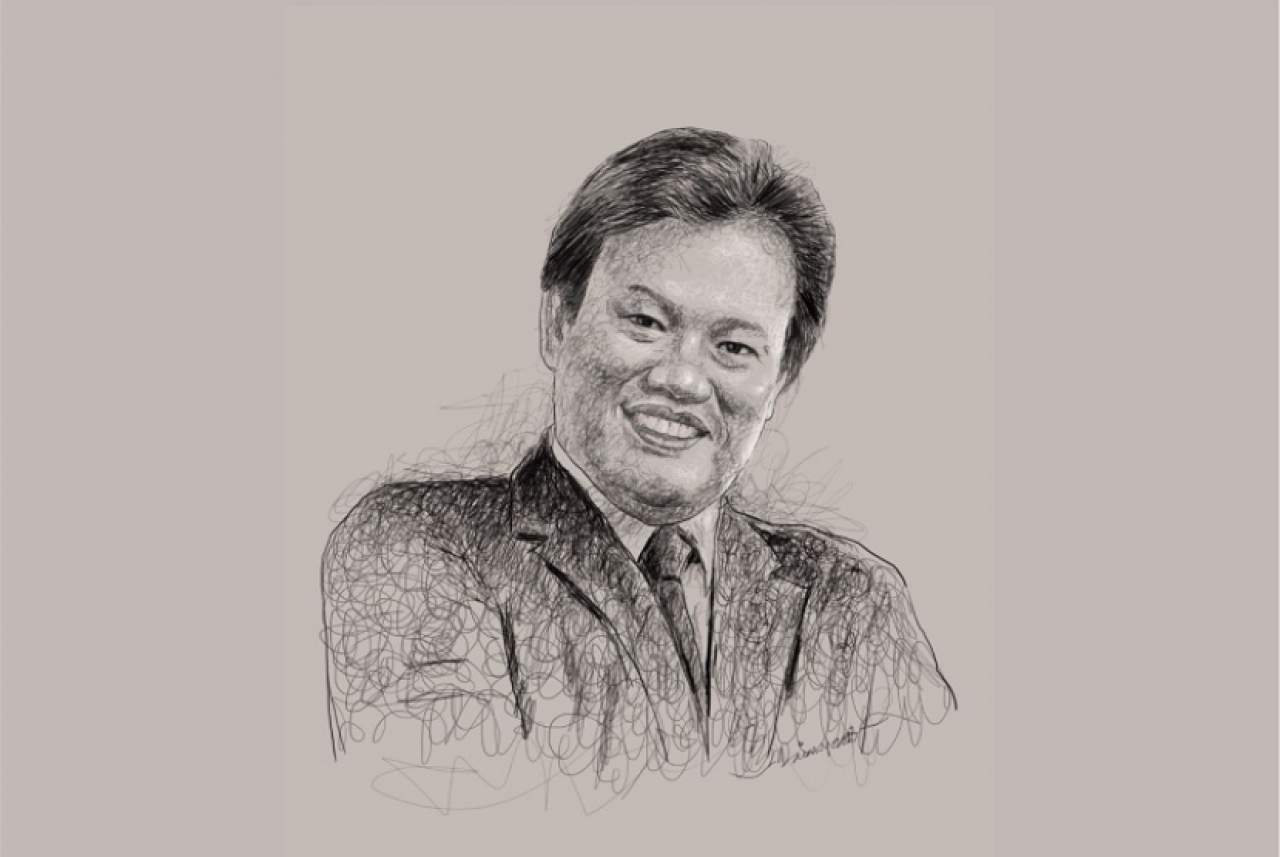
Analisis
Kebijakan Gas Sebagai Energi Transisi
Keberlangsungan investasi di industri gas menjadi pilar penting untuk mewujudkan gas sebagai energi transisi.
Oleh SUNARSIP
Indonesia merupakan negara yang cukup agresif dalam menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)-nya. Dalam dokumen updated nationally determined contributions (updated NDC’s) atau target kontribusi penurunan emisi GRK yang ditetapkan secara nasional, Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89 persen (sebelumnya 29 persen) tanpa dukungan internasional pada...
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Merevitalisasi Harta Sebagai Media Kebajikan
Eksistensi harta adalah alat dan wasilah atau media untuk tujuan yang baik.
SELENGKAPNYAIroni Sawit: Eropa yang Tanam, Eropa yang Larang
Industri sawit dan banyak komoditas sawit dipicu kolonialisme.
SELENGKAPNYA