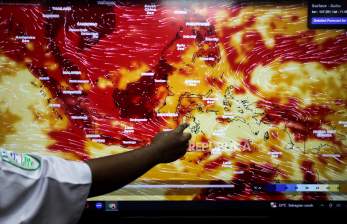Kronik
Refleksi Krisis Asia 1997-1998
Krisis ekonomi moneter di Indonesia lebih banyak disebabkan faktor-faktor luar neger.
Oleh JUWONO SUDARSONO
Pergantian pemerintahan Indonesia dari Presiden Soeharto ke Presiden BJ Habibie pada 21 Mei 1998 merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian krisis ekonomi dan politik seluruh Asia-Pasifik yang resminya dimulai pada 2 Juli 1997 di Thailand. Seperti juga di Korea Selatan dan Thailand, krisis ekonomi moneter di Indonesia lebih banyak disebabkan...
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Riwayat 32 Tahun Pemerintahan Soeharto (1967-1998)
Soeharto terpaksa menerima desakan reformasi politik.
SELENGKAPNYABunga-Bunga Api Menjelang Perubahan
Kerusuhan meletus di seantero negeri menjelang lengsernya Presiden Soeharto.
SELENGKAPNYA