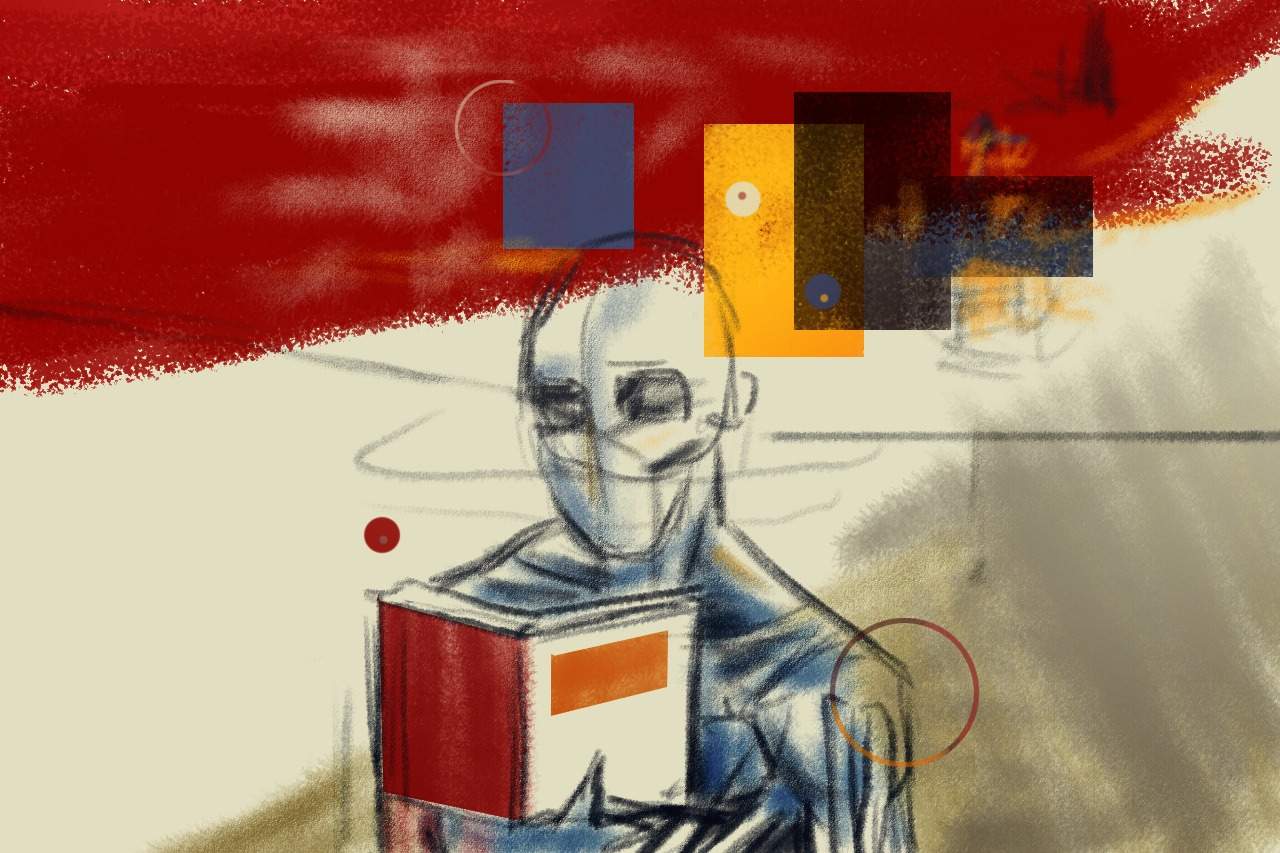
Sastra
Kursi Kosong dan Sandiwara
Cerpen Musafir Kelana
Oleh MUSAFIR KELANA
Ketulusan guru di sekolah ini kandas menghitung angka ganjil di kepala. Sementara buliran keringat menjadi butiran debu, bergetah menjadi daki, barulah nasib dipandang genap. Makanya aku biasa saja.
Yah, cukuplah menggagas suara lirih di balik dinding. Bila perlu bersembunyi di belakang kawan. Padahal di luar sana setor muka penting, demi perbaikan nasib, kata kawanku yang menjadi guru senior di sini. ”Jenjang apa lagi hendak dikejar, usia telah melampaui garis tangan,” gumamku.
Kawanku, Haruna, dengan gelora mudanya bersuara lantang langsung ditodong jadi pelopor. Tiga tahun suara lantang akhirnya meradang berubah menjadi lirih dan agak berat "gantian, jangan saya terus".
Teman seangkatan Haruna telah lama minggat. Tidak tahan menghitung angka ganjil di kepala. Katanya angka-angka itu kian lama mirip kunang-kunang. Akhirnya semakin kecil serupa Cimex lectular (sejenis kutu busuk). Bikin penat. Makanya ia bertahan untuk menggantikan peran sang kawan. Jadi, mohon dimaklumi bila sekarang suaranya agak serak.
Asam garam di sekolah ini sudah telanjur nyaman terasa. Bagi mereka yang tiada jalan lain cukup bersikap sederhana bisa menjadi seni bertahan hidup. Tiada waktu lagi membanting stir, menggeber hasrat petualang. Kawanku diwarisi buliran keringat untuk bertahan. Buliran keringat itu persis wasiat ayahnya untuk saling membantu di perantauan.
Salah satu pertahanan terbaik dengan cara menjaga silaturahim. Apalagi mereka yang telah beranak pinak, lebih pasrah lagi. Bagiku, hidup seperti itu tak ubahnya sandiwara memelihara senyum. Seolah semua baik-baik saja. Hingga muncullah kesimpulan lain, mereka yang bertahan adalah orang-orang yang mampu bersandiwara.
Bagi mereka yang tiada jalan lain cukup bersikap sederhana bisa menjadi seni bertahan hidup.
Adapun sandiwara itu jelmaan ruang-ruang kantor ditindih oleh tumpukan buku-buku yang belum habis dibaca lalu segera hadir lagi buku baru. Demi literasi, katanya. Begitu seterusnya hingga jarak antartumpukan buku membatasi ruang gerak. Tetapi, aku lebih leluasa melihat orang masuk kantor lewat celah-celah tumpukan buku.
Di celah itulah tersisa ruang untuk berbincang. Pak Daren dan Pak Novrinlah yang membuka ruang agar buku-buku di sini menggenapi bacaan walau separuhnya lewat obrolan. Mereka berdua seorang guru di dua musim. Luring dan daring. Kehadiran mereka membuat kita menikmati kedalaman sekolah yang penuh cerita.
Tak jadi soal, aku jadi sasaran kelakar Pak Novrin, daripada beku di ruangan ber-AC menyaksikan kawan ke sana kemari ditodong undangan pertemuan tiada habisnya. Lebih baik membicarakan hasil bacaan yang terputus, mungkin bisa tuntas lewat obrolan.
Di sini sulit melihat hasil bacaan karena para pembaca buku sekadar jadi pembawa buku. Para pembaca itu mirip kameramen. Pak Novrin menghela napas melihat kameramen sekolah berlari dengan bayangan sendiri di bawah terik puncak hari.
Padahal lewat teras dekat taman sekolah lebih sejuk. Jalur itu lebih mudah. Katanya memutus alur liku-liku agar cepat memajang foto di pentas dumay (baca: dunia maya). Bagaimana bisa dinikmati gambar-gambar itu, belum dibaca sudah ditimpa dengan gambar lain.
Lambat laun, Pak Novrin kasihan melihat kameramen sekolah yang selalu sigap dengan jepretan kamera dalam situasi apa pun. Seperti serdadu yang siaga dengan senjatanya. Suatu ketika mereka menghunuskan kamera pada seorang guru teladan dalam sebuah urusan kepepet. "Loh, saya kebelet mau ke toilet, mau dijepret juga? kata sang guru teladan sedikit kaget. Sontak kameramen itu berseloroh, "Tak bisa ditunda, soalnya bapak sulit ditemui, sementara waktu terbatas.”
Dalam keadaan terpaksa guru itu pun diambil gambarnya dengan wajah meringis. Ketika rilis foto, sang guru menuai gelak tawa dari kawan-kawannya. Guru teladan itu boleh juga menimpali dengan sedikit nyelekit, “Adakah orang masuk toilet dalam keadaan tersenyum. Makanya jangan main todong.”
Pak Novrin dan Pak Daren tertawa hingga bola matanya berair. Tampaknya Pak Novrin mulai membuka ruang guru dengan mengisahkan kameramen sekolah. “Kameramen itu masih belia, sayang, kalau usia mudanya habis di sini, mestinya ia berpetualang.”
Kawan-kawan menggeleng, orang baru semacam kameramen sekolah pun tak luput dari pengamatan Pak Novrin.
Kawan-kawan menggeleng, orang baru semacam kameramen sekolah pun tak luput dari pengamatan Pak Novrin. Tampaknya ia hendak membandingkan aku dengannya. Perasaan girangku pun langsung meresponsnya, “Terima kasih, sudah mengatakan aku awet muda.”
Menurutnya, di kantor jangan terlalu tegang dan kaku. Hidup seperti itu sudah tidak laku. Sekat saja sudah membuat sumpek, apalagi ditambah dengan wajah manyun. Betapa suramnya hidup. Seolah mendung itu menempel di plafon. Kalau tidak dibahas, nanti seperti Pak Musafir, sambil menunjuk ke arahku.
Ia menyebut diriku banyak masalah. Tampilan wajahku yang berkerut. Baju kusut. "Lihatlah batik itu, warnanya sudah butek, seperti kena debu erupsi..."lagi-lagi aku jadi objek candaan. “Itu tandanya keringat kering di baju, ramah lingkungan," Pak Daren pasang badan.
“Daripada baju berwarna terang pertanda baju basah-bergetah oleh keringat, itulah asli butek (bau ketek) seperti bajunya Pak Novrin." Pak Daren menimpali Pak Novrin diikuti gelak tawa teman-teman sekantor. Suasana menjadi riuh sehingga bel masuk belajar tak terdengar.
Aku menunda masuk ke ruangan. Aroma kelas tidak bersahabat. Anak-anak tak siap belajar.
Aku menunda masuk ke ruangan. Aroma kelas tidak bersahabat. Anak-anak tak siap belajar. Bangku berantakan. Lama aku menunggu di kantor untuk menguji perhatian mereka. Anak-anak akan datang meminta aku ke kelas kembali, bila ada perhatian, mungkinkah? Hampir 15 menit tak ada seorang pun yang datang. Aku lupa, tak semua kelas bersikap sama, walau mereka dibalut dengan pakaian seragam.
Tiba-tiba pintu kantor dibuka, seseorang masuk. Ternyata siswa. "Pak Novrin ada?" Ternyata Pak Novrin sama denganku, tidak berada di kelas. Aneh, dia paling cepat berkemas. begitu bel berbunyi, langsung melesat menuju kelas.
Selang beberapa detik, siswa lainnya datang memberi kabar, "Pak Novrin, ada di Labkom (Laboratorium Komputer), menunggu kita". Tanpa menunggu waktu lama mereka segera menghambur menuju labkom. Maklum pelajaran di ruangan yang satu itu menjadi favorit bagi seluruh siswa. Kekecewaan terlihat jelas kala mereka gagal menggunakan labkom.
Sejam kemudian, bel berbunyi tanda pelajaran berganti. Pak Novrin segera meraih jaket dan ranselnya untuk pulang. Beberapa kawan mengingatkan nanti sore ada rapat. Mendengar kata rapat, wajah Pak Novrin tampak menyeringai bercampur ungkapan nyinyir. "Pagi rapat, sore rapat, besok apel pembekalan, hasilnya, sabar ya, masih berproses, yang penting, niat baiknya sampai, toh anda dihitung berpahala,” kata Pak Novrin. Ia pun berlalu tak peduli. Istri dan anaknya sudah menunggu di rumah. Ia tak mau seperti Pak Musafir, menjadi "Bang Toyib" sepanjang hayat. “Mana tahan....”Lagi-lagi pembicaraannya mengarah kepadaku.
Seperti biasa, aku menjadi sasaran canda Pak Novrin tentang bujang sekolah paruh baya. wajar aku menjadi pusat obrolan karena tampangku murah senyum dan mudah bertukar sapa. Tentu mudah larut dalam obrolan Pak Novrin.
Menurut mereka, satu hal yang masih misteri tentangku, pasangan hidup yang menggantung. “Jika aku dalam posisimu, kupertegas kepada “Si Dia,” hendak turut orang tua atau suami. Jika sudah bersuami tidak ada istilah anak mami. Akan kutunjukkan diri ini lelaki sejati,” kata Pak Novrin mencak-mencak.
Gegara itu Pak Novrin menyapaku sebagai lelaki peragu. Peranku sebagai guru hanyalah lakon dalam sebuah sandiwara.
Gegara itu Pak Novrin menyapaku sebagai lelaki peragu. Peranku sebagai guru hanyalah lakon dalam sebuah sandiwara. Memang benar di belakang layar aku termasuk orang belum dewasa mencerahkan teman hidup. Tepatnya aku lebih senang memendam perasaan.
Mungkin bercampur gengsi karena separuh hidup pernah malang melintang di pelosok, Tembagapura, tempat cukong-cukong Paman Sam menguras perut bumi negeri ini. Penuh keringat dan air mata. Apa iya aku mesti diajari lagi tentang kedewasaan padahal misaiku sudah tebal di perantauan.
***
Tidak disangka rapat pembahasan hasil belajar kali ini lebih alot dibandingkan pengolahan nilai rapor yang suntuk di batas waktu. Hingga ada babak tambahan. Mirip pertandingan ketat mempertaruhkan hidup-mati. Seperti biasa Pak Novrin dan Pak Daren kembali bergulat dalam pertemuan. Seolah mereka anak kemarin sore. Padahal setiap akhir tahun segala kemungkinan sering membayang. Memungkinkan yang pasti. Memastikan yang mungkin.
Silang sengkarut tentang ketentuan nilai dan naik tidaknya seorang murid masih menyita waktu. Beberapa guru muda bersitegang. Pak Novrin dan Pak Daren berhasil membakar suasana. Aku hanya sibuk mengunyah kudapan bersama kawan-kawan lainnya. Ketika baru masuk dahulu, aku mirip kawan-kawan yang bersitegang itu. Sangat ideal. Nasib siswa berada di ujung pena guru-gurunya. Belum mengenal sandiwara.
Mereka yang awalnya tersulut dengan pertanyaan "mengapa" akan menjadi tontonan dalam sebuah pertemuan. Peserta rapat akan sekadar meramaikan. “Kami tetap pada pendirian, nilainya tetap seperti itu, ” kata guru-guru muda itu.
“Rapat ini sudah harus diputuskan sekarang karena hasilnya akan dibawa ke acara penutupan akhir tahun,” kata guru-guru kawakan yang berkerumun di sudut ruangan. Guru-guru muda hanya bisa menunduk. Pada akhirnya pasrah Ketika suara terbanyak menentukan hasil rapat. Guru-guru muda itu hanya saling berpandangan.
Mereka yang awalnya tersulut dengan pertanyaan "mengapa" akan menjadi tontonan dalam sebuah pertemuan.
Aku pernah bangga dengan pandangan Kiai Arsad tentang sekolah peradaban. Konon kabarnya sekolah ini berbeda dengan sekolah umumnya. Tata krama siswa menjadi nomor satu. Hingga dibuatlah mars dan yel-yel penggugah jiwa.
Hasil dari rapat, workshop dan seminar menggeser pandangan itu. Urun rembug tentang nilai siswa bermuara pada kesantunan siswa, walau kenyataannya, saling sikut dan baku hantam untuk menentukan nilai sebenarnya.
Bayangkan, di tengah suasana ujian, kita disibukkan dengan musyawarah. “Kebelet banget acara itu," seloroh Pak Daren sambil mengunyah cemilan. Belum lagi bila orang tua siswa meminta restu langsung kepada Pak Kiai perihal nilai anaknya, palu sidang langsung berbunyi “tik-tik,” bukan “tok-tok.”
Di tengah perdebatan sengit tentang nilai, Pak Daren mencoba menoleh. Ya, tinggallah kursi kosong. Ke mana Pak Novrin? Hobinya memancing perdebatan, giliran ribut malah minggat. Sampai kapan rapat ini bisa selesai kalau begini terus. Laporan prestasi santri kebanyakan anjlok belum lagi catatan pelanggaran yang menumpuk. Hasil rapat ini harus disimpulkan sekarang karena esok pesta penutupan tahun ajaran.
***
Banyak pagelaran menghibur para guru dan siswa. Semua akan tersaji di pentas aula serba guna. Seperti biasa, Para Kyai dan sepuh akan memberikan wejangan untuk bekal menjalani liburan. Seperti biasa pula, para kyai harus menyemprit sana, semprit sini untuk menertibkan hilir mudik suara.
Riuh tak tertanggungkan menjadi pemandangan akhir tahun. Jangan heran pesta ini berubah menjadi apel siaga. Orang yang bermental kuasa akan melontarkan emosinya. Hingga semprit berubah menjadi semprot. Sambut akan menjadi sambit. Maka tampillah kyai Arsad melambungkan suara, menjebol riuh suasana.
Penghulu Para kyai itu kembali melontarkan wejangan pamungkas: "Mohon menjadi perhatian, wahai muridku. Aku, tak perduli, seberapa jatuh nilai kalian dalam kelas, yang penting santun dan beradab saya jamin kalian lulus semua. Sayang sekali, hasil belajar tidak bisa diumumkan di sini, baru kali ini terjadi.”
Aku dan Pak Novrin hanya bisa saling menatap. Guru-guru muda yang hadir nampak tertunduk dan menggeleng. Jadi, rapat dan pertemuan yang menyita tidur mereka selama ini isinya raib kemana? Pergulatan dalam rapat sekadar bunga-bunga pentas. Hadir juga bunga lain ternyata menjadi rumput. Mereka baru paham, kawan-kawannya yang pamitan tempo hari bukan isapan jempol semata. Tiba-tiba guru muda beranjak satu persatu menuju toilet.
Guru-guru muda yang hadir nampak tertunduk dan menggeleng.
Selang beberapa menit, aku menengok Kembali deretan kursi mereka. Ya, benar kata Pak Novrin, barisan kursi guru-guru muda telah kosong. “Bakal ada lagi guru yang pamitan di akhir tahun ajaran”, kata Pak Daren.
Belum sempat menuntaskan kudapan, disajikan pula gelaran drama persembahan para siswa. Tak disangka drama anak-anak menggemparkan seisi aula. Riuh sorak sorai dan tepuk tangan peserta pesta tak bisa dibendung. Pasalnya, para lakon drama memerankan adegan yang persis dengan watak tokoh.
Diperagakan lakon guru yang menyemprit dan menyemprot. Guru yang sering marah-marah. Hingga sosok paling sabar pun digambarkan. Dalam hiruk pikuk kegembiraan itu, tiba-tiba terselip kecemasan di hatiku. Peran anak-anak terlalu berlebihan. Banyak skenario yang dialihkan. Khawatir Pak Kyai tersinggung dan menanyakan siapa sutradaranya, Matilah aku.
"Wah, bahaya, kawan kita yang satu ini, bisa kena pemanggilan,” kata Pak Daren menakut-nakuti. "Apanya yang salah, drama itu cermin kehidupan. Pengalaman berkesan wajar dipentaskan,”Pak Novrin menimpali. Di luar sana, ada yang meniru-niru gaya presiden malah mendapat sambutan hangat. Bahkan, jadi artis dadakan.
Pemimpin kita di sini berbeda, Sangat sensitif. Karena itulah, aku segera beranjak. Mereka pun terkejut melihat air mukaku. Dengan mudahnya berpamitan. Padahal acara belum berakhir. Mirip guru-guru muda saja. "Aku mau kembali ke ponsel, bercengkrama dengan orang tuaku,”pungkasku singkat.
Pemimpin kita di sini berbeda, Sangat sensitif. Karena itulah, aku segera beranjak.
Dalam perjalanan menuju wisma, tak henti-hentinya aku berbisik lirih pada Ilahi. "Semoga semua baik-baik saja, cukuplah aku ditampar mondar-mandir hingga dower oleh Sang Nasib. Hingga kurelakan perpisahan dengan “Si Dia,”bersama senyum dan air mata, Wahai Sang Pembolak-balik hati."
Selepas santap siang, tersiar kabar aku dipanggil menghadap pimpinan. Beragam pikiran dan perasaan tawuran di kepala. Seolah berperang dengan diri sendiri sebelum berhadap-hadapan dengan Pak Kyai. “Itu kan, yang kukhawatirkan benar-benar terjadi,”gumamku. Jika sampai terjadi apa-apa denganku gegara anak-anak itu, siang ini juga aku akan mengundurkan diri sebagai pembimbing teater.
Tiba di ruang pimpinan, segenap para pejabat hadir. Mulai dari Para Kyai, Kepala sekolah dan para guru senior. Suara-suara dari rongga dada mulai mencibirku. "Bersiaplah menjalani sidang! Tamatlah kau hari ini Musafir!!!"Aku hanya tertunduk dengan bibir terkatup rapat. Kucoba menelan ludah seperti menelan biji mahoni. "Pokoknya hari ini aku pasrah", gumamku.
Pak Kyai mulai berbicara dengan penuh khidmat. Usai menyampaikan pesan-pesan motivasi, ia mulai menyampaikan maksud undangan beberapa orang penting ke ruangannya. Setelah semua para undangan disapa tibalah giliranku. “Seharusnya dalam pesta akhir tahun ini ada penghargaan terhadap guru.” Salah satu penghargaan yang akan saya berikan kepada Pak Musafir sebagai guru…,”Pak Kyai sengaja menangguhkan kata-katanya untuk memicu rasa penasaran.
“pelipur lara,”kata-katanya Kembali disambung dalam waktu 20 detik.
“Pilihan kata yang disampaikan para lakon drama patut diacungi jempol.”
Segenap para undangan mengaplaus diri ini. Anak-anak itu lebih kreatif. Aku seolah menumpang nama saja. Lagi-lagi aku mengusap dada. Merinci perasaan, semoga tetap berkesan. Perlahan aku menyeka keringat di dahi. Entah bulir apa yang menitik di kerling sudut mata. Air mata atau peluh, entahlah. Pak Kyai ketularan Pak Novrin, berbakat mengaduk-aduk emosi.
Musafir Kelana, lahir di Atari Jaya, Sulawesi Tenggara 1982. Tinggal di Pebayuran, Bekasi. Cerpennya pernah dimuat di Harian Republika. Kumpulan puisinya: Kumpulan Puisi Taman Pena telah terbit.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Azan Shalat Jumat Al-Zaytun: Tangan Terkepal di Atas Diawali Pekik Merdeka
Pelaksanaan shalat Jumat juga dilakukan dengan shaf yang renggang
SELENGKAPNYABulan Pernikahan Rasulullah
Sejumlah wanita dinikahi Nabi Muhammad SAW tepat pada bulan Syawal.
SELENGKAPNYA












