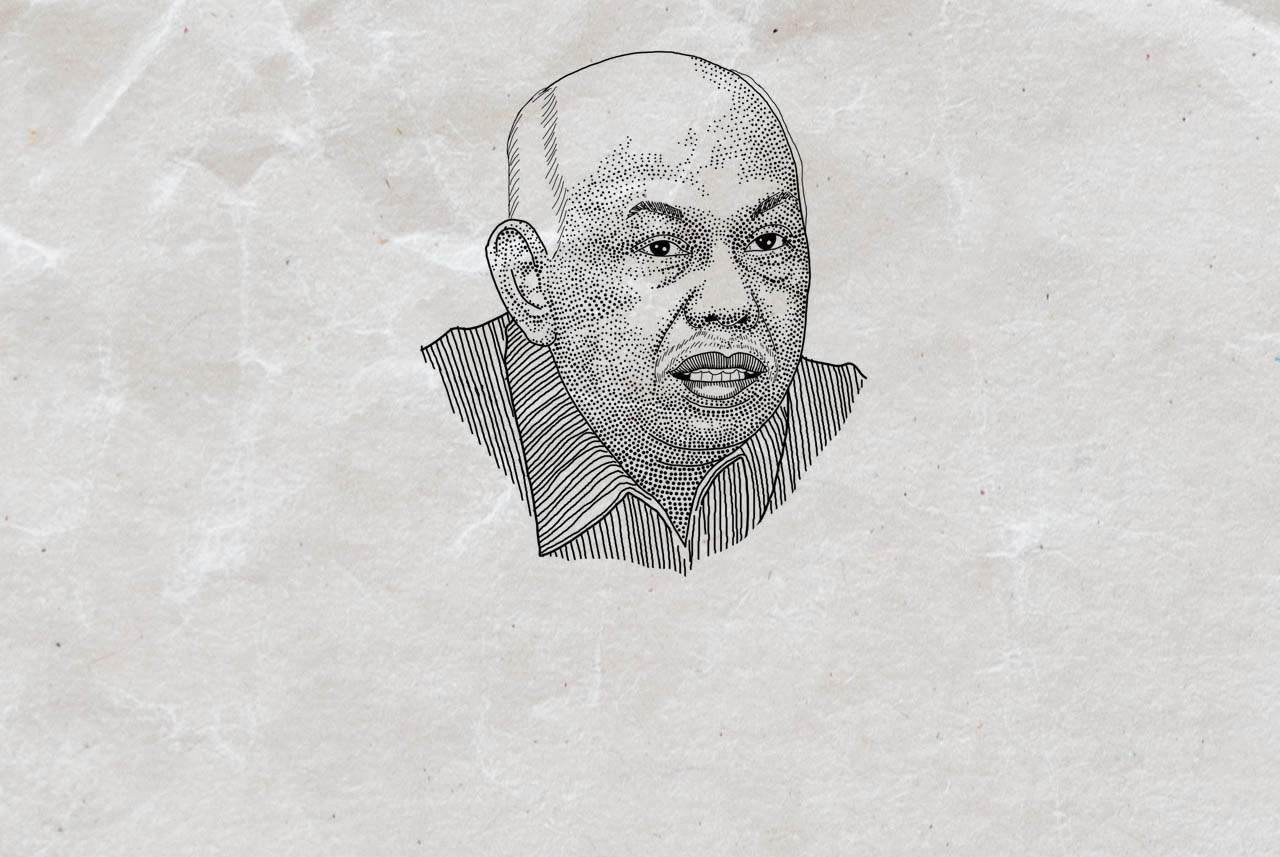
Resonansi
Memberantas Islamofobia (3)
Tantangan untuk memberantas Islamofobia tidak ringan.
Oleh AZYUMARDI AZRA
OLEH AZYUMARDI AZRA
Indonesia. Islamofobia? Mungkin kedengaran bagi banyak Muslim Indonesia sendiri mengada-ada. Alasan sederahana; mayoritas penduduk Indonesia dan juga kebanyakan pejabatnya sejak dari tingkat tertinggi sampai terendah mayoritas mutlak adalah Muslim.
Tetapi tetap saja ada kalangan Muslim yang menganggap pemerintah pusat sebagai menganut dan menerapkan Islamofobia. Benarkah?
Tanggal 15 Maret diproklamasikan Majelis Umum PBB (UNGA) di markas besarnya di New York sebagai ‘Hari Internasional Memberantas IslamoFobia’ (‘The International Day to Combat Islamophobia).
Jelas, tantangan untuk memberantas Islamofobia tidak ringan. Sikap dan tindakan yang mencerminkan Islamofobia masih merajalela di berbagai negara.
Islamofobia bahkan dibenarkan pemerintah di Barat khususnya atas dasar argumen kebebasan berekspresi, seperti pembakaran kitab suci Alquran oleh kelompok supremasi kulit putih Rasmus Paludan di Narkopping dan di beberapa tempat lain di Swedia.
Jelas, tantangan untuk memberantas Islamofobia tidak ringan. Sikap dan tindakan yang mencerminkan Islamofobia masih merajalela di berbagai negara.
Kelompok rasis kulit putih antiimigran, antikulit berwarna, dan anti-Islam atau anti-Muslim terus bertahan di berbagai negara Eropa dan Amerika Serikat. Walhasil, proklamasi PBB tentang pemberantasan Islamofobia secara simbolik sangat penting.
Walau masih banyak pertanyaan; seberapa jauh bisa diterapkan. Pemberantasan Islamofobia perlu diakselerasi khususnya di negara-negara yang secara historis mengidap pandemi ini.
Terkait itu, bahkan di negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia bukan tidak sering ada anggapan dari kalangan umat Islam sendiri. Mereka beranggapan rezim penguasa menerapkan politik Islamofobia?
Bagi sebagian Muslim, Pemerintah Indonesia sepanjang sejarah memperlihatkan Islamofobia.
Meski anggapan Islamofobia itu terkait kebijakan tertentu yang boleh jadi dalam kasus dan batas tertentu benar, juga berhubungan dengan psikologi sosial-politik yang bertahan di kalangan umat Islam Indonesia.
Bagi sebagian Muslim, Pemerintah Indonesia sepanjang sejarah memperlihatkan Islamofobia.
Salah satu psikologi sosial-politik yang berkembang sejak zaman kolonial Belanda tecermin dalam ungkapan yang diperkenalkan sosiolog, Profesor WF Wertheim (1907-1998), ia berargumen, ‘Muslim Indonesia adalah mayoritas dengan mentalitas minoritas’ (Indonesian Muslim are majority with minority mentality’).
Argumen Wertheim ini, pertama-tama terkait realitas politik sejak masa kolonial di mana Islam dan kaum Muslim tersisih dari kekuasaan politik. Keadaan ini bersumber dari sikap kebanyakan kaum Muslim di berbagai daerah yang melakukan jihad terhadap kolonialisme Belanda.
Setelah kalah perang, kebanyakan kaum Muslim melakukan perlawanan diam (silent resistance) dan berkonsentrasi dalam dakwah dan pendidikan Islam: menjauhkan diri dari kekuasaan kolonial.
Psikologi ‘mayoritas dengan mentalitas minoritas’ makin kuat ketika berkombinasi dengan ‘politik belah bambu’ dari penguasa kolonial Belanda yang dianggap juga dilakukan pemerintahan Indonesia sendiri pasca-kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Setelah kalah perang, kebanyakan kaum Muslim melakukan perlawanan diam (silent resistance) dan berkonsentrasi dalam dakwah dan pendidikan Islam: menjauhkan diri dari kekuasaan kolonial.
‘Politik belah bambu’ berdasar saran penasihat Pemerintah Belanda, Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) yang membagi Islam kepada dua: ‘Islam ibadah’ yang tidak perlu terlalu dikekang pemerintah kolonial, dan ‘Islam politik’ yang perlu diwaspadai.
Tetapi Snouck keliru karena ‘Islam ibadah’ seperti naik haji, pendidikan Islam semacam pesantren, madrasah, dan sekolah pada gilirannya menimbulkan implikasi dan reperkusi sosial-politik.
Dikotomi Islam menjadi dua bagian itu terbukti tidak bisa dipertahankan berkelanjutan.
Presiden Sukarno dengan ekletisisme ideologi semacam Nasakom (nasionalisme, agama, komunisme) juga dianggap sebagian Muslim Indonesia sebagai menerapkan politik belah bambu. Meski istilah belum populer ketika itu, politik Bung Karno itu secara retrospektif dianggap sebagian Muslim sebagai satu bentuk ‘Islamofobia’.
Presiden Soeharto juga dianggap melakukan politik yang sama dalam paroan pertama kekuasaannya (1970-1990) ketika ia melakukan fusi parpol yang juga dianggap sebagai ‘depolitisasi Islam’ atau ‘deislamisasi politik’.
Dikotomi Islam menjadi dua bagian itu terbukti tidak bisa dipertahankan berkelanjutan.
Sepanjang masa reformasi, pemerintahan Presiden Jokowi yang kini terutama dianggap kalangan Muslim sebagai menerapkan Islamofobia.
Mereka menyebut indikasinya seperti ‘kriminalisasi ulama’, ‘pesantren sebagai perkecambahan radikalisme’, ‘perlakuan hukum tidak adil terhadap aktivis Muslim’ dan seterusnya.
Anggapan adanya Islamofobia—belum dijawab Presiden Jokowi dan pejabat tinggi lain secara tuntas dan meyakinkan. Jawaban hanya secara sporadis disampaikan.
Sebaliknya terlihat ada peningkatan anggapan di kalangan umat Islam tentang gejala Islamofobia itu—dan bisa terus meningkat menjelang akhir masa pemerintahannya pada 20 Oktober 2024. Keadaan ini tidak kondusif bagi kohesi religio-sosial berbangsa dan keutuhan integrasi bernegara.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.







