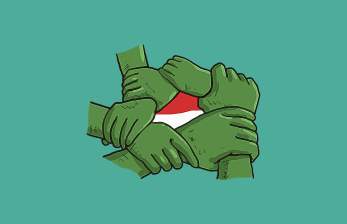Tema Utama
Bagaimana Hadis Palsu Muncul?
Ada pelbagai motif di balik timbulnya hadis-hadis palsu di tengah umat Islam.
OLEH HASANUL RIZQA
Arab merupakan bangsa yang darinya Nabi Muhammad SAW berasal. Masyarakat Arab pun menjadi yang paling pertama dalam menerima ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Alhasil, perkembangan Islam pada tahap awal tidak bisa terlepas dari pengaruh kultur setempat.
Menurut Prof KH Said Aqil Siroj dalam buku Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Reinterpretasi (2000), bangsa Arab terdiri atas berbagai kabilah dan suku. Hampir setiap hari mereka disibukkan dengan masalah sumber daya alam, terutama air dan rumput—makanan ternaknya. Sebab, kondisi geografis jazirah tempat tinggalnya memang gersang dan terik.
Karakteristik bangsa Arab, khususnya pada zaman Jahiliyah, dapat diibaratkan sebagai pasir. Benda ini tidak bisa disatukan. Selain itu, pasir pun berwatak labil. Ke mana angin berembus, ke situlah pasir mengarah.
Begitu pula dengan orang-orang Arab. Di mana mereka mendapatkan tempat berlindung—semisal suku yang bisa menjamin keamanan dan kebahagiaannya—mereka akan mengikutinya dengan semangat yang tinggi.
Fanatisme kesukuan dan sukarnya mewujudkan persatuan; itulah dua tabiat dominan bangsa Arab. Bagaimanapun, Allah SWT Maha Berkehendak. Dia mengutus Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah bangsa tersebut dengan membawa misi Islam.
Agama tauhid ini sangat menekankan persatuan. Ukhuwah itu tidak didasarkan pada kesamaan suku atau pelbagai kepentingan duniawi, sebagaimana yang biasa terjadi pada masa Jahiliyah. Rasa persaudaraan yang islami berdasarkan semata-mata pada iman.
Kiai Said mengatakan, Rasulullah SAW berhasil mengarahkan watak fanatik dan emosional bangsa Arab agar bertujuan lebih luhur. Fanatisme tidak lagi digunakan untuk membela kabilah di hadapan kabilah lain. Energi tersebut kini dimanfaatkan untuk membela tauhid. Girah Islam sebegitu tingginya, sampai-sampai seorang Muslim pada zaman Nabi SAW akan malu untuk membawa-bawa sukunya.
Sebelum berislam, mereka dengan bangga memakai gelar di belakang namanya yang mengindikasikan kesukuan.
Sebelum berislam, mereka dengan bangga memakai gelar di belakang namanya yang mengindikasikan kesukuan, semisal at-Taymi, al-‘Adiy, az-Zahri, dan sebagainya. Sesudah menjadi Muslim, sebutan-sebutan dari Rasulullah SAW-lah yang membanggakannya, semisal ash-Shiddiq, al-Faruq, Saifullah al-Maslul, dan lain-lain.
Sayangnya, kondisi demikian tidaklah permanen. Begitu Nabi SAW wafat, girah kesukuan mulai kembali tampak di antara orang-orang Arab. Bahkan, tutur Kiai Said, jasad mulia beliau belum dikebumikan, tetapi sejumlah tokoh mengadakan rapat di Bani Saqifah untuk membahas siapa yang selanjutnya akan memimpin Muslimin. Dari sana, muncul suara, “Minna amir, wa minkum amir,” ‘dari pihak kami ada seorang pemimpin, begitupun dari pihak kalian.’ Perkataan itu menjadi sinyal keretakan persatuan umat.
Pada zaman kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, perpecahan (politik) terasa, tetapi tidak sampai menimbulkan konflik terbuka di antara sesama Muslimin. Barulah sesudah syahidnya Khalifah Utsman bin Affan, beberapa perang saudara terjadi.
Kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan saling berhadapan di Perang Siffin pada 657 M. Setelah terjadi rupa-rupa konfrontasi, Hasan dan Husain—keduanya anak-anak Ali—menerima pemerintahan Muawiyah pada 41 H/661 M. Tahun tersebut dinamakan 'Am al-Jama'ah (Tahun Persatuan) karena kaum Muslimin kembali bersatu di bawah pimpinan seorang khalifah.
View this post on Instagram
‘Hadis’ dan politik
Nuansa damai dari 'Am al-Jama’ah tidak berlangsung lama. Banyak elite Dinasti Umayyah yang masih saja memandang sinis (bekas) lawan politik mereka. Padahal, kubu Ali nyata-nyata telah mengalami kekalahan-politik yang telak. Bahkan, beberapa raja Umayyah menerapkan kampanye penuh stigma terhadap sepupu Nabi SAW itu, beserta anak keturunannya.
Sebagai contoh, khatib di masjid-masjid negara Umayyah diharuskan menutup khutbah Jumat dengan doa-doa keburukan untuk sang Karamallaahu Wajhah. Instruksi ngawur itu baru dicabut pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah kedelapan Umayyah.
Para ekstremis yang berdiri di pihak pro-Ali pun tak kurang parahnya. Mereka sering kali menjelek-jelekkan pemerintahan Umayyah. Bahkan, pada akhirnya Ali sendiri wafat akibat dibunuh Khawarij. Kaum tersebut mulanya mendukung Ali, tetapi kemudian menuduhnya sebagai kafir selepas peristiwa arbitrase (tahkim).
Periode antara Perang Siffin dan era Umar bin Abdul Aziz dipenuhi pergolakan politik yang begitu panas. Masing-masing kelompok, hanya untuk membela patron politiknya, tidak ragu membawa-bawa nama Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, banyak muncul hadis-hadis palsu (maudlu’). Dengan 'hadis' tersebut, pendapat (politik) mereka seolah-olah dibenarkan oleh nubuat Rasulullah SAW.
Dengan 'hadis' tersebut, pendapat (politik) mereka seolah-olah dibenarkan oleh nubuat Rasulullah SAW.
Misalnya, perkataan kaum fanatikus Ali sebagai berikut, “’Aliyyun khairu al-basyari, man syakka fiihi kafar,” ‘Ali merupakan sebaik-baik manusia. Barangsiapa meragukannya, maka ia telah kafir.’
Teks itu adalah hadis palsu karena disandarkan pada Nabi SAW, padahal tidak berasal dari beliau. Tidak pernah dari lisan Rasulullah SAW keluar kata-kata demikian. Namun, para pendukung Ali yang sudah fanatik buta menggembar-gemborkan perkataan itu sebagai sebuah sabda Nabi SAW.
Alhasil, mereka mendapatkan pembenaran untuk memusuhi Muawiyah. Dengan berdiri di sisi Ali, mereka merasa perbuatannya telah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Padahal, Ali sendiri tidak pernah membenarkan kelakuan mereka yang mengutip perkataan lalu menyandarkannya pada nama mulia al-Musthafa.
Di luar kubu-kubuan Ali dan Muawiyah, pemalsuan hadis juga terjadi pada zaman Abbasiyah. Umpamanya, cerita tentang Ghiyats bin Ibrahim an-Nakha’i al-Kufi tatkala menemui Khalifah al-Mahdi. Waktu itu, sang amirul mukminin sedang bermain-main dengan burung merpati kesayangannya.
Berkatalah Ghiyats kepadanya bahwa Rasul SAW pernah bersabda, “Tidak ada perlombaan kecuali bermain pedang, pacuan, atau menggali atau sayap.” Kata “atau sayap” (aw janaah) itu sesungguhnya tidak berasal dari Nabi SAW. Ghiyats hanya menambahkannya demi menyenangkan hati al-Mahdi.
Mengetahui itu, sang khalifah segera memerintahkan bawahannya untuk menyembelih burung merpatinya. “Aku yang menanggung beban atas hal seperti itu,” katanya.
Tentunya, musuh-musuh Islam juga tidak ketinggalan dalam memanfaatkan eksistensi hadis palsu. Tujuannya untuk menghancurkan ajaran agama tauhid. Salah satu contoh perkataan yang diklaim sebagai hadis oleh kaum zindik ialah berikut: “Anaa khaatamu an-nabiyyiin, laa nabiyya ba’dii illa an yasyaa Allah,” ‘aku (Muhammad SAW) adalah Nabi terakhir; tidak ada lagi nabi sesudahku kecuali yang Allah kehendaki.’
Kata-kata “kecuali yang Allah kehendaki” (illa an yasyaa Allah) sengaja ditambahkan seorang murtad, Muhammad bin Sa’id as-Syami. Dengan begitu, dirinya berharap, timbul keraguan di tengah Muslimin tentang status Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi dan rasul. As-Syami sendiri akhirnya dihukum mati akibat perbuatannya itu.
Para pemalsu hadis tak hanya berasal dari kalangan politikus dan musuh agama. Beberapa sufi pun menggunakan hadis palsu demi alasan-alasan tertentu.
Menurut Prof KH Ali Mustafa Yaqub, para pemalsu hadis tak hanya berasal dari kalangan politikus dan musuh agama. Beberapa sufi pun menggunakan hadis palsu demi alasan-alasan tertentu. Misalnya, mereka melihat bobroknya akhlak umat yang mulai enggan beramal saleh. Karena itu, hadis palsu dibuat olehnya agar Muslimin lebih terstimulus dalam menyegerakan berbuat kebajikan. Sebuah contoh hadis palsu yang demikian ialah “Uthlub al-‘ilma walaw bi ash-Shin,” ‘Tuntutlah ilmu walau (harus berangkat) ke Negeri Cina.’
Kiai Ali Mustafa dalam buku Hadis-hadis Bermasalah (2003) menerangkan, hadis di atas sangat parah kelemahannya. Karena itu, statusnya adalah hadis palsu. “Uthlub al-‘ilma walaw bi ash-Shin” pun tidak bisa digunakan sebagai dalil apa pun, termasuk untuk mengerjakan amal-amal kebajikan (fadhailul a’mal). Sebab, statusnya adalah maudlu’, bukan semata-mata dhaif (lemah).
Pada akhirnya, Rasulullah SAW sendiri melarang siapapun untuk berkata bohong, apalagi sampai mencatut namanya. Sabda Nabi SAW, “Barangsiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka kelak posisinya di neraka” (HR Ibnu Majah).
Beliau juga berpesan, “Siapa yang menyampaikan informasi tentangku, padahal ia mengetahui informasi itu bohong, maka ia termasuk pembohong” (HR Muslim). Maka dari itu, para ulama menegaskan, tidak boleh meriwayatkan, menyampaikan, dan menyebarkan sebuah hadis maudlu’.
Namun, dibolehkan menunjukkannya, asalkan dengan tujuan pengajaran. Yakni, mengajarkan kepada khalayak bahwa hadis yang ditunjukkannya itu bukanlah sahih, melainkan palsu.

Mengenal Musthalah Hadits
Sejak wafatnya Utsman bin Affan, kerusakan (fitnah) mulai terjadi di mana-mana wilayah Islam. Para pelaku bidah pun kian mudah dijumpai. Seakan tanpa rasa bersalah, mereka mengeklaim sebuah atau beberapa ungkapan sebagai sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis palsu yang disebarkannya tidak lain bertujuan mendukung ideologi atau patron politik masing-masing.
Keadaan demikian tentu merisaukan ulama-ulama yang lurus. Seperti dikisahkan Ibnu Sirin, yang dikutip Imam Muslim dalam Shahih-nya, sebagai berikut. “Para sahabat Nabi SAW (awalnya) tidak pernah menanyakan tentang isnad (silsilah hadis). Namun, ketika fitnah mulai tersebar, mereka pun berkata (kepada setiap pembawa teks hadis), ‘Coba sebutkan kepada kami sanad keilmuan kalian!’ Mereka kemudian memilah informasi (sehingga bisa dibedakan antara) ahli sunah dan ahli bidah (yang suka berbohong). Hadis yang disampaikan para ahli sunah, mereka terima. Hadits yang bersumber dari ahli bidah, mereka tolak.”
Dari sana, berkembanglah ilmu untuk mengetahui kredibilitas pembawa berita (khabar) hadis. Namanya, ilmu al-Jarah wa at-Ta’dil. Muncul kemudian kaidah-kaidah mengenali asal-usul pembawa khabar, yakni ilmu rijal. Lantas, ilmu sanad pun lahir untuk membuktikan, apakah silsilah sebuah khabar bersambung hingga kepada Nabi SAW atau terputus.
Muslimin menyambut disiplin ilmu yang mengkaji tentang kaidah-kaidah terkait sanad dan matan (redaksi) hadis. Itulah ilmu musthalah hadits.
Pada fase belakangan, yakni keempat Hijriyah, Muslimin menyambut disiplin ilmu yang mengkaji tentang kaidah-kaidah terkait sanad dan matan (redaksi) hadis. Itulah ilmu musthalah hadits.
Di antara manfaat ilmu tersebut adalah, seorang alim dapat membedakan dan menentukan, mana hadis-hadis yang berderajat sahih, hasan, dan dhaif. Pencetus musthalah hadits adalah al-Qadhi Abu Muhammad al-Hasan bin Abdurrahman bin Khallad ar-Ramahurmuzi (360 H). Karyanya yang menjadi tonggak dalam hal ini ialah Al-Muhaddits al-Fashil bayna ar-Rawi wa al-Wa’i.
Melihat pada objek kajiannya, musthalah hadits adalah sebuah disiplin yang penting dan turut mendukung tegaknya syariat. Sebab, hadis di samping Alquran adalah juga sumber hukum menurut Islam. Dalam pada itu, para ahli musthalah hadits pun membuat klasifikasi tentang hadis-hadis.
Dilihat dari konsekuensi hukumnya, hadis terbagi dua, yakni maqbul (diterima) dan mardud (ditolak). Hadis maqbul terdiri atas hadis sahih dan hadis hasan. Adapun hadis mardud merupakan hadis yang lemah (dhaif).

Alhasil, level tertinggi ada pada hadis sahih. Ia dapat menjadi dalil (hujjah) keislaman serta bisa pula diamalkan. Sebuah hadis dipandang sahih apabila memenuhi lima syarat berikut ini.
Pertama, sanadnya bersambung (telah mendengar/bertemu antara para perawi). Kedua, hadis itu melalui penukilan dari perawi-perawi yang adil. Adapun kriteria-kriteria “perawi yang adil” ialah Muslim, baligh, berakal sehat, serta terhindar dari sebab-sebab kefasikan dan rusaknya kehormatan. Ketiga, hafalannya kuat (tsiqah).
Keempat, tidak ada syadz, yakni keadaan ketika seorang perawi yang tsiqah menyelisihi perawi yang lebih tsiqah darinya. Kelima, tidak ada kecacatan (illat) dalam hadis yang bersangkutan.
Sementara itu, sebuah hadis bisa dikatakan berstatus hasan apabila perawi-perawinya hanya sampai pada tingkatan di bawah tsiqah, yakni shaduq. Artinya, tingkat kesalahannya adalah 50:50. Dalam pengertian lain, tingkat tsiqah-nya di bawah 60 persen. Shaduq bisa terjadi pada seorang perawi atau keseluruhan perawi dalam rantai sanad.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.