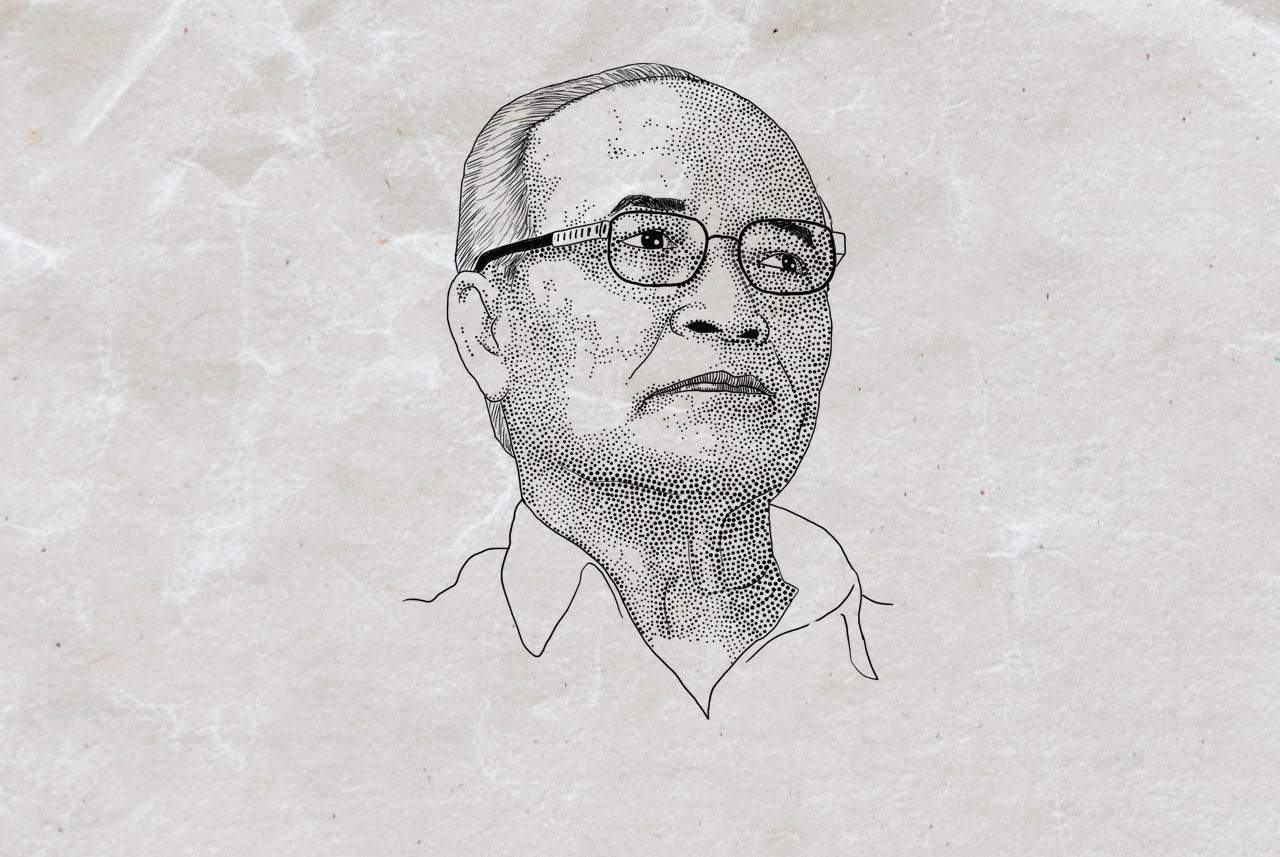
Resonansi
Modal Utama Berbangsa-Bernegara dan Sisi-Sisi yang Rapuh (I)
Penghargaan kita kepada para pemikir kebudayaan ini belum cukup tinggi. Karyanya dibaca lalu dilupakan.
Oleh AHMAD SYAFII MAARIF
OLEH AHMAD SYAFII MAARIF
Artikel ini akan berbicara empat modal utama bangsa dan negara yang kita miliki dan sisi mana yang masih rapuh yang perlu segera dibenahi. Dengan modal ini, kita tetap punya harapan meneropong hari esok yang lebih baik dan adil.
Sekalipun, tantangan sosio-politik-kultural sungguh berat dan tidak mudah diurai. Teman saya, sastrawan senior yang belum lama ini wafat, sudah sangat skeptis memandang masa depan Indonesia, yang belum juga membaik dari sisi moral dan rasa tanggung jawab.
Dewi keadilan yang didambakan sejak masa penjajahan belum menghampiri kita. Perpecahan politik yang menguras energi, terus menghantam.
Penghargaan kita kepada para pemikir kebudayaan ini belum cukup tinggi. Karyanya dibaca lalu dilupakan, tak lagi dijadikan bahan pertimbangan dalam strategi pembangunan.
Saat pembicaraan sampai masalah sisi yang masih rapuh, pandangan sastrawan di atas dihadirkan kembali, di samping mempertimbangkan pendapat ilmuwan dan budayawan besar lain, seperti Mochtar Lubis dan Koentjaraningrat.
Penghargaan kita kepada para pemikir kebudayaan ini belum cukup tinggi. Karyanya dibaca lalu dilupakan, tak lagi dijadikan bahan pertimbangan dalam strategi pembangunan.
Mochtar Lubis, misalnya, bahkan harus meringkuk dalam penjara setelah Indonesia merdeka, bertahun-tahun. Kritiknya terhadap rezim otoriter dinilai terlalu tajam, tetapi orang sengaja melupakan niat dan tujuan baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara.
Agar pemikiran dan perjuangan Mochtar Lubis tidak hilang dimakan musim, catatan Ramadhan KH di bawah ini perlu dikutip: “Orang seperti ini yang menjadi pusat perhatian dan menyebabkan rekan-rekannya menaruh simpati kepadanya. Tentu ada saja pihak yang tidak menyukainya.
Lawan-lawannya yang pasti adalah koruptor-koruptor, penyuap-penyuap, penyeleweng-penyeleweng, pelanggar-pelanggar moral dan hukum, pemeras, perusak alam sekeliling. Kalau tidak gemetaran, sedikitnya mereka tentu akan benci melihatnya.
Modal utama itu, pertama, bahasa Indonesia. Sekalipun proses pembentukan bangsa sejak 1920-an belum tuntas, gerak dinamis dan kreatif meraih tujuan itu tak pernah berhenti.
Sebab memang mereka yang digugatnya. Dia pergunakan benar fungsi pers (pena) yang dia anut dan menggugah peminat sastra untuk tidak cuma bermain dengan kata-kata.” (Lih. Mochtar Lubis, Budaya, Masyarakat, dan Manusia Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993, hlm. xx-xxi).
Modal utama itu, pertama, bahasa Indonesia. Sekalipun proses pembentukan bangsa sejak 1920-an belum tuntas, gerak dinamis dan kreatif meraih tujuan itu tak pernah berhenti.
Peran bahasa Indonesia sebagai lingua franca (bahasa nasional/bahasa pergaulan) menjadi sangat strategis. Kita tidak bisa membayangkan Indonesia sebagai bangsa baru dengan ribuan pulau ini jika tidak punya alat perekat ampuh, yaitu bahasa Indonesia.
Ajaibnya, bahasa nasional ini bukan dari bahasa suku mayoritas, melainkan berhulu dari bahasa suku minoritas, yaitu suku Melayu di Kepulauan Riau. Bahasa Indonesia adalah sumbangan terbesar suku Melayu Riau terhadap bangsa Indonesia.
Beberapa tahun sebelum munculnya novel Siti Noerbaya dan Salah Asoehan pada era 1920-an, bangsawan Jawa, Ki Hadjar Dewantara sejak 1916 membela kedudukan bahasa Melayu sebagai lingua franca untuk nusantara ini.
Bahasa Melayu dinilai lebih sesuai untuk sistem politik demokrasi, yang menjadi cita-cita para pemimpin pergerakan nasional.
Jadi, Ki Hadjar adalah tokoh kebudayaan visioner dan patriotik saat bangsa ini masih menyandang nama kolonial: Hindia Timur Belanda. Ki Hadjar tidak mengusulkan bahasa Jawa yang bertingkat-tingkat dan bersekat-sekat itu sebagai bahasa persatuan.
Bahasa Melayu dinilai lebih sesuai untuk sistem politik demokrasi, yang menjadi cita-cita para pemimpin pergerakan nasional.
Pada 1938, Ki Hadjar tetap pada pendiriannya, dengan tegas mengatakan, “… demi persatuan bangsa Indonesia hanya bahasa Indonesialah yang berhak menjadi bahasa persatuan.” (Lih Majelis Luhur Taman Siswa karya Ki Hadjar Dewantara. Yogyakarta, 1962, hlm 514).
Jika dari Abdoel Moeis meluncur ungkapan ini, orang tak perlu heran karena dia berasal dari suku Minangkabau. Namun, dari Ki Hadjar, maknanya sangat mendalam dan pengaruh politiknya menjadi demikian luas.
Gagasan Ki Hadjar ini, menemukan momen dalam Sumpah Pemuda 1928, yang langsung mengukuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam ungkapan, “Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe mendjoendjoeng bahasa parsatoean, bahasa Indonesia.”
Kedudukan bahasa Indonesia secara konstitusional sangat kuat, tercantum dalam Pasal 36 UUD 1945: “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.”
Di ranah pemakaian bahasa Indonesia, lisan atau tertulis, masih perlu pembinaan. Jangankan di kalangan rakyat banyak, bahkan belum semua pejabat negara yang mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Karena itu, semboyan “bahasa adalah jiwa bangsa” perlu selalu diingat dan dipertajam agar penutur bahasa itu selalu berada dalam ketegangan kreatif menuju tingkat kebudayaan yang tinggi, adil, dan beradab dengan jalan pemakaian bahasa secara baik dan teratur.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.








