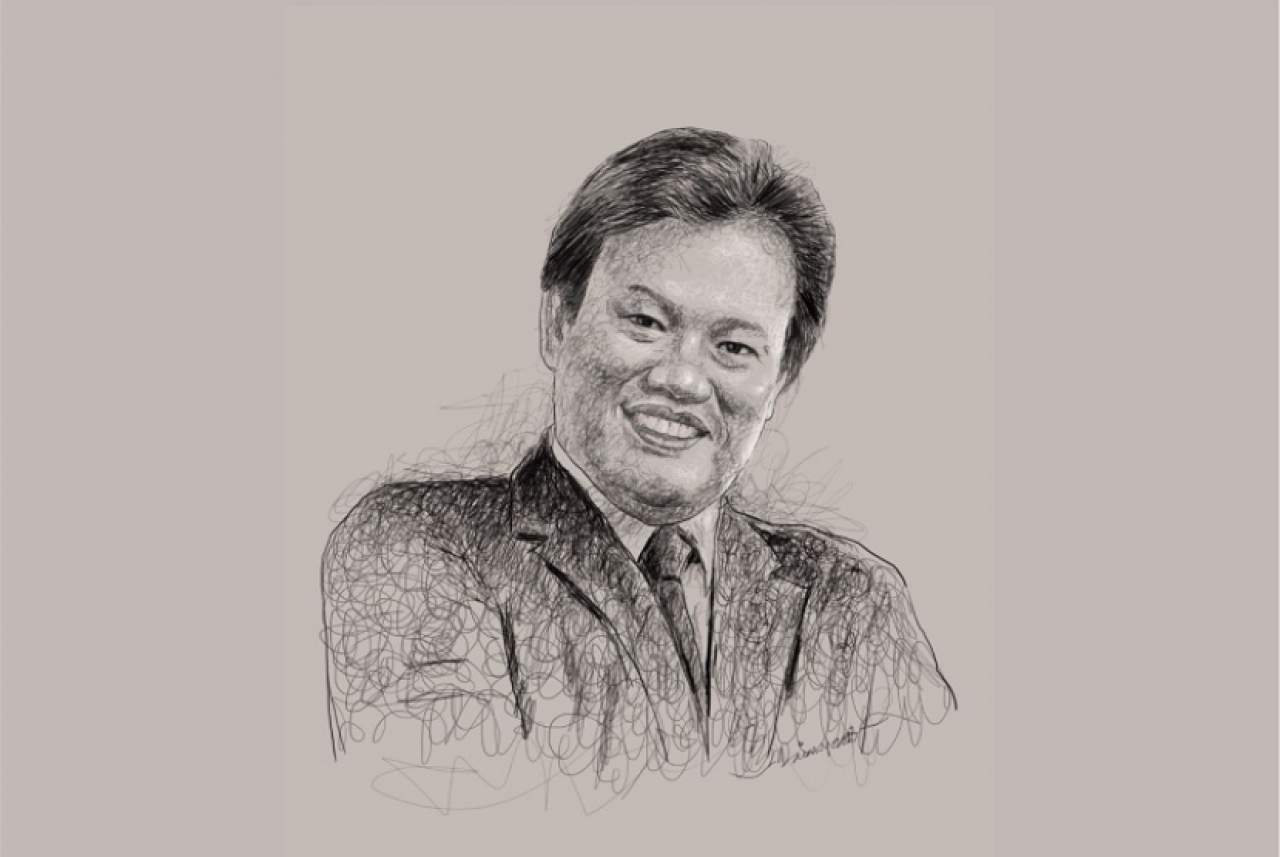
Analisis
BUMN Energi di Era Transisi Energi
Transisi energi memang akan mengubah peta bisnis di sektor energi.
Oleh SUNARSIP
Transisi energi menuju net zero emission (NZE) tentunya akan turut mengubah peta bisnis korporasi yang bergerak di sektor energi. Berkurangnya pangsa penggunaan energi fosil, terutama minyak bumi dan batu bara di masa mendatang, tentunya akan mempengaruhi rencana bisnis yang dikembangkan korporasi di sektor tersebut. Korporasi yang bergerak di bisnis minyak...
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Tragedi Masjidil Haram 1979
Sekelompok bersenjata menguasai Makkah kala jamaah haji belum seluruhnya pulang pada 1979.
SELENGKAPNYAPeci Lambang Pergerakan
Ali dan tokoh pergerakan lainnya justru mengikuti kebiasaan Soekarno.
SELENGKAPNYAJuru Ikhlas
Amal sedikit dan rutin, mungkin jalan yang bisa dipilih sebagai ikhtiar menjadi ikhlas.
SELENGKAPNYA









