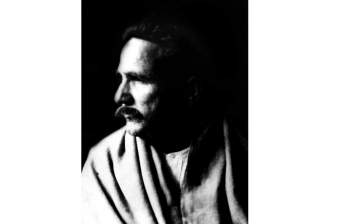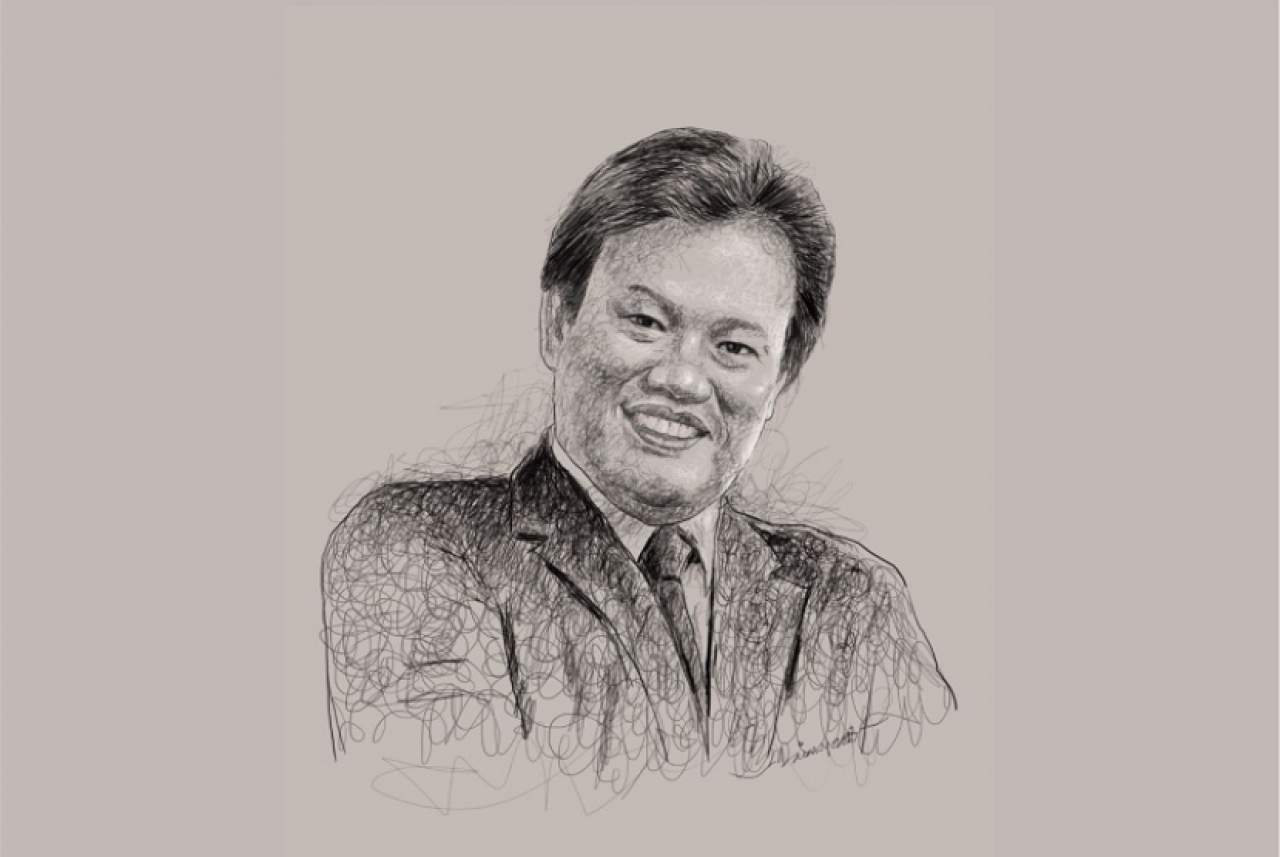
Analisis
Deindustrialisasi dan Hilirisasi
Dua tahun terakhir, hilirisasi mendapatkan perhatian besar dari pemerintah.
Oleh SUNARSIP
Penulis percaya bahwa kemajuan industrialisasi suatu negara berkorelasi dengan tingkat kemakmuran negara tersebut. Karena faktanya, negara yang memiliki tingkat industrialisasi yang tinggi diiringi pula dengan kenaikan kemakmuran, yang tercermin dari pendapatan per kapita (income per capita). Sebagai contoh, saat ini Cina merupakan the world manufactur superpower terbesar. Ini mengingat, manufaktur...
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Masa Kekhalifahan Utsman
Dinamika terjadi pada era ketika umat dipimpin Sang Dzun Nurain.
SELENGKAPNYAGuna Ulang dan Diet Plastik untuk Upaya Kelestarian
Gaya hidup guna ulang adalah gaya hidup yang menjalankan prinsip pakai-habiskan-kembalikan.
SELENGKAPNYAIndonesia Kejar Target Pembangunan Smelter
Presiden berulang kali menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam.
SELENGKAPNYA