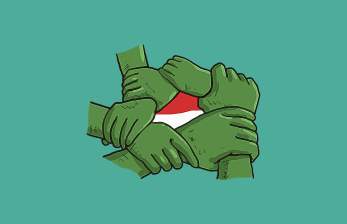Opini
Kompleksitas Radikalisme Agama
Kita bisa belajar dari mantan pelaku yang pernah berada dalam dunia radikalisme dan terorisme.
Oleh NOOR HUDA ISMAIL
NOOR HUDA ISMAIL; Visiting Fellow RSIS, NTU
Tulisan Amirsyah Tambunan, sekjen MUI, yang berjudul “Radikalisme Bukan Agama” (21/12), penting untuk dicermati dengan jernih. Selain karena posisi penulis yang strategis, yaitu sebagai sekjen MUI dan tokoh Muhammadiyah, tetapi juga tawaran pendekatan baru dalam membedah isu radikalisme.
Dalam tulisan ini, Amirsyah menawarkan tiga framing, yaitu ‘konspirasi’, ekonomi, dan pendidikan. Framing ini menyegarkan, mengingat selama ini diskusi radikalisme masih berkutat isu ‘state security’ (keamanan negara) dan belum ‘human security’ (keamanan jiwa) manusia. Lalu bagaimana posisi ketiga framing Amirsyah dalam diskusi radikalisme, baik dalam ranah global maupun lokal?
Framing konspirasi
Framing ini muncul ketika Amirsyah berusaha menggugat adanya upaya sistematis dari sejumlah pihak yang “mengaitkan radikalisme dengan kelompok tertentu, khususnya Islam”. Padahal, menurut Amirsyah, “radikalisme itu ada sejak zaman dulu karena sudah ada dalam diri manusia”.
Pada era media sosial, framing terorisme sebagai konspirasi atau mainan pihak-pihak tertentu posisinya lemah atau tidak dapat menjelaskan munculnya teroris-teroris hasil rekrutan media sosial, yang punya niat ikhlas untuk membela umat Islam.
Menurut hemat penulis, framing ‘konspirasi’ Amirsyah ini mudah dicari pembenarannya. Misalnya dalam konteks global, Amerikalah paling jago dalam hal isu ini. Negara adikuasa ini mahir memainkan doktrin war by proxy atau “meminjam tangan orang lain untuk menyerang musuh Amerika”.
Framing konspirasi ini membantu kita menjelaskan fenomena radikalisme secara “struktur” atau “gambaran besar” sebuah peristiwa, baik di tingkat global (mobilisasi di Afghanistan) maupun lokal (Komando Jihad). Namun, salah satu kelemahan framing ini adalah mengerdilkan aspek “agency” (kemampuan diri untuk melakukan sebuah tindakan) dari para pelaku.
Artinya, benar ada “kekuatan besar” yang memfasilitasi untuk memunculkan sebuah aksi radikalisme. Tapi, kita pun tidak bisa menutup mata bahwa ada segelintir orang (agency) yang membajak agama untuk pembenaran aksi kekerasan mereka.
Pada era media sosial, framing terorisme sebagai konspirasi atau mainan pihak-pihak tertentu posisinya lemah atau tidak dapat menjelaskan munculnya teroris-teroris hasil rekrutan media sosial, yang punya niat ikhlas untuk membela umat Islam. Seperti kasus Ika Puspitasari, buruh migran Indonesia di Hong Kong yang menjadi pendana dan siap menjadi pelaku bom bunuh diri. Pada waktu bersamaan, sosok seperti Ika ini tidak bersentuhan dengan para konspirator (Pemerintah AS atau aparat Indonesia) sama sekali.
Framing ekonomi dan pendidikan
Framing ekonomi ini terbaca pada saat Amirsyah mengatakan, “Sebagian besar masyarakat tingkat ekonomi lemah umumnya berpikiran sempit, sehingga mudah percaya pada tokoh-tokoh radikal karena dianggap dapat membawa perubahan drastis untuk hidup mereka”. Sedangkan framing pendidikan muncul dalam paparan terakhir tulisan, yaitu “Pendidikan yang salah menyebabkan munculnya radikalisme agama di berbagai tempat”.
Bahkan, jika ditarik secara global dan dalam rentang sejarah yang lebih panjang, kita akan mendapatkan gambaran yang lemahnya hubungan antara faktor ekonomi, pendidikan, dan terorisme ini.
Kedua framing ini sengaja penulis jadikan dalam satu bahasan karena saling terkait satu dengan yang lain.
Memang ada benarnya kedua framing yang disodorkan oleh Amirsyah ini. Hampir dua ribuan warga Indonesia yang tertangkap karena keterliban dalam tindak pidana terorisme itu, mayoritas berasal dari kalangan menengah ke bawah dan tidak berpendidikan tinggi setingkat universitas.
Namun, framing ekonomi dan pendidikan tidak dapat menjawab pertanyaan, mengapa 27,54 juta penduduk miskin Indonesia dan 177,7 juta penduduk Indonesia yang berpendidikan rendah (data Badan Pusat Statistik 2020) tidak serta-merta menjadi teroris? Kalau framing ini benar, tentunya jutaan penduduk tersebut sudah menjadi teroris semua.
Bahkan, jika ditarik secara global dan dalam rentang sejarah yang lebih panjang, kita akan mendapatkan gambaran yang lemahnya hubungan antara faktor ekonomi, pendidikan, dan terorisme ini. Usamah bin Ladin, pendiri Alqaidah itu orang kaya dan berpendidikan. Salah satu tokoh gerakan anarkistis kiri dari Rusia, Peter Kropotkin (1842-1921) juga lahir dari keluarga aristokrat terdidik.
Hubungan antara faktor ekonomi, tingkat pendidikan, dan terorisme itu langsung, kompleks, dan barangkali lemah. Membaca terorisme sebagai bentuk respons dari kondisi politik, rasa kecewa, dan frustrasi yang berlarut-larut lebih tepat. Meminjam istilahnya Kepala Densus 88, Irjen Pol Martinus Hukom, “Mereka ini (yang terlibat dalam terorisme di Indonesia) adalah orang-orang baik yang tidak mendapatkan tempat dalam pembangunan ini” (2022).
Melihat kompleksnya isu radikalisme dan terorisme ini kita perlu prioritas. Menurut hemat penulis, kita bisa belajar dari para mantan pelaku yang pernah berada dalam dunia radikalisme dan terorisme, baik di tingkat nasional maupun global.
Prioritas penyelesaian
Melihat kompleksnya isu radikalisme dan terorisme ini kita perlu prioritas. Menurut hemat penulis, kita bisa belajar dari para mantan pelaku yang pernah berada dalam dunia radikalisme dan terorisme, baik di tingkat nasional maupun global. Mereka inilah para “credible voice”, yaitu orang-orang yang mempunyai pengalaman dan cara pikir yang bisa dipercaya.
Salah satu sosok itu adalah Abu Fida. Dia lahir dari keluarga Muhammadiyah, alumnus Gontor, dan mantan anggota JI senior. Abu Fida pernah terlibat dalam pelatihan militer Afghanistan tahun 1980-an dan mendapatkan uang saku dari Usamah bin Ladin untuk melanjutkan belajar Akidah dan Filsafat di Ummul Qurra, Makkah.
Dan dia telah melepaskan baiat kepada organisasi lamanya. Ia menawarkan solusi perlunya “moderasi berbasis literatur”. Yaitu, memberi tafsir baru terhadap pemikiran tokoh-tokoh panutan kelompok jaringan radikal seperti Ibn Taymiyah. Dalam disertasinya, Abu Fida berargumen bahwa “kelompok ini hanya fokus pada aspek radikal dari pemikiran Ibn Taymiyah dan melupakan bahwa ada banyak sisi moderat dari tokoh ini” (2020).
Abu Fida ingin menuliskan tafsir baru atas dua buku yang diterbitkan oleh kelompok lamanya, yaitu: PUPJI, Pedoman Umum Pergerakan Jamaah Islamiyah dan MTI, Materi Taklimat Islamiyah. Dalam konteks inilah, Amirsyah Tambunan selalu sekjen MUI dan tokoh penting dalam Muhammadiyah dapat membantu keinginan dari Abu Fida ini.
Jika hal ini terjadi, “moderasi beragama dan bukan deradikalisasi" (2019) yang ditawarkan oleh Prof Dr Haedar Nasir, ketua Muhammadiyah dalam pidato guru besarnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dapat terwujud dengan baik. Wallahu’alamu bi shawab.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.