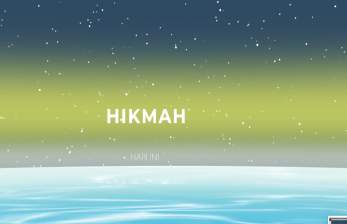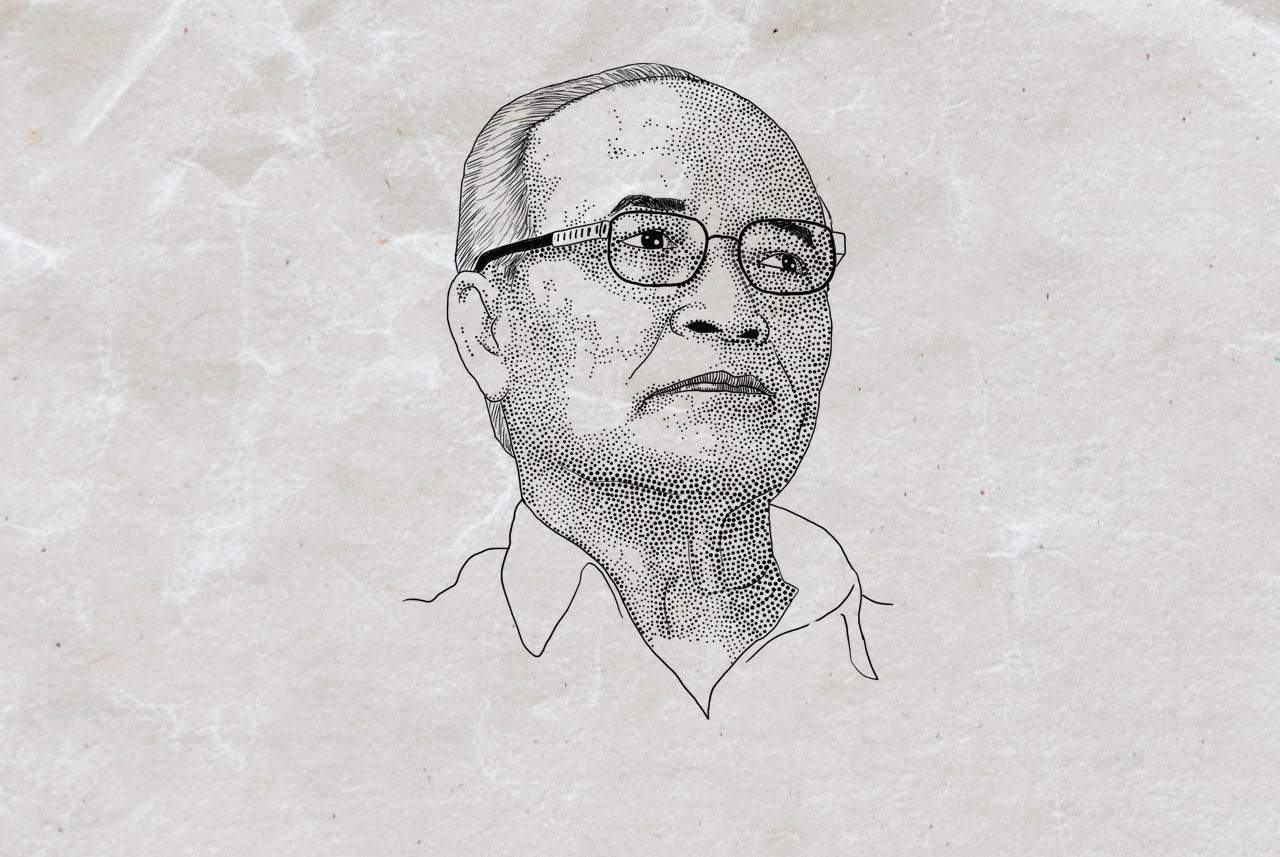
Resonansi
Perpecahan Parpol di Indonesia (III)
Ketika warna ideologi politik semakin kabur, perpecahan parpol semakin mudah terjadi.
Oleh AHMAD SYAFII MAARIF
OLEH AHMAD SYAFII MAARIF
Pendukung aliran Marxisme sami mawon. Tidak perlulah kita berbicara tentang gesekan antara Tan Malaka dan Alimin-Darsono dari kubu Marxisme sebelumnya. Kita ambil saja kejadian tahun 1948 antara PSI dan PKI.
Semula, Sutan Sjahrir bersama Amir Sjarifuddin mendirikan PS (Partai Sosialis). Hanya dalam tempo singkat keduanya pecah kongsi.
Sjahrir mendirikan PSI (Partai Sosialis Indonesia) yang antikomunis, sedangkan Amir justru bergabung dengan PKI di bawah pimpinan Musso yang baru kembali dari Moskow. Musso adalah veteran PKI tahun 1920-an.
Sejarawan mendiang Soe Hok Gie menggambarkan hubungan Amir dan Sjahrir dalam ungkapan yang khas. Selama ini PS memiliki dua unsur yang saling bantu satu sama lain. Amir merupakan gas, sementara Sjahrir merupakan rem. PS kini berjalan tanpa rem, yang makin lama makin radikal. Akhirnya, PS terbawa arus yang mereka bangkitkan sendiri.
Sementara itu, PSI yang tidak (kurang) memiliki gas dalam perjuangan politik, akhirnya mandek serta kehilangan vitalitas dan keberanian dalam merintis pemikiran-pemikiran politik baru. (Lih Soe Hok Gie, Orang-Orang Di Persimpangan Kiri Jalan. Yogyakarta: Bentang, 2005, hlm. 174).
Bung Karno itu gas, Bung Hatta rem. Ketika gas tanpa rem, Bung Karno tidak bisa lagi mengendalikan kendaraannya. Nama kendaraan itu adalah Indonesia.
Tampaknya kongsi Amir-Sjahrir lebih bersifat pragmatisme politik, bukan ideologis. Jadi rapuh.
Ketika orang berbicara tentang Perundingan Linggarjati (1946) dan Perundingan Reinville (1947), yang sangat merugikan perjuangan Indonesia melawan kolonialisme, pelaku utamanya adalah Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan Perdana Menteri Amir Sjarifuddin, dua penganut Marxisme yang kemudian berpecah itu.
Fenomena gas dan rem ini terlihat pula pada hubungan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno itu gas, Bung Hatta rem. Ketika gas tanpa rem, Bung Karno tidak bisa lagi mengendalikan kendaraannya. Nama kendaraan itu adalah Indonesia.
Pada akhir 1956, Bung Hatta dengan kehendak sendiri meninggalkan posisinya sebagai wakil presiden setelah dijabatnya sejak Agustus 1945. Maka berlakulah apa yang berlaku. Legenda dwi tunggal berakhirlah sudah. Korbannya adalah Indonesia.
Becermin pada kejadian ini maka ke depan, kearifan pemimpin dari semua aliran politik amat sangat diperlukan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, apalagi untuk sebuah bangsa dan negara besar seperti Indonesia.
Bahwa Bung Karno dan Bung Hatta sangat mencintai negeri ini, tak seorang pun yang meragukan. Namun, mengapa keduanya harus bersimpang jalan pada saat Indonesia masih labil?
Kita lanjutkan membaca fenomena perpecahan parpol untuk masa yang belum terlalu jauh ke belakang. Ketika warna ideologi politik semakin kabur, perpecahan itu semakin mudah terjadi.
Idealisme politik di lingkungan budaya yang suka main kayu ini belum menemukan tanah subur di bumi Pancasila untuk tumbuh berkembang.
Masyumi sebagai parpol ideologis, buah dari kemerdekaan, hanya bertahan 15 tahun, kemudian menghilang selama 60 tahun. Bukan karena kehendak sendiri, melainkan dihantam palu godam sistem DT (Demokrasi Terpimpin, 1959-1966) dengan dukungan kuat PKI pada akhir 1960.
Masyumi muncul lagi awal November 2020, sebagaimana yang akan disinggung lagi nanti.
Di bagian akhir abad yang lalu, dalam tesis MA di Departemen Sejarah Universitas Ohio, saya menggambarkan nasib Masyumi ini sebagai berikut: “Sikap Masyumi melawan Sukarno dapat ditafsirkan seperti seseorang yang membenturkan kepalanya ke tembok tebal. Tapi, itulah yang dipilihnya demi demokrasi dan negara hukum.” (Lih. Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin, 1959-1965. Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 77). Masyumi telah martir untuk konstitusi dan demokrasi.
Karena usianya terlalu singkat, Masyumi tidak sempat mencetak kader penerus yang kuat dan matang secara ideologis. Di era DT yang minus demokrasi itu, hanya parpol pendukung sistem yang boleh bertahan.
Di luar itu, dicap sebagai parpol kontra revolusi yang mesti dihentikan hak hidupnya sesegera mungkin. Maka, pada akhir 1960, Masyumi dan PSI dipaksa mengembuskan napas terakhirnya.
Idealisme politik di lingkungan budaya yang suka main kayu ini belum menemukan tanah subur di bumi Pancasila untuk tumbuh berkembang.
Perlu juga dicatat, Masyumi adalah parpol modern yang umumnya dipimpin para negarawan-intelektual andal dengan penguasaan bahasa asing yang nyaris sempurna. Kualitas kenegarawanan mereka setanding dengan tokoh nasionalis lainnya.
Selama 15 tahun itu, Masyumi dipimpin Dr Soekiman Wirjosandjojo, Mohammad Natsir, dan Prawoto Mangkusasmito. Di tangan Prawotolah partai ini diperintahkan bubar oleh penguasa DT.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.