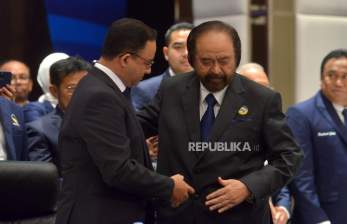Opini
Dilema Relasi Kuasa
Selain masalah kesehatan, sejumlah masalah ikutannya juga menjadi ujian nyata kepemimpinan Jokowi.
GUN GUN HERYANTO, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta
Kritik Presiden Jokowi dalam pidato di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni lalu, sontak memantik diskursus publik dan mulai mengaitkannya dengan potensi reshuffle.
Wacana ini mengemuka karena secara eksplisit dan tegas pernyataan Jokowi itu dibagikan ke khalayak. Ini artinya, setelah 10 hari dari peristiwanya, tepatnya 28 Juni, Jokowi memberi kode lewat kata dan tindakan kemarahannya bahwa line up menteri bisa berubah.
Seriuskah Jokowi dengan rencana reshuffle? Kalau melihat pola perombakan kabinet Jokowi pada periode pertama, ini sangat mungkin. Saat berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK), Jokowi melakukan empat kali bongkar pasang para menterinya.
Jokowi harus memasukkan variabel krisis sebagai pertimbangan utama karena realitasnya, bangsa dan negara sedang dihadapkan pada peliknya situasi pandemi.
Reshuffle pertama dilakukan Jokowi pada 12 Agustus 2015, yang kedua pada 27 Juli 2016, ketiga pada awal Januari 2018, dan keempat pada 15 Agustus 2018.
Membaca pola ini, saat Jokowi tak puas atau ada pertimbangan evaluasi kinerja dan politik yang mengharuskan perombakan, bukan hal aneh jika Jokowi melakukan reshuffle sebelum kabinetnya genap satu tahun berjalan.
Saat ini, situasinya sangat berbeda dengan periode pertama. Jokowi harus memasukkan variabel krisis sebagai pertimbangan utama karena realitasnya, bangsa dan negara sedang dihadapkan pada peliknya situasi pandemi.
Selain masalah kesehatan, sejumlah masalah ikutannya juga menjadi ujian nyata kepemimpinan Jokowi. Indikasi awal krisis ekonomi terlihat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2020.
Pada periode ini, pertumbuhan ekonomi hanya 2,97 persen, padahal dalam keadaan normal pertumbuhan selalu di atas lima persen. Tentu, bukan hanya Indonesia, pandemi Covid-19 telah membawa negara-negara di dunia ke jurang resesi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi, kinerja perekonomian hingga akhir tahun tumbuh di kisaran minus 0,4 persen hingga satu persen.
Angka tersebut jauh lebih rendah daripada proyeksi perekonomian skenario berat yang sebelumnya disebutkan, yakni perekonomian masih bisa tumbuh 2,3 persen hingga akhir tahun. Jadi, ada dua krisis utama saling berimpitan pada waktu bersamaan.
Merombak kabinet pada saat krisis mendera memang bukan momentum ideal.
Pertama, krisis kesehatan yang diakibatkan pandemi. Kedua, krisis ekonomi karena di tingkat domestik ataupun global, ekonomi mengalami kontraksi cukup, bahkan bisa sangat dalam. Di atmosfer krisis ini juga bermunculan krisis lain yang bersifat multidimensional, seperti krisis sosial, politik, bahkan kebudayaan. Singkatnya, secara substantif, isi pesan dan gestur kegundahan Jokowi di depan para menterinya wajar dan relevan. Jokowi wajib mengevaluasi kinerja menterinya, dan memastikan rentang kontrol berjalan efektif.
Merombak kabinet pada saat krisis mendera memang bukan momentum ideal. Biasanya, selain menimbulkan kegaduhan politik, juga belum tentu menteri baru bisa langsung klop dengan jajaran birokrat dan sistem di kementerian yang dipimpinnya.
Alih-alih melakukan akselerasi, yang ada malah bisa jadi menteri baru sibuk beradaptasi. Namun pada akhirnya, variabel krisislah yang harus menjadi pertimbangan.
Jika memang setelah dievaluasi ternyata menteri-menteri tertentu tak lagi bisa dilanjutkan dan berpotensi menambah masalah, konsep mengamputasi terkadang diperlukan daripada menunggu terjadinya pembusukan.
Sirkulasi elite
Jika akhirnya, Jokowi mengambil opsi merombak kabinetnya, jangan pilih orang yang “baru belajar” memahami kerja birokrasi, atau sekadar memperhatikan politik representasi. Jokowi sendiri sudah memberi pernyataan publik bahwa ini bukan situasi normal.
Memang, perombakan tidaklah sederhana. Sebab, dalam proses sirkulasi elite, biasanya yang paling sulit menuntaskan relasi kuasa antarkekuatan. Terutama jika yang mau dirombak adalah menteri-menteri yang disponsori partai politik.
Di sini, berlaku tesis Vilfredo Pareto dalam tulisannya The Circulation of the Elite (Dalam William D Perdue, 1986) yang mengingatkan, proses sirkulasi elite itu hubungannya resiprokal (timbal-balik) dan bersifat saling ketergantungan.
Mengganti atau mereposisi satu atau beberapa menteri biasanya diikuti bergeraknya perubahan sistem di kementerian yang diganti, ataupun dalam partai-partai pengusung kekuasaan.
Kemarahan Jokowi, jangan berhenti menjadi dramaturgi karena krisis tak cukup didekati hanya dengan basa-basi.
Pengalaman perombakan pertama pada periode Jokowi-JK, strateginya mereposisi beberapa menteri dari satu pos kementerian ke kementerian lain. Selain itu, mengganti menteri dari kalangan nonparpol. Pun demikian, reshuffle kedua pada Agustus 2016.
Jokowi mengeksplisitkan praktik akomodasi politik dengan memberi ruang bagi partai baru yang datang belakangan, yakni Golkar dan PAN. Singkatnya, pola dominannya adalah keseimbangan politik di partai-partai penyokong.
Pola ini harusnya berubah jika memang mau merombak kabinet pada musim pandemi. Anggaplah pernyataan marahnya Jokowi itu dijadikan prakondisi. Maka itu, basis penilaiannya pada performa kerja dan orientasi perubahan signifikan yang diharapkan.
Kemarahan Jokowi, jangan berhenti menjadi dramaturgi karena krisis tak cukup didekati hanya dengan basa-basi.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.